Jika Kalian menemukan Gambar Rusak / Terpotong / Tidak Terload Silahkan Lapor ke [chatango] atau [disini]

6.Arno Dan Aini
Bab: Pertemuan di Antara Bayang dan Pagi
Kabut tipis masih menggantung rendah di atas Alun-Alun Utara. Jalanan lengang, hanya beberapa pedagang kaki lima yang mulai menata dagangannya, ditemani suara burung yang kadang hilang, kadang muncul lagi dari balik pepohonan.
Aini duduk diam di bangku kayu, menggenggam buku catatan kecil yang sudah hampir penuh dengan coretan. Ia tidak menulis, hanya memandangi halaman kosong terakhir, seolah menunggu inspirasi yang belum mau datang.
Langkah pelan terdengar dari arah belakang. Aini tak perlu menoleh; langkah itu terlalu dikenal untuk disalahtebak.
“Pagi di Jogja selalu dingin buat orang yang nggak siap pulang,” suara itu datar, tapi lembut di ujungnya.
Aini tersenyum tipis tanpa menoleh. “Dan kamu masih nggak pernah siap pulang, ya, No?”
Arno tertawa pelan, duduk di sampingnya. “Pulang tuh… kadang bukan soal tempat. Kadang soal orang yang nungguin. Kalau nggak ada yang nunggu, apa masih bisa disebut pulang?”
Aini menoleh pelan, menatapnya sebentar, lalu kembali ke bukunya. “Filosofis banget pagi-pagi. Kurang tidur?”
“Bisa jadi. Bisa juga kebanyakan mikir.”
—
Mereka diam sebentar, hanya mendengar suara sepeda ontel lewat di kejauhan.
Aini akhirnya berkata, “Kamu ke mana aja? Tiba-tiba ilang kayak batu dilempar ke sumur.”
Arno menatap ke depan, ke arah pohon beringin besar di tengah alun-alun.
“Ke tempat-tempat yang bahkan aku sendiri nggak yakin kenapa harus ke sana. Kadang cuma… nyari tenang. Meski jarang ketemu.”
Aini tertawa kecil, nadanya lembut. “Kamu tuh kayak radio rusak, No. Kadang dapet sinyal, kadang enggak.”
Arno ikut tertawa. “Ya, yang penting masih bisa nyala walau suaranya kresek-kresek.”
—
Mereka terdiam lagi, tapi tidak canggung.
Aini akhirnya berkata pelan, “Kamu sadar nggak sih… dunia tuh kayak nggak peduli kita capek. Pas kita berhenti, dia tetap jalan terus. Pas kita nangis, orang lain tetep ketawa.”
Arno mengangguk. “Iya. Tapi justru itu bagus. Artinya kita nggak harus ngatur semuanya. Tinggal pilih: mau ikut ketawa atau diem sebentar sampai kuat lagi.”
Aini menatapnya lama. “Kamu berubah. Dulu kamu selalu nyuruh aku lari kalau capek.”
Arno menghela napas pendek. “Mungkin dulu aku juga lagi lari. Sekarang… aku lagi berhenti sebentar.”
—
Aini tertawa kecil, menepuk pundaknya pelan. “Cieee… Arno yang sekarang ngomongnya bijak banget. Ini beneran Arno atau udah diganti sama yang lebih kalem?”
Arno pura-pura menatapnya serius. “Jangan-jangan aku ini alien, Nin. Cuma kamu yang belum sadar.”
Aini memutar bola matanya sambil tersenyum. “Kalau kamu alien, pasti Jogja udah kebakar dari kemarin-kemarin gara-gara kamu panik.”
Mereka tertawa bersama. Ringan. Tanpa bayangan pertanyaan rumit. Seperti dua teman lama yang cuma butuh secuil pagi untuk merasa hidup.
—
Aini akhirnya membuka buku catatannya lagi.
“Hari ini aku mau cek ke Terban. Ada laporan listrik padam aneh. Kayaknya nggak cuma korsleting biasa.”
Arno melirik sebentar. “Sendiri?”
“Ya siapa lagi? Kamu mau ikut?”
Arno mengangguk pelan, tersenyum. “Kalau kamu mau ditemenin, aku ikut.”
Aini tertawa kecil. “Aku minta temen, bukan bodyguard.”
“Tenang. Aku bukan bodyguard. Aku cuma orang yang lagi belajar jalan pelan-pelan di dunia yang ngebut.”
Aini mengangguk, matanya teduh.
“Yaudah, ayo. Sebelum dunia keburu bangun.”
—
Mereka bangkit dari bangku tua itu, berjalan berdampingan melewati jalanan yang masih kosong. Sepatu mereka beradu pelan dengan paving alun-alun yang basah sisa embun pagi.
Mereka tidak membicarakan kekuatan, tidak membicarakan rahasia besar. Hanya berjalan, membiarkan dunia tetap menjadi teka-teki yang belum perlu dijawab hari ini.
Karena kadang, menjadi biasa… adalah pelarian terbaik dari hidup yang terlalu luar biasa.
—
Bab: Di Balik Listrik Padam
Pagi itu di Terban, suasana masih seperti biasa: warung bubur ayam mulai buka, suara radio tua memutar berita pagi, dan ibu-ibu menyapu halaman dengan santai. Hanya satu hal yang membuat pagi itu terasa janggal-sejumlah rumah masih gelap, padahal jam sudah menunjukkan lewat pukul tujuh.
Aini dan Arno berdiri di pinggir jalan sempit, berdampingan namun masih canggung. Mereka sudah beberapa kali bertemu kembali sejak lama berpisah setelah SMP, tapi ini adalah perjalanan pertama mereka menyelidiki sesuatu bersama.
Aini membuka buku catatannya. “Secara teknis, listrik padam di satu kampung bisa karena trafo atau kabel bawah tanah rusak. Tapi ini… jaringan utamanya normal.”
Arno menatap tiang listrik sebentar, lalu melirik ke arah sumur tua yang terletak tak jauh dari situ.
“Kadang masalahnya nggak kelihatan di atas tanah,” katanya datar. “Mungkin kita harus lihat ke bawah.”
Aini mengangkat alis. “Ke bawah?”
Arno hanya tersenyum tipis. “Sumur kadang lebih jujur daripada kabel.”
Mereka mendekati sumur tua yang ditutupi pagar kayu reot. Suara denging samar terdengar jika berdiri cukup dekat, seperti getaran kawat halus yang tertarik terus-menerus.
Aini berjongkok, menyorotkan senter ke dalamnya. Hanya gelap dan dinding batu tua yang tampak.
“Dulu aku pikir suara sumur paling seram tuh air netes-netes. Ternyata bisa ada suara begini juga…” gumamnya.
Arno berdiri tak jauh di belakang, memejamkan mata sejenak. Ada rasa aneh yang menyusup dari dalam dirinya-bayangan Svarnavarna yang selama ini bersemayam di tubuhnya bergetar perlahan, seperti merespons sesuatu.
Dan saat itu, suara dingin itu muncul.
Svarnavarna (datar, tajam):
> “Kau merasakannya juga, bocah? Ada bayangan lain di sini… yang bermain-main dengan arus listrik.”
Arno menggeram pelan, menjawab dalam hati.
“Siapa? Apa dia berbahaya?”
Svarnavarna (ringan, seolah mengejek):
“Tentu saja berbahaya. Tapi bukan untuk mereka yang kuat. Pertanyaannya, kau cukup kuat, atau tidak?”
Arno menarik napas perlahan, lalu berkata ke Aini dengan tenang. “Aku cek ke sekeliling dulu. Kamu tunggu di sini sebentar, ya.”
Aini mengangguk santai. “Oke, tapi jangan lama-lama. Bukan sumur doang yang seram, gang sini juga sepi.”
—
Tak jauh dari sumur, di balik tembok bata yang ditumbuhi lumut, Arno menemukan sesuatu yang lebih aneh: bekas kabel terbakar, tapi bekasnya seperti terbakar dari dalam, hitam dan berbau seperti logam hangus. Di sudut gelap gang, ia melihat sekilas-sesuatu bergerak cepat seperti kilatan hitam, melesat tanpa suara.
Svarnavarna berbisik tajam:
“Itu entitas lain. Yang bermain dengan arus, tapi membungkusnya dengan kegelapan.”
Arno mengerutkan kening. Tanpa sadar, ia mengaktifkan sebagian bayangan dalam dirinya. Tubuhnya terasa dingin sebentar, seperti ada kabut hitam tipis yang melapisi kulitnya. Bukan untuk bertarung, hanya untuk berjaga.
Kilatan hitam itu muncul lagi. Bentuknya menyerupai manusia, tapi kabur, seolah tersusun dari listrik liar yang terkontaminasi sesuatu yang gelap.
Arno mengangkat tangannya perlahan, menenangkan dirinya.
Arno (berbisik):
“Aku nggak datang buat cari ribut.”
Bayangan itu hanya bergetar, seolah mengamati, lalu perlahan memudar, menyerap kembali ke tanah, menembus jalur kabel yang tersembunyi di bawah kota.
Svarnavarna tertawa pelan:
“Dia belum siap bertemu. Tapi ia akan kembali. Kau tahu, Jogja nggak pernah kekurangan makhluk lapar.”
—
Saat Arno kembali ke sumur, napasnya sudah stabil. Aini masih di sana, berdiri sambil merapikan catatannya.
“Gimana?” tanya Aini.
“Kayaknya cuma korsleting bawah tanah. Nanti kita lapor PLN biar dicek,” jawab Arno santai, tak menunjukkan apa pun yang sebenarnya ia temui.
Aini menghela napas, sedikit kecewa. “Kupikir bakal ada yang lebih… dramatis.”
Arno tersenyum kecil. “Dramatis tuh biasanya cuma di kepala kita. Yang bahaya justru diem-diem aja.”
Aini tertawa kecil. “Kamu masih suka ngomong kayak gitu ya? Dari dulu nggak berubah.”
Arno menatap jalan yang mulai ramai. “Mungkin Jogja-nya yang nggak banyak berubah. Jadi kita juga masih kayak dulu.”
Aini menatapnya, tersenyum samar. “Makasih ya udah nemenin. Baru pertama nih kita jalan bareng lagi setelah lama. Biasanya cuma ketemu bentar terus sibuk sendiri-sendiri.”
“Ya, akhirnya sempat juga,” jawab Arno ringan.
“Yuk, cari sarapan. Aku belum makan dari pagi.”
Arno tertawa kecil. “Deal. Tempat bubur enak masih buka kok. Kali ini aku yang traktir.”
“Wajib,” kata Aini sambil menutup bukunya.
Mereka berjalan beriringan meninggalkan sumur tua yang kembali diam. Tak ada yang tahu bahwa jauh di bawah sana, sesuatu masih bergerak… menyerap… menunggu… tumbuh lebih kuat.
Svarnavarna berbisik perlahan sebelum menghilang dari benaknya:
“Bersiaplah bocah. Mungkin sekarang dia menghindarimu..tapi kelak, jalan kalian akan bersinggungan. Siap atau tidak, waktunya tetap datang.”
Tapi untuk pagi ini, Arno memilih menunda semua itu.
Hari ini, ia hanya ingin duduk tenang, menyantap bubur, menyeruput kopi hitam, dan untuk sejenak, merasa… biasa.
Bab: Pertemuan yang Tidak Direncanakan
Warung bubur di pojokan jalan itu masih lengang pagi itu. Bau kaldu ayam dan taburan bawang goreng mengisi udara, bercampur wangi kopi hitam yang mengepul dari cangkir-cangkir sederhana.
Arno dan Aini duduk berseberangan, menikmati bubur panas di tengah obrolan ringan tentang berita dan kejadian-kejadian aneh yang mereka temui pagi itu. Tawa mereka tidak keras, hanya sepotong jeda di antara keheningan kota yang perlahan mulai hidup.
Seseorang menarik kursi di meja sebelah mereka, gerakannya tenang tapi mantap.
“Permisi, boleh nebeng duduk? Sepagi ini kok suasananya menarik sekali buat ngobrol,” suara itu terdengar ramah, dengan logat Jawa yang sedikit kaku, seperti seseorang yang masih menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya.
Arno menoleh. Lelaki itu berperawakan tegap, mengenakan jaket lusuh dan celana jeans, dengan wajah lelah namun waspada. Tatapannya jeli, seperti orang yang terbiasa membaca situasi. Namanya tak terucap, tapi Arno mengenalinya dari berita internal kepolisian yang sempat ia dengar sekilas di radio: Jono, polisi dari Semarang yang baru pindah tugas ke Jogja beberapa hari lalu.
“Tentu saja, Pak. Silakan duduk,” kata Arno sopan.
Aini menoleh, sedikit bingung, karena tidak mengenali pria itu. Tapi ia ikut tersenyum sopan.
Jono duduk, meletakkan topinya di meja, lalu memesan secangkir kopi. Ia mengamati mereka berdua sebentar sebelum akhirnya bertanya.
“Maaf, saya baru beberapa hari di sini. Nama saya Jono, dari Polsek Kota. Tadi sempat dengar kalian ngobrol soal sumur tua? Kebetulan saya lagi cari informasi soal gangguan listrik di Terban.”
Aini mengangguk pelan. “Saya Aini, wartawan lepas. Pagi ini kami memang sempat lihat sumur tua yang aneh itu. Kebetulan, listrik padam di sekitar situ, dan ada suara denging dari sumurnya.”
Jono mengerutkan kening, tertarik. “Denging dari sumur? Itu yang saya dengar juga dari laporan warga Wirobrajan. Katanya, ada suara yang nggak biasa di bawah tanah. Tapi saya belum sempat cek langsung.”
Ia berpaling ke Arno. “Kalau masnya?”
“Arno,” jawab Arno singkat. “Saya warga lama sini, baru-baru ini balik lagi ke Jogja. Tadi ikut menemani Aini sekadar memastikan. Kami nggak menemukan apa-apa yang jelas, cuma sumur tua yang masih berdengung… agak aneh memang.”
Jono menatap keduanya, mengangguk pelan.
“Menarik. Karena semalam juga ada laporan lampu jalan meledak di Bumijo tanpa sebab. Tidak ada petir, kabel pun katanya utuh. Rasanya seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah kota, tapi belum bisa saya pastikan apa.”
Aini mencatat hal itu cepat-cepat di buku kecilnya, lalu menatap Jono.
“Jadi Bapak baru pindah dari Semarang, ya?”
Jono tertawa kecil. “Iya, baru beberapa hari. Jogja ini tenang di permukaan, tapi dalamnya… saya rasa ada yang nggak beres.”
Arno tersenyum tipis. “Kota ini memang penuh kejutan. Kadang sumur tua lebih banyak rahasia daripada kantor polisi.”
Jono ikut tertawa, lalu menyeruput kopinya.
“Kalau kalian nemu yang aneh-aneh, kabari saya. Kita nggak bisa biarin gangguan kayak gini dibiarkan terlalu lama. Kadang yang kecil-kecil justru bahaya.”
Angin pagi berhembus perlahan, membawa aroma bubur hangat dan suara burung dari kejauhan.
Untuk sejenak, mereka bertiga hanya duduk dalam diam yang tenang, saling membaca situasi.
Tapi masing-masing tahu:
Pagi itu hanya awal.
Di bawah kota, sesuatu sedang bergerak.
—
Bab: Dalam Gelap yang Menunggu
Namanya Guntur. Usianya sekitar dua puluh empat tahun. Hidupnya pas-pasan di Sayidan, pinggir Kali Code yang tenang di siang hari tapi bisa berubah ganas saat hujan dari utara turun deras. Ia anak tunggal, yatim sejak kecil, ibunya hanya penjual nasi gudeg keliling yang wafat karena sakit paru-paru bertahun-tahun lalu. Sejak itu, hidupnya cuma soal bertahan: jadi tukang listrik keliling yang dipanggil orang kampung buat pasang saklar, betulin radio tabung, atau nyambung kabel-kabel rusak di rumah-rumah tua.
Tapi jadi tukang listrik kampung bukan cita-cita hidupnya. Bukan pula hidup yang ia bayangkan waktu kecil dulu. Ia ingin lebih. Ingin dikenal, dihormati, bukan cuma dipanggil kalau ada kabel putus lalu dilupakan begitu saja.
Malam itu, setelah memperbaiki colokan rusak di rumah Pakde Sastro-yang malah membentaknya karena minta ongkos lebih seratus rupiah-Guntur berjalan menyusuri gang kecil yang hanya diterangi lampu petromaks redup. Kepalanya masih panas, pikirannya penuh sumpah serapah yang tak ia keluarkan.
Saat itulah, ia mendengar suara aneh. Bukan suara jangkrik, bukan pula bunyi korsleting biasa. Lebih seperti dengungan kawat yang tegang, halus, tapi dalam, seolah memanggil.
Ia berhenti. Napasnya tertahan.
Di ujung gang yang gelap, muncul semacam asap hitam berkilat samar, bergetar seperti api yang mati-matian bertahan hidup di malam basah. Kilatan itu tidak terang seperti listrik biasa, melainkan gelap-seperti bayangan yang hidup.
Guntur menegang, keringat dingin merayap di punggungnya. Ia mundur selangkah.
Lalu, suara itu muncul. Bukan terdengar di udara, tapi langsung di benaknya-dingin, perlahan, dan berat seperti besi tua.
Suara:
“Kau lelah… kau marah… kau ingin didengar. Izinkan aku menyalakan apa yang sudah lama padam dalam dirimu.”
Guntur merapatkan jaketnya. “Siapa kamu? Mau apa kamu dari aku?”
Bayangan itu berputar perlahan, suara dengingnya menebal.
Suara:
“Aku… adalah bagian yang tertolak. Sama seperti kau yang ditolak dunia. Aku adalah kekosongan yang mencari rumah.”
Guntur mengatupkan rahang, menahan amarah yang lama ia kubur. “Aku hidup karena kerja keras, bukan karena… kegelapan kayak kamu.”
Suara itu tertawa kecil, getir, seperti suara kawat yang digesek kasar.
Suara:
“Kerja kerasmu dihargai berapa? Seratus rupiah? Satu terima kasih pun tak kau dapat. Dunia tak akan memberi tempat untuk orang kecil yang sabar.”
Guntur terdiam. Teringat semua penghinaan kecil yang ia telan diam-diam. Teringat bagaimana orang kampung hanya memanggilnya saat butuh, lalu melupakannya esok hari.
Dengan suara pelan, ia bertanya, “Kalau aku terima kamu… apa yang akan terjadi?”
Bayangan itu mendekat perlahan, hampir menyentuh wajahnya.
Suara:
“Kau akan punya kekuatan. Mereka akan berhenti meremehkanmu. Dan kau… takkan pernah sendiri lagi.”
Hening beberapa saat. Guntur menggertakkan gigi. Dalam dadanya, perlawanan masih ada, tapi lelahnya jauh lebih kuat.
Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata tegas,
“Baik. Tapi aku yang memegang kendali.”
Bayangan itu tampak bergetar pelan, seperti tertawa puas.
Suara:
“Kesepakatan.”
Dan dalam sekejap, bayangan itu melesat masuk ke tubuhnya-dingin seperti logam basah, tajam seperti arus liar. Tubuh Guntur gemetar. Mata kirinya berpendar redup, dadanya seperti dihantam gelombang listrik yang tak ia mengerti.
Malam itu, tanpa saksi mata, seorang pemuda biasa mulai berubah.
Dan di dadanya, suara itu tetap berbisik:
“Aku bukan pemimpinmu. Aku adalah luka yang kau rawat sendiri.”
Bab: Gelap yang Menyala
Malam itu di Sayidan masih sunyi. Hanya suara riak Kali Code yang perlahan menyapa tepi rumah-rumah kayu. Guntur berdiri diam, mencoba merasakan apa yang baru saja terjadi pada tubuhnya.
Tangannya bergetar pelan. Ia mengangkatnya ke depan wajah. Dari ujung jemarinya, kilatan hitam samar muncul seperti bayangan yang menyala. Bukan panas seperti listrik biasa, tapi dingin-seperti arus yang melewati tulang-tulangnya tanpa membakar, hanya menyisakan sensasi kosong yang menggetarkan.
Suara itu-Petrawala-kini tidak hanya berbisik, tapi menyatu dalam pikirannya, berbicara dengan nada tenang namun tajam.
Petrawala:
“Tubuhmu masih lemah, tapi perlahan akan terbiasa. Energi dunia ini… terlalu padat oleh keteraturan. Kau dan aku akan membelahnya.”
Guntur menarik napas kasar, menahan pusing yang mulai menyerang kepalanya.
“Apa maumu sebenarnya?”
Petrawala:
“Aku ingin bertahan hidup. Di tempat asalku, aku diburu. Di sini, aku bebas-selama tubuhmu cukup kuat menahan aku.”
Guntur mengepalkan tangan.
“Aku bukan wadah kosong. Kalau mau hidup di sini, jangan atur aku.”
Petrawala tertawa pelan, seperti suara listrik liar yang menari di udara.
“Baik. Tapi ingat, kekuatan seperti ini… selalu menuntut harga. Dan harga itu bukan uang.”
Guntur menghela napas berat. Dunia yang ia kenal baru saja runtuh malam itu.
—
Keesokan Harinya:
Guntur bangun dengan kepala berat, tapi tubuhnya terasa lebih ringan. Seolah-olah beban hidup yang biasa ia tanggung… kini dibagi dengan sesuatu yang tak kasatmata.
Di luar, kabut tipis menutupi Kali Code. Orang-orang mulai beraktivitas, namun Guntur merasa… berbeda. Jalanan yang dulu biasa ia lalui, kini seperti penuh dengan suara samar-dengungan listrik bawah tanah, detak arus di balik dinding rumah, dan bisikan energi yang mengalir diam-diam.
Petrawala masih diam di dalam pikirannya, hanya sesekali berbisik lirih.
“Cobalah… uji kekuatanmu… lihat apa yang bisa kau kendalikan.”
Tapi Guntur memilih berjalan biasa. Ia belum siap menunjukkan apapun. Dunia belum tahu apa yang baru saja bangkit di Sayidan.
—
Sementara Itu, di Tempat Lain
Arno yang masih bersama Aini belum menyadari bahwa gelombang energi baru telah muncul di sisi lain kota.
Svarnavarna, yang terdiam dalam bayangan Arno, perlahan membuka matanya.
Ia merasakan getaran yang tak asing.
Svarnavarna (dalam hati):
“Petrawala…? Jadi kau masih hidup… Dunia ini akan terlalu kecil untuk dua kekuatan seperti kita.”
Dan pertarungan yang tak kasat mata itu… baru saja dimulai.
—
Bab: Persimpangan yang Semakin Ramai
Siang itu, panas khas Jogja terasa menggigit, bahkan di bawah rindangnya pohon asam di dekat perempatan Terban. Aini dan Arno baru saja selesai mewawancarai warga soal padamnya listrik yang masih belum jelas penyebabnya. Mereka berjalan santai menuju warung es dawet di pojok jalan, mencoba meredakan panas kepala dan panas cuaca sekaligus.
Saat mereka baru saja duduk, seseorang mendekat dengan langkah santai.
“Wah, ketemu lagi. Rupanya kalian belum kapok muter-muter cari jawaban,” sapa suara yang sudah mereka kenal.
Aini menoleh dan tersenyum. “Pak Jono, siang-siang begini masih patroli?”
Jono tertawa pelan, duduk tanpa sungkan di bangku kosong. “Patroli perut, Mbak Aini. Lapar lebih bahaya daripada maling listrik.”
Arno ikut tersenyum. “Sendirian, Pak?”
“Ya, beginilah. Anak baru di Jogja, belum banyak teman. Paling temannya cuma warung sama bapak-bapak ronda,” jawab Jono sambil memesan es dawet pada penjaja yang lewat.
Aini mencondongkan tubuh sedikit. “Jadi, sudah ada kabar baru soal listrik padam itu?”
Jono menghela napas, wajahnya agak serius. “Belum ada jawaban yang enak didengar. PLN bilang jaringannya aman. Tapi semalam ada laporan baru dari Bintaran, dua rumah mendadak korsleting bareng, padahal alat-alatnya baru semua.”
Arno mengerutkan dahi. “Padahal itu daerah pusat kota, ya? Harusnya aman.”
Jono mengangguk. “Makanya saya mulai mikir, ini bukan cuma soal alat atau jaringan. Mungkin ada… yang lain.”
Aini tersenyum samar, tapi tak ingin langsung melontarkan spekulasi. “Maksudnya, yang lain itu apa, Pak?”
Jono menatap keduanya sejenak, lalu tertawa kecil. “Ah, saya cuma ngelantur. Paling juga bocah iseng atau orang pinter yang lagi eksperimen aneh-aneh.”
Arno tersenyum tipis. “Kadang yang kelihatan iseng, justru yang paling bahaya.”
Jono menyandarkan punggung ke kursi kayu. “Nah, itu. Saya baru pindah ke Jogja, tapi rasanya kota ini nggak segampang yang saya kira. Di Semarang, maling ya maling, rampok ya rampok. Di sini… bayangan bisa ngomong, suara bisa muncul dari sumur. Kalian percaya begituan?”
Aini tertawa pelan, mencoba meredakan suasana. “Kami percaya data, Pak. Tapi kalau datanya aneh, ya mau tak mau kita cari ceritanya juga.”
Jono mengangguk pelan. “Fair point, Mbak.”
Es dawet mereka datang. Tiga gelas sederhana dengan warna hijau dan santan yang menggoda di siang terik itu. Mereka diam sejenak, menikmati minuman masing-masing.
Setelah beberapa tegukan, Arno bertanya pelan. “Kalau misalnya kami nemu sesuatu yang… mungkin nggak bisa dijelaskan ke kantor polisi dengan kata-kata biasa, Pak Jono kira-kira bakal dengerin nggak?”
Jono menatapnya dengan mata yang lebih serius, tapi tetap tenang. “Dengerin sih pasti. Tapi percaya atau nggaknya, ya lihat nanti. Yang penting kita cari jalan keluar sama-sama, bukan saling nutup telinga.”
Aini tersenyum lega mendengar itu. “Baiklah, Pak. Kalau begitu… semoga Jogja ini tetap terang, ya. Walau jalannya kadang gelap.”
Jono tertawa pelan. “Kalau semua terang, kerja saya nganggur.”
Mereka bertiga tertawa kecil, membiarkan siang Jogja yang panas terasa sedikit lebih ringan.




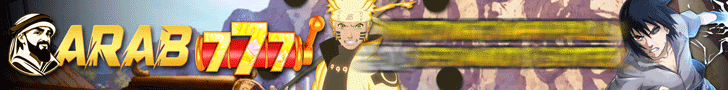
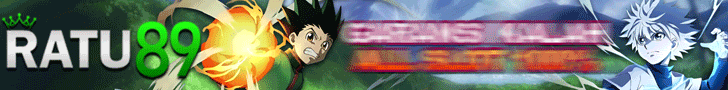



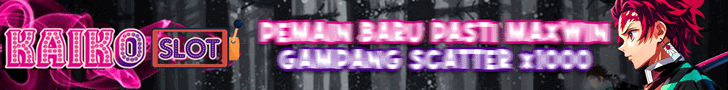

Comment