Jika Kalian menemukan Gambar Rusak / Terpotong / Tidak Terload Silahkan Lapor ke [chatango] atau [disini]

5.Setelah semua tenang
Bab: Di Tempat Segalanya Dimulai
Pagi yang dingin dan lembab masih menyelimuti dusun ketika Romo Seto tiba lebih dulu di sana.
Lalu beberapa orang datang menghampiri Romo Seto mengabarkan bahwa gadis wartawan itu berada di Rumah salah satu warga. Tanpa menunggu lama dengan rasa lelah yang masih menggantung di tubuhnya, ia melangkahkan kakinya mengikuti beberapa orang itu menuju tempat dimana Aini berada.
Sesampainya disana Romo Seto menemukan Aini di ruang depan rumah kayu itu, Aini terbaring di atas dipan bambu dengan wajah pucat dan napas yang masih berat. Matanya tetap terpejam, tubuhnya lemah, namun setidaknya ia kembali dalam keadaan hidup.
Romo Seto duduk di sisi dipan, menggenggam tangan Aini yang dingin dan lembab. Wajahnya lelah, namun sorot matanya menyimpan syukur yang dalam.
Pak Kandar, pemilik rumah itu, berdiri tak jauh di belakang, wajahnya masih diliputi heran. “Romo… saya temukan dia tergeletak di depan pintu sebelum subuh. Tidak ada jejak orang lain, tidak ada suara langkah. Seolah-olah… dia diletakkan dengan hati-hati, lalu orangnya pergi begitu saja.”
Romo Seto menoleh lalu berujar pelan hampir tidak terdengar.
“Mungkin orang itu juga lah yang membantu kita menutup titik api di sana.. Tapi siapapun dia kita harus bersyukur karena tangan Tuhan memakai dia untuk menolong kita”
Pandangan Romo Seto kembali ke Aini. Ada doa dalam hatinya.
“Syukurlah nak Aini.. Siapapun orang itu yang terpenting kini kamu selamat.”
Romo Seto menarik napas panjang, memandang keluar jendela yang masih berkabut. “Mungkin yang membawanya memang tak ingin dikenal. Yang penting Aini selamat.”
Tak lama kemudian, Pak Parman, Ki Prayitno, dan Mbah Suro tiba dengan langkah berat, masih menyisakan kelelahan malam sebelumnya. Mereka terdiam sejenak, memandangi Aini yang terbaring, lalu duduk di sekelilingnya, membiarkan keheningan menjadi penyambut pertama mereka.
Pak Parman akhirnya bicara, suaranya berat tapi tulus, “Kita semua selamat. Dan dia pun kembali.”
Ki Prayitno mulai menceritakan tentang Haryo, pria bermulut lebar dengan candaan yang datang di saat paling tak tepat, namun justru menjadi kunci di patahan batu. Mbah Suro melanjutkan, menceritakan bagaimana Haryo menahan retakan seperti sedang bermain-main dengan api purba.
Pak Parman dan Romo Seto lalu bercerita tentang Pura, pria kurus yang muncul tiba-tiba di Wonosadi. Tenang, terang, dan membawa ilmu yang mampu menenangkan titik api tanpa banyak bicara.
Tapi keduanya, Haryo dan Pura, menghilang begitu saja setelah semua selesai. Tanpa pamit, tanpa jejak.
Tak lama, beberapa warga berdatangan ke rumah Pak Kandar, membawa kabar dan kecemasan mereka.
“Romo, semalam kami lihat kilat-kilat hitam kemerahan dari arah lereng Merapi… seperti petir tapi membelah tanah,” kata Pak Karno, petani tua yang tinggal di tepi dusun.
“Tanah bergetar keras, Romo, seperti ada sesuatu yang bangkit dari bawah bumi. Bahkan sumur saya sempat berbunyi seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya!” tambah Pak Slamet.
“Dan… ledakan! Kami dengar ledakan keras dari arah barat daya. Bukan letusan gunung, suaranya seperti batu retak, lalu… hening lagi. Tapi tidak ada longsor,” timpal yang lain.
Semua suara itu berputar di ruang kecil itu, menumpuk menjadi satu pertanyaan besar yang menggantung tanpa jawaban pasti.
“Apa yang sebenarnya terjadi, Romo? Dan siapa yang menutup titik pertama itu? Kami tahu di sana sudah terbuka beberapa hari… tapi pagi ini, tanahnya tertutup lagi, tak ada jejak api sama sekali,” tanya Pak Wiryo, heran.
Romo Seto tersenyum tipis, memandang Aini yang masih tertidur lemah.
“Kadang kita tak perlu tahu semua jawabannya, Pak Wiryo. Yang penting kita tahu: kita masih hidup, dan bahaya itu, untuk sementara, sudah berlalu.”
Ki Prayitno mengangguk pelan. “Mungkin suatu hari nanti kita akan bertemu lagi dengan mereka yang membantu kita. Atau mungkin tidak. Tapi semalam, jelas kita bukan satu-satunya yang bergerak.”
Angin pagi berhembus pelan, melewati jendela tua, membawa sisa-sisa kabut yang perlahan menipis. Dan di sana, di tempat segalanya dimulai, mereka duduk dalam diam, mencoba memahami makna dari malam yang baru saja mereka lewati.
Bab: Kasus yang Salah, Kota yang Benar
Pagi di Yogyakarta tahun 1983 bergerak pelan tapi pasti, membangunkan jalanan dari Tugu sampai ke Kotagede, dari Pasar Ngasem yang baru buka hingga Stasiun Lempuyangan yang mulai sibuk. Matahari menebar cahaya hangat, menyinari deretan becak, pedagang angkringan, dan pegawai negeri yang buru-buru ke kantornya.
Di salah satu sudut kota, tepatnya di kawasan Gondomanan, seorang pria berdiri di bawah papan nama warung makan sederhana, menyesap kopi hitam dengan wajah penuh tanya. Namanya Jono, detektif yang baru saja dipindahkan dari Semarang ke Jogja. Orang mengenalnya bukan karena kepintaran luar biasa, tapi karena keberuntungannya yang sering tak masuk akal. Kasus-kasus yang ia pecahkan lebih sering terselesaikan karena kebetulan yang tepat, bukan metode yang rumit.
Tugas pertamanya di Jogja jauh dari heroik. Ia tengah menyelidiki kasus pencurian alat listrik dari gudang PLN di daerah Klitren dan Baciro. Kasus yang remeh, tapi tetap harus ditangani. Dari pagi, ia sudah mewawancarai satpam yang mengantuk, tukang becak yang pura-pura tak tahu apa-apa, dan pedagang rokok di emperan Jalan Solo yang lebih sibuk membicarakan skor pertandingan sepak bola.
Namun, di sela-sela itu, cerita lain mulai terdengar. Tukang becak, pedagang batik, sampai pegawai kelurahan, ramai membicarakan tentang semalam: kilatan cahaya merah kehitaman di langit utara, suara dentuman dari arah Merapi, dan tanah yang katanya sempat bergetar.
Seorang penjaga sekolah di Kotabaru berkata sambil menyapu halaman, “Semalam saya kira itu uji coba meriam. Tapi kok Merapi ya, Pak? Nggak biasanya ada suara begitu dari sana.”
Jono cuma mengangguk malas. “Merapi ya Merapi, saya sih ngejar maling kabel, bukan ngejar setan.”
Ia menuliskan catatan kecil, bukan karena tertarik, tapi karena naluri detektifnya merasa segala hal aneh layak dicatat. Tapi dalam hatinya, ia tetap fokus: kasusnya hanyalah soal kabel listrik yang hilang. Urusan Merapi biarlah orang-orang gunung yang mikirin.
Motor bututnya meraung pelan saat ia menyusuri Jalan Kaliurang, bukan ke arah gunung, tapi ke arah selatan, menuju gudang PLN tempat laporan awal dibuat. Ia hanya sesekali menoleh ke utara, ke arah puncak Merapi yang masih diselimuti kabut tipis.
“Orang Jogja aneh-aneh. Kabel ilang dikait-kaitin sama gunung. Lha wong malingnya paling-paling ya butuh beli rokok,” gumamnya sambil tertawa kecil.
Jono mungkin lucu, mungkin sembrono, tapi instingnya tahu: kadang yang terlihat paling sederhana justru menyimpan banyak teka-teki. Dan meskipun ia tak tahu apa yang benar-benar terjadi di Merapi, ia sadar: Jogja bukan kota biasa.
Dan mungkin, kasus kabelnya pun akan berujung ke hal yang tak terduga. Tapi untuk sekarang, satu-satunya yang ia kejar hanyalah pencuri alat listrik, bukan cahaya merah di langit malam.
Bab: Percakapan di Antara Kabel yang Hilang
Gudang PLN di Baciro pagi itu tampak seperti lokasi yang baru saja bangun dari tidur panjang. Beberapa petugas sibuk mondar-mandir, mencatat, mengecek pintu belakang yang dirusak, sementara seorang mandor tua tampak duduk lesu di depan kantor kecil dengan segelas teh yang sudah dingin.
Jono tiba dengan motor bututnya, remnya berdecit pelan saat berhenti di depan gerbang yang sedikit miring akibat semalam dipaksa paksa. Helmnya masih menempel di kepala, jaketnya kusut, tapi matanya awas.
Seorang petugas keamanan, masih muda, menghampirinya. “Pak, dari kepolisian ya?”
Jono mengangguk, membuka helmnya sambil mengusap rambutnya yang acak-acakan. “Iya, saya Jono. Baru pindahan. Yang laporan kehilangan kabel siapa?”
Petugas menunjuk ke arah mandor tua yang duduk sambil mengelus kepala. “Pak Gito, yang nemuin pertama kali pas mau buka gudang subuh tadi.”
Jono melangkah santai, menyapa Pak Gito dengan senyum lebar. “Pak Gito ya? Saya Jono. Gimana ceritanya, Pak? Kabel ilangnya sejak kapan?”
Pak Gito mendesah panjang, seperti orang yang sudah terlalu lelah untuk marah. “Semalam gudang dikunci seperti biasa, Pak. Satpam terakhir ronda jam sepuluh malam, nggak ada yang aneh. Pagi-pagi pas saya buka, pintu belakang udah rusak, gemboknya dilempar ke got, dan kabel-kabel itu… hilang begitu saja. Yang hilang bukan cuma kabel, Pak. Ada alat sambungan listrik yang baru datang minggu lalu juga lenyap.”
Jono mencatat sambil mendengarkan. “Ada jejak sepatu, bekas ban, atau apalah itu?”
Pak Gito menggeleng. “Aneh, Pak. Tanah becek tapi bersih. Nggak ada bekas kaki, nggak ada bekas roda.”
Jono berhenti menulis, menatap Pak Gito tajam tapi tetap santai. “Lho, kalau maling biasa pasti ninggalin jejak, Pak. Kecuali malingnya terbang.”
Pak Gito hanya bisa mengangkat bahu, pasrah.
Di tengah-tengah percakapan itu, terdengar suara langkah sepatu berat mendekat. Seorang pria berkumis tebal dengan wajah serius muncul di belakang Jono. Itu Sidik, atasannya.
“Jon, bagaimana?” tanya Sidik tanpa basa-basi.
“Masih aneh, Pak. Barang ilang, pintu rusak, tapi jejaknya bersih kayak disapu malaikat.”
Sidik mendengus. “Jangan main-main. Cek lingkungan sekitar. Siapa tahu malingnya pinter nutup jejak. Jogja ini banyak yang pinter, tapi lebih banyak yang nekat.”
Jono tertawa kecil, lalu berdiri tegak. “Baik, Pak. Saya cek ke belakang.”
Ia berjalan ke arah pintu belakang gudang yang masih terbuka setengah, memeriksa tanah dan semak-semak sekitar. Tapi memang benar, seperti kata Pak Gito: tidak ada bekas apa pun. Bahkan rumput pun tampak masih tegak berdiri, seolah tidak ada yang menginjaknya.
Dari kejauhan, terdengar suara klakson becak dan deru kereta api pagi dari Stasiun Lempuyangan, mengingatkan mereka bahwa dunia tetap berjalan seperti biasa, bahkan ketika sesuatu yang aneh sedang terjadi di salah satu sudutnya.
Jono menghela napas panjang. Ia tahu pencurian ini bukan sekadar soal kabel dan alat listrik biasa. Tapi apa hubungannya dengan kilatan merah semalam? Ia belum tahu.
Yang jelas, kasus pertamanya di Jogja sudah lebih rumit dari yang ia bayangkan.
“Selamat datang di Jogja, Jon,” gumamnya pelan. “Kota yang bahkan maling kabelnya pun pakai cara nggak biasa.”
Bab: Kembali ke Bayang Kota
Sore menjalar lambat-lambat di atas langit Jogja, mewarnai jalanan dengan cahaya jingga yang hangat. Di sudut-sudut kota tua, lampu-lampu minyak mulai dinyalakan di warung kopi dan kios kecil. Becak berderit pelan melintasi jalanan berkerikil, sementara suara lonceng sepeda tua berpadu dengan celoteh orang-orang yang baru pulang dari pasar.
Arno berjalan sendirian, menyusuri gang sempit di pinggiran kota. Jaketnya yang sudah usang menutupi sebagian tubuhnya yang masih terasa nyeri setelah pertarungan panjang semalam. Topinya ia tarik rendah, menutupi mata yang masih lelah.
Tak ada yang mengenalnya di sini. Tak ada yang tahu bahwa semalam, di tempat yang jauh dari kota ini, ia telah mengalahkan makhluk purba yang hampir menghanguskan dunia. Tiga titik api itu kini telah tertutup, kekuatan Banaspati lenyap bersama tubuhnya yang tersedot ke pusaran terakhir.
Namun di dalam dirinya, bayangan itu belum sepenuhnya pergi.
—
Langkahnya terhenti di depan warung kecil di sudut jalan. Bau kopi tubruk yang baru diseduh dan gorengan hangat mengisi udara. Ia duduk diam di bangku kayu tua, memesan secangkir kopi tanpa banyak bicara.
Ketika ia menyeruput kopi itu perlahan, sebuah suara lama kembali terdengar di kepalanya. Dalam-dalam, dari tempat paling gelap di pikirannya.
Svarnavarna, dengan suara dingin seperti bisikan angin dari lembah kosong:
“Kau merasa tenang sekarang, bocah? Padahal dunia baru saja kau ubah jalannya.”
Arno menutup matanya sebentar, menarik napas panjang.
Arno:
“Aku hanya ingin ini berakhir. Tidak lebih.”
Svarnavarna tertawa kecil, getir, seperti suara besi yang digoreskan ke batu.
Svarnavarna:
“Berakhir? Tidak ada yang benar-benar berakhir, Nak. Kau hanya menunda gelombang berikutnya. Dan kau pikir bayangan dalam dirimu akan tidur selamanya?”
Arno menggenggam cangkir kopinya lebih erat.
Arno:
“Selama aku masih sadar, aku yang memegang kendalinya.”
Svarnavarna (mengejek):
“Kendalikan? Hah… kau bahkan belum tahu setengahnya tentang apa yang kau bawa dalam dirimu. Bayangan itu bukan sekadar senjata. Ia… adalah lubang yang akan menelanmu jika kau lengah.”
Arno terdiam. Memandang lalu lalang orang-orang di jalanan. Mereka tertawa, berkelakar, hidup dalam dunia yang tak pernah tahu betapa dekatnya mereka dengan kehancuran semalam.
Arno (pelan):
“Biarkan aku hidup seperti ini sebentar saja. Aku lelah.”
Svarnavarna (perlahan, dingin):
“Istirahatlah, bocah. Tapi ingat… bayangan tidak tidur lama. Dan saat ia bangun nanti, kau akan lihat: musuhmu bukan hanya api… tapi dirimu sendiri.”
Suara itu perlahan meredup, hilang di antara derit becak yang melintas.
—
Arno meneguk kopi tubruknya sampai habis.
Malam mulai turun pelan-pelan, menutup kota Jogja dalam selimut angin dingin dan aroma tanah basah.
Ia berdiri, meninggalkan beberapa keping uang receh di meja.
Lalu berjalan lagi, menembus gang-gang sempit yang remang, menuju kamar sewanya yang sunyi di sudut kota tua.
Ia tahu, damai ini… hanya sementara.
—
Bab: Hari-Hari yang Sunyi
Beberapa hari berlalu sejak malam yang membakar lembah itu.
Kota Jogja tetap bergerak seperti biasa: suara becak pelan membelah pagi, hiruk-pikuk pasar Beringharjo yang tak pernah benar-benar diam, dan deretan angkringan yang mulai ramai saat senja perlahan turun.
Tak ada yang tahu tentang pertempuran di tempat jauh itu-di mana cahaya dan bayangan saling melukai dalam diam.
Bagi orang-orang kota, hidup tetap berjalan dari pagi ke malam, dari warung ke rumah, dari tawa ke letih.
Dan di sela riuh itu, Arno berjalan perlahan melewati Jalan Malioboro yang sedikit berdebu sore itu. Langkahnya lebih ringan, meski rasa letih masih menggantung di pundaknya.
Hari ini, suara Svarnavarna di kepalanya diam. Tidak sepenuhnya pergi, tapi memilih bersembunyi. Seperti badai yang menunggu waktu untuk bangun lagi.
Ia mampir ke kios buku bekas, membuka halaman demi halaman tanpa benar-benar membaca. Hanya membiarkan waktu berlalu seperti air selokan yang tak pernah berhenti mengalir.
—
Di Taman Itu Lagi
Dan sore itu, seperti beberapa hari sebelumnya, ia kembali ke taman kecil di sudut kota.
Tempat yang tenang, hanya ditemani suara burung gereja yang bertengger di kabel listrik dan semilir angin yang membawa bau tanah basah sisa gerimis pagi.
Aini sudah di sana, duduk di bangku yang sama. Tubuhnya masih tampak lelah, pucat samar di balik senyum tipisnya. Buku tulis terbuka di pangkuannya, penuh dengan coretan-coretan yang belum sempat ia rapikan. Rambutnya dikuncir seadanya, gerakannya pelan seperti orang yang masih belajar berdiri setelah jatuh.
Ia menoleh, tersenyum lemah.
Kukira kamu masih sibuk lari dari dunia.
Arno membalas dengan senyum tipis. Kali ini tak ada getir, hanya kelegaan yang belum utuh.
Hari ini nggak ada yang ngejar. Dunia lagi pelan.
Aini menatap langit yang mulai berwarna jingga kusam.
Dunia tuh jarang benar-benar pelan, No. Kadang kita aja yang capek ngejarnya.
Mereka diam sejenak. Tak perlu banyak kata. Karena hari-hari ini, diam lebih jujur daripada basa-basi.
—
Cerita Lama yang Terlewatkan
Aini menghela napas pendek, lalu tertawa kecil-suara yang terdengar rapuh tapi hangat.
Kamu masih inget nggak… dulu kita main layangan di kuburan Cokrodiningratan? Layanganmu nyangkut, terus kamu nyuruh aku yang panjat. Pulang-pulang aku demam seminggu gara-gara jatuh dari pohon.
Arno tertawa pelan, lebih pelan dari biasanya.
Itu karena kamu lebih gesit. Logika bertahan hidup.
Aini menggeleng pelan, menatap ke jalanan sepi.
Logika licik, lebih tepatnya. Yang suruh manjat sehat-sehat aja, yang jatuh malah yang disuruh.
Arno menunduk, senyumnya samar.
Tapi lihat sekarang, yang jatuh masih berdiri. Yang diem malah bingung mau ke mana.
Aini diam, matanya lembut menatap Arno, seperti ingin bicara lebih banyak tapi tubuhnya terlalu lelah untuk memulai.
—
Sore yang Sementara
Angin sore berhembus perlahan, membawa suara sepeda anak-anak yang baru pulang ngaji, dan bunyi bedug dari masjid jauh di ujung jalan.
Tak ada bayang Banaspati. Tak ada bisikan Svarnavarna.
Hanya dua orang yang duduk bersebelahan, sama-sama belum utuh, tapi cukup untuk hari ini.
Dan dalam diam itu, Arno merasa:
Mungkin, untuk sekarang, tak apa-apa menjadi biasa.
Tak perlu jadi penyelamat. Tak perlu jadi korban.
Cukup jadi orang yang duduk di bangku tua, menunggu senja turun tanpa tergesa.
Ia tahu: bahaya belum selesai.
Dunia belum aman.
Tapi untuk hari ini, untuk satu senja ini,
Ia beristirahat.
—
Bab: Mereka yang Tidak Bernama
Di ruang bawah tanah yang hanya diterangi cahaya redup, udara seperti berhenti bergerak.
Langkah siapa pun yang memasuki ruangan itu selalu terdengar terlalu keras, terlalu nyata di antara keheningan yang menyesakkan.
Seseorang berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya tegak, tak bergerak, nyaris seperti bayangan yang terpaku di lantai.
Suara yang keluar dari mulutnya pelan, namun cukup untuk membuat ruangan yang dingin itu terasa semakin sempit.
“Kita tidak di sini untuk didengar. Kita di sini… untuk tidak bisa dihindari.”
Tak ada yang berbicara setelahnya.
Lima sosok bertopeng hanya duduk diam, menatap tanpa mata, menunggu tanpa detak.
Tak ada nama disebut. Tak ada alasan diberikan.
Salah satu dari mereka akhirnya bersuara.
Pelan, seperti sesuatu yang merayap dari balik dinding retak:
“Dan mereka… akan tahu, meski tak sempat bertanya.”
Tak ada jawaban.
Karena jawaban adalah kelemahan.
Yang ada hanya kesepakatan diam: sesuatu akan terjadi.
Dan ketika terjadi, tak ada yang akan sempat mencari siapa pelakunya.
—
Langkah yang Tak Meninggalkan Jejak
Malam itu, dunia tetap berputar seperti biasa.
Lampu-lampu jalan tetap menyala, warung-warung tetap melayani pembeli, dan orang-orang tertawa di balik tembok rumah mereka.
Tapi di sudut-sudut tergelap kota, bayangan mulai bergerak.
Tidak mencolok. Tidak memaksa.
Hanya hadir, dan itu cukup untuk membuat udara terasa berat.
Mereka menghampiri orang-orang yang bahkan dunia sudah berhenti memanggil namanya.
Tidak menawarkan apa pun. Tidak menjanjikan apa pun.
Hanya hadir… dan menunggu jawaban.
Dan anehnya, sebagian orang memilih mengikuti tanpa bertanya kenapa.
—
Suara yang Mengendap di Malam
Sebelum mereka bubar, suara itu berbicara sekali lagi.
Pelan, nyaris seperti bisikan yang menempel di tengkuk:
“Biarkan dunia terus tertidur. Kita akan bangunkan mereka… saat waktu berhenti berdetak.”
Lalu sunyi kembali.
Sunyi yang tidak menenangkan.
Sunyi yang seperti pisau digantung di atas kepala, menunggu jatuh tanpa aba-aba.
—
Di Tempat Lain, Kehidupan Masih Buta
Di kota yang jauh dari ruangan itu,
orang-orang masih saling sapa, masih menghitung hari menuju pasar malam,
masih menyeduh kopi di pagi buta.
Dan Arno…
masih duduk di bawah langit yang ia kira tenang,
tak tahu bahwa sesuatu sudah mulai mengintainya.
Bukan suara.
Bukan bayangan.
Tapi sesuatu yang bahkan tidak butuh nama untuk membuat dunia bergetar.
—
Bab: Tanda yang Tak Masuk Akal
Tiga hari berlalu sejak pencurian di gudang PLN Baciro. Kota Jogja berjalan seperti biasa: suara becak, hiruk-pikuk pasar, dan aroma gudeg yang mengepul di pagi hari. Tapi di balik rutinitas itu, beberapa laporan kecil mulai menumpuk di meja Jono.
Semua laporan itu tampak sepele-sekilas tidak ada hubungannya dengan pencurian kabel. Tapi ada satu benang merah yang tak bisa ia abaikan.
Di kampung Terban, listrik padam tanpa sebab, padahal jaringan utama tidak rusak.
Di Wirobrajan, seorang tukang las mengaku mendengar suara “denging” aneh dari dalam sumur tua.
Dan di kawasan Bumijo, beberapa warga melaporkan lampu-lampu jalan yang tiba-tiba menyala terang berlebihan hingga meledak, padahal tidak ada sambaran petir.
Jono duduk di kantornya, menyatukan laporan-laporan itu di atas meja.
“Listrik padam… sumur berisik… lampu meledak…,” gumamnya sambil mencoret-coret peta Jogja. “Kalau ini cuma korsleting, kenapa lokasinya nyebar nggak beraturan?”
Ia mencoret titik-titik merah di peta yang menandai lokasi kejadian. Semuanya membentuk garis acak yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawah kota, tapi tak mengikuti jalur kabel biasa.
Jono menarik napas panjang, lalu menyalakan rokoknya.
Ini bukan sekadar pencurian kabel. Ada sesuatu yang lebih besar, tapi belum tahu apa.
—
Percakapan yang Tidak Menjawab
Sore itu, Jono menemui kepala PLN Jogja, Pak Waskito, di kantornya yang penuh asap rokok dan berkas-berkas tua.
“Pak, saya cuma mau tanya. Kalau ada orang yang ambil alat sambungan listrik, kira-kira mau dipakai buat apa?”
Pak Waskito mengernyit, lalu tertawa kecil.
“Buat pasang jaringan baru, Mas. Atau buat eksperimen. Tapi orang biasa nggak ngerti cara makainya. Itu alat khusus.”
“Kalau bukan orang PLN?”
Pak Waskito mendesah.
“Ya… kalau bukan orang PLN, berarti orang yang ngerti listrik. Atau… orang yang mau main-main sama sesuatu yang nggak seharusnya disentuh.”
Jawaban itu membuat Jono semakin tidak tenang.
—
Gerak yang Tak Terlihat
Malamnya, saat Jono menyusuri kawasan belakang Pasar Kuncen, ia merasa ada yang mengawasinya. Bukan sekadar perasaan biasa. Seperti mata yang terlalu dekat, tapi tak terlihat.
Ia berhenti di depan tiang listrik tua yang mengeluarkan suara berdengung pelan, lebih keras dari biasanya.
Tangannya refleks menyentuh senjata di pinggang, meski ia tahu pistol tidak akan berguna melawan… sesuatu yang belum jelas bentuknya.
Dan di kejauhan, dalam bayang-bayang gang sempit, tampak sosok samar berdiri diam.
Tak bergerak, tak mendekat, hanya… menunggu.
Jono memicingkan mata. Tapi saat ia melangkah maju, sosok itu sudah hilang.
Yang tertinggal hanya dingin yang anehnya menusuk tulang, padahal malam itu tak sedingin biasanya.
—
Kota yang Tak Lagi Sepenuhnya Normal
Jono tahu, ia sedang masuk ke dalam sesuatu yang jauh lebih gelap dari kasus-kasus sebelumnya.
Tapi ia belum tahu siapa yang menarik benangnya.
Hanya satu hal yang jelas:
Kota ini… mulai bergerak keluar dari kewarasan yang selama ini ia percayai.
Dan Jono, entah suka atau tidak, adalah satu dari sedikit orang yang masih berusaha menjaga logika tetap berdiri di tengah bayangan.
—
Bab: Sunyi di Antara Halaman-Halaman yang Terbit
Pagi itu, Harian Dwi Warna sudah terbit. Di halaman kedua, tepat di bawah kolom editorial, tercetak jelas laporan investigasi Aini:
“Merapi Tak Hanya Membakar Batu: Misteri Kilatan Malam dan Suara yang Tak Terjawab”
Oleh: Aini Prameswari.
Artikel itu membahas kesaksian warga Kaliurang, laporan lindu kecil di beberapa desa, dan fenomena cahaya merah yang membelah langit malam. Ia tetap menjaga nadanya netral-setengah ilmiah, setengah pengingat-agar tak terlihat terlalu percaya pada hal-hal yang belum terbukti.
Namun, bagi siapa pun yang pernah berdiri di tengah keheningan Merapi malam itu, mereka tahu:
Ini bukan sekadar gejala alam.
—
Redaksi yang Mulai Sibuk
Di ruang redaksi Dwi Warna, telepon berdering hampir tanpa jeda. Beberapa pembaca menelepon untuk mengucapkan terima kasih karena ada yang peduli pada suara-suara kecil dari desa.
Beberapa lain, tentu saja, menuduhnya membesar-besarkan ketakutan.
Pak Harun, sang redaktur senior, menghampiri Aini yang sedang mengetik revisi untuk artikel berikutnya.
” Liputanmu bagus, Nin. Tapi kayaknya kita bakal dapat surat peringatan dari kantor pusat BMKG kalau kamu terus pakai kata ‘tak biasa’ tanpa klarifikasi ilmiah.”
Aini tersenyum kecil.
“Kalau semuanya bisa dijelaskan dengan ilmiah, Pak, Jogja nggak bakal punya legenda.”
Pak Harun tertawa pelan.
“Dasar kamu… Boleh puitis, tapi jangan kelewat liar. Hati-hati, Nin. Kota ini lebih banyak yang diam, tapi matanya tajam.”
—
Diam yang Mengganggu
Sepulang dari kantor, Aini mampir di sebuah kios koran kecil. Ia lihat sendiri berapa banyak koran pagi itu yang sudah habis. Tapi itu tak membuatnya tenang. Ada sesuatu yang lebih ia khawatirkan.
Bukan soal berita yang dibaca orang. Tapi tentang orang-orang yang tidak suka berita itu terbit.
Sore harinya, saat ia membuka surat kabar lain di angkringan, matanya menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduknya naik:
Di pojok kecil halaman kriminal sebuah koran pinggiran, tertulis singkat:
“Gudang PLN Baciro Kemalingan: Aneh, Tak Ada Jejak Pelaku.”
Ia terdiam. Baciro… kejadian yang terjadi hanya sehari setelah peristiwa Merapi.
Kabel dan alat sambungan hilang tanpa jejak. Persis seperti cerita-cerita gelap yang hanya berseliweran di lorong malam.
—
Satu Pesan Masuk
Malam harinya, di kamar kos sempitnya, radio tua memutar lagu Ebiet G. Ade pelan-pelan. Di meja, buku catatan dan koran-koran berserakan.
Ia membuka surat yang baru saja diselipkan di bawah pintu.
Kertasnya tipis, tanpa nama pengirim, hanya satu kalimat tertulis dengan spidol hitam tebal:
“Tulis saja terus. Tapi siap-siap kehilangan lebih dari sekadar kata-kata.”
Tangannya terdiam. Dadanya sesak sebentar. Tapi matanya tetap tenang. Ia lipat surat itu perlahan, memasukkannya ke dalam laci yang ia kunci rapat.
“Kalau takut kehilangan… ngapain nulis dari awal?” gumamnya pelan.
—
Esoknya, Sebelum Fajar
Aini berangkat lebih pagi ke alun-alun, seperti janjinya pada diri sendiri. Membawa buku kecil dan pensil, ia duduk sendirian. Menunggu… entah siapa.
Mungkin Arno.
Mungkin bahaya yang tak berwajah.
Atau mungkin hanya… dirinya sendiri yang butuh waktu hening.
—




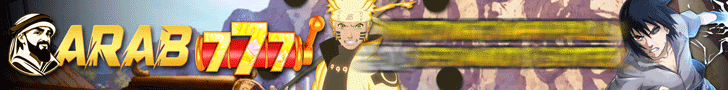
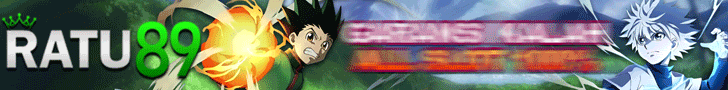



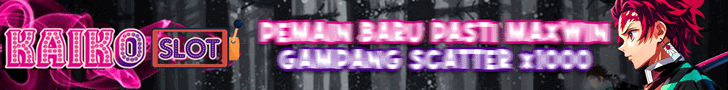

Comment