Jika Kalian menemukan Gambar Rusak / Terpotong / Tidak Terload Silahkan Lapor ke [chatango] atau [disini]

4.Bangkitnya Sang Kelam
—
Bab: Sambutan Terakhir bagi yang Lemah (Bagian 2)
Jauh dari hiruk-pikuk pertempuran, di puncak sebuah gedung tua yang nyaris dilupakan zaman, seorang pria tua berdiri diam. Pakaian lusuhnya diterpa angin malam, rambut putihnya terurai bebas. Ia memandang ke arah langit berwarna kemerahan dengan mata yang tenang, seolah tahu persis apa yang sedang terjadi.
Hanya senyum tipis yang menghias bibirnya. Sebuah senyum penuh arti, seperti seseorang yang telah lama menanti benih yang kini tumbuh menembus kerasnya tanah takdir.
Pria tua itu berbisik, suaranya larut bersama angin malam:
“Akhirnya… sang bayangan bangkit juga.”
Lalu ia melangkah pergi perlahan, membiarkan dunia melanjutkan kisahnya sendiri. Malam itu masih terlalu dini baginya untuk campur tangan.
—
Di lembah yang jauh lebih rendah, dari perkampungan dan ladang-ladang yang sunyi, orang-orang mulai berdiri di luar rumah mereka, menatap ke arah langit yang kelam. Kilatan cahaya merah dan hitam saling bersilang di udara seperti petir yang berperang.
Gemuruh dan dentuman berat terdengar samar, menggetarkan tanah di bawah kaki mereka.
Beberapa orang saling bertanya, suaranya bergetar di antara bisik-bisik takut.
“Itu… apa? Petir? Atau kembang api?”
Tapi tidak ada jawaban satu pun yang keluar, mereka hanya berdiri, menatap jauh tanpa berani melangkah lebih dekat. Anak-anak ditarik masuk ke dalam rumah, pintu-pintu ditutup rapat. Tapi mata mereka tetap mengintip dari celah-celah jendela, menyaksikan bayangan raksasa yang menari di langit malam.
—
Sementara itu, di pusat pertarungan, Banaspati meraung, mengusir keraguan yang sempat menggerogoti dirinya. Ia menghentakkan kakinya, menciptakan gelombang panas yang memecahkan tanah. Dari kedua tangannya, semburan api hitam memanjang seperti tombak, meluncur deras ke arah Arno.
Namun Arno hanya mengangkat satu tangan. Dari balik tubuhnya, bayangan menggeliat hidup, membentuk cambuk panjang hitam legam, berujung merah menyala. Cambuk itu melesat cepat, membelit tombak api Banaspati, lalu memutar dan melemparkannya ke langit malam, meledak seperti bunga api yang jatuh ke dalam keheningan.
Banaspati tertegun, tapi tanah di bawahnya kembali retak. Dari kegelapan itu, bayangan Arno menjulur membentuk tangan raksasa-gelap, kasar, berurat merah menyala-yang menghantam Banaspati dari bawah, menghentakkannya keras ke tanah.
Blarrr!
Gema benturan itu mengguncang seluruh lembah. Burung-burung malam beterbangan panik, dan bumi terasa seperti menghela napas berat.
Banaspati, meski terluka, bangkit kembali. Api hitam di tubuhnya semakin pekat. Dengan raungan yang menggetarkan langit, ia meluncur ke arah Arno, kedua tangannya berubah menjadi bilah api melengkung.
Di udara, mereka kembali bertabrakan. Api dan bayangan saling memukul, saling menelan, menciptakan kilatan cahaya yang menerangi langit malam, disaksikan oleh mata-mata takut dari lembah-lembah yang jauh.
Arno menghentakkan tangannya. Dari balik punggungnya, bayangan berubah menjadi puluhan tombak hitam, melesat ke udara lalu menghujani Banaspati seperti badai kematian. Banaspati menangkis sebagian dengan perisai api, namun sisanya menghantamnya keras, membuat tubuhnya terdorong mundur, terhuyung untuk pertama kalinya.
Banaspati, mencibir getir sambil terengah:
“Kau pikir dengan kekuatanmu itu kamu mampu melumatku Sang Api Abadi ini?.”
Arno berdiri mantap, suaranya dingin, tajam, seperti malam yang baru saja dilahirkan kembali.
Arno (pelan, menusuk):
“Mungkin. Tapi bukan hanya aku.. Aku dan bayanganku ini yang akan mengirimkanmu kembali ke tempatmu yang seharusnya.”
Svarnavarna tertawa girang;
“Bagus bocah.. Optimis itu perlu.”
Dengan satu hentakan kaki, bayangan di belakangnya membesar, membentuk sosok raksasa samar-seperti bayangan dirinya sendiri-yang menatap Banaspati dengan mata merah yang membara.
Pertarungan antara api purba dan bayangan hidup baru saja dimulai.
Dan dunia di bawahnya, hanya bisa berdoa, semoga fajar masih mau datang.
—
Bab: Pria yang Datang Terlambat Tapi Tepat
Langkah Ki Prayitno dan Mbah Suro terhenti mendadak ketika dari balik kabut patahan batu, terdengar suara berat namun ceria-sangat tidak cocok dengan suasana yang mencekam itu.
“Eh, kalian kenapa mukanya kayak habis dikejar utang pajak tujuh tahun? Atau… jangan-jangan memang iya?”
Sosok itu muncul perlahan dari balik batu, bayangannya melebur dengan kabut sebelum akhirnya tampak jelas. Seorang pria berusia sekitar 46 tahun, bertubuh berisi namun tidak gemuk. Bahunya lebar, perutnya sedikit menonjol seperti orang yang terlalu sering makan malam kedua, tapi kakinya masih cukup kuat untuk memanjat bukit. Matanya besar, selalu tampak terkejut seperti tokek yang baru bangun tidur, dan mulutnya melebar ke samping, membuat senyumnya terlihat lebih seperti ejekan yang ramah.
“Haryo…” desis Ki Prayitno, suaranya bercampur antara lega dan kewaspadaan. “Kau… masih hidup?”
Mbah Suro melangkah setengah mundur, matanya tajam meneliti Haryo dari ujung kaki sampai kepala, seolah tak yakin apakah yang mereka lihat benar-benar manusia atau bayangan yang menyamar jadi manusia. “Dari semua waktu yang mungkin… kenapa sekarang kau muncul?”
Haryo tertawa pendek, suaranya membelah kesunyian seperti pisau yang tidak tahu diri.
“Kalau aku muncul pas semuanya tenang, kalian pasti tidur sambil mendengkur. Justru di saat genting begini kalian butuh sesuatu… semacam, humor tragis. Kan, kalau mati, setidaknya ketawa dulu.”
Mbah Suro mendesis, menggenggam kerisnya erat. “Kalau bukan karena keadaan genting, sudah kutarik kupingmu biar mulutmu berhenti sebentar.”
Namun Haryo mengangkat tangannya santai, masih dengan senyum malasnya. “Santai, santai. Aku tahu kenapa kalian di sini. Titik pertama sudah terbuka, kan? Dua lagi sedang menunggu. Dan aku… ya aku, orang yang kalian cari-cari, yang katanya tahu cara menutup lubang-lubang tua ini.”
Ki Prayitno mendekat, suaranya berat. “Kenapa baru sekarang kau muncul?”
Untuk pertama kalinya, gurauan Haryo reda. Ia menarik napas pelan, menatap retakan merah yang berdenyut samar di patahan batu. “Karena sebelum ini, jalurnya masih tertutup rapat. Dan aku… belum cukup kuat untuk melawan apa yang menjaga titik-titik ini dari dalam. Tapi sekarang, jalannya sudah dibuka-
Oleh seseorang yang masih misterius.”
Mbah Suro mengernyit curiga. “Kau yakin bukan kau yang membukanya?”
Haryo menoleh, senyum lebarnya kembali muncul seperti pelindung tipis atas rasa lelahnya. “Andai aku yang membuka, aku pasti sudah jual tiket masuknya. Sayangnya, ini bukan bisnis yang menguntungkan.”
Ia berjalan mendekat ke retakan batu, menatap cahaya merah yang bernafas seperti luka yang belum sembuh.
“Yang kita hadapi ini bukan sekadar gerbang. Ini sisa ritual tua yang dulu… tak pernah selesai. Kalau satu terbuka, dua lainnya akan bangkit dengan sendirinya… kecuali simpulnya diikat kembali dari dalam.”
Ki Prayitno mengepalkan tangan. “Dan kau tahu simpulnya?”
Haryo melirik sambil menyeringai, mulut lebarnya tampak seperti sedang menggoda maut. “Sedikit. Sisanya kita pelajari sambil jalan. Hidup ini kan improvisasi abadi.”
Mbah Suro masih menatap tajam. “Apa yang harus kita lakukan sekarang?”
Haryo memejamkan mata sejenak, lalu berkata datar, “Seseorang harus masuk ke dalam retakan. Mengikat simpul itu dari dalam sebelum panasnya meluap ke luar.”
Mbah Suro menoleh pada Ki Prayitno, keduanya saling tatap dengan ragu. “Dan siapa yang cukup kuat… dan cukup bodoh… untuk masuk ke sana?”
Haryo membuka satu matanya, tersenyum lebar. “Kabar baiknya, aku pernah masuk. Kabar buruknya, aku hampir nggak keluar waktu itu. Selebihnya… ya, kita lihat nanti.”
Keheningan menelan mereka. Hanya retakan batu yang bergetar pelan, dan suara bumi yang seolah menunggu jawaban.
—
Bab: Penjaga yang Tak Dikenal
Di sisi hutan Wonosadi yang sunyi, Pak Parman dan Romo Seto berdiri cemas di tepi lingkaran tanah yang hangus terbakar. Hawa panas merayap pelan-pelan dari tanah, menjalar seperti nafas makhluk purba yang mulai terbangun. Bara halus di permukaan tanah berpendar samar, membentuk garis-garis aneh yang tak mereka pahami.
Pak Parman mengusap wajahnya yang mulai basah oleh keringat. “Kita harus lakukan sesuatu, Romo. Kalau ini menyebar ke ladang atau desa, kita habis.”
Romo Seto menggenggam salib kecil di lehernya, suaranya berat. “Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita bukan orang yang tahu cara menghadapi api seperti ini…”
Tiba-tiba, dari balik semak dan kabut tipis, terdengar suara tenang namun tajam.
“Kalian benar. Ini bukan api yang bisa dipadamkan dengan air atau doa biasa.”
Mereka berdua menoleh tajam, berjaga-jaga. Dari kegelapan muncul seorang pria berperawakan tinggi dan kurus, berkulit cerah, dengan sorot mata tajam namun tenang. Wajahnya tidak menunjukkan otot-otot tegang atau kesan jagoan, lebih mirip seorang Guru SMA atau pengamat yang tersesat di medan perang.
Pak Parman memandanginya waspada. “Siapa kau? Apa kau yang menyebabkan semua ini?”
Pria itu berhenti beberapa langkah dari mereka, tangannya terangkat perlahan, menunjukkan bahwa ia tidak membawa ancaman. “Aku bukan musuh kalian. Namaku Pura. Dan tidak, aku tidak membukanya. Aku di sini karena aku tahu bagaimana menutupnya.”
Romo Seto tetap memasang sikap hati-hati. “Kau datang dari mana? Orang desa sini tak ada yang kenal kau.”
Pura tersenyum tipis, tidak menyinggung, tapi juga tidak terlalu ramah. “Kalian tak perlu mengenalku untuk menerima bantuanku. Percayalah, jika kita berlama-lama berdebat, tempat ini bisa hancur sebelum matahari terbit.”
Pak Parman menatap bara itu, yang mulai bergetar seolah-olah mendengar percakapan mereka dan tidak sabar menunggu.
Akhirnya, Pak Parman mengangguk pelan. “Baik. Apa yang harus kami lakukan?”
Pura melangkah lebih dekat ke lingkaran bara, mengeluarkan gulungan benang tipis berwarna perak dari balik bajunya. Cahaya api memantul di wajahnya, membuat sorot matanya semakin tajam.
“Ini bukan tentang memadamkan api. Ini tentang mengikat kembali simpul yang terlepas. Tapi aku tak bisa melakukannya sendirian. Kalian berdua, jagalah lingkaran ini. Pastikan tak ada yang mendekat, baik dari luar maupun… dari dalam.”
Romo Seto menegakkan badan, meski dadanya masih penuh keraguan. “Dari dalam?”
Pura tak menjawab. Ia mulai menenun benang itu di udara, membentuk pola-pola halus yang tampak seperti jaring cahaya di atas bara. Begitu ia mulai bekerja, hawa panas memancar lebih kuat, membuat tanah bergetar dan udara mendesis.
Pak Parman menggenggam tongkat kayunya erat-erat. Romo Seto berdoa dalam hati, matanya tak berkedip mengawasi api yang seolah marah.
Dan di tengah-tengah semuanya, Pura berdiri tenang, menenun benang tipisnya melawan kekuatan yang ingin keluar. Mereka tak mengenalnya, tapi untuk saat ini, mereka tak punya pilihan selain percaya.
Malam terasa lebih berat dari biasanya. Seolah menunggu: apakah simpul itu akan terikat kembali… atau justru melepaskan sesuatu yang lebih buruk.
—
Bab: Sambutan Terakhir bagi yang Lemah (Bagian 3 – Pertempuran Tanpa Akhir)
Langit malam telah berubah menjadi medan perang yang tak terjangkau logika. Angin berhenti bertiup, waktu terasa melambat di sekitar mereka, hanya menyisakan benturan api dan bayangan yang silih berganti meledakkan udara.
Namun bagi Arno, ada satu hal yang jauh lebih penting dari sekadar kemenangan: Aini.
Gadis itu masih di tangan Banaspati, tersembunyi entah di mana, mungkin terluka, mungkin sudah tak sadarkan diri. Ia harus diselamatkan-malam ini juga.
Arno (berbisik dalam hati, matanya tajam menatap Banaspati):
“Aku tidak akan biarkan dia menjadi korban keangkuhanmu.”
Arno melesat maju, tubuhnya seperti bayangan tajam yang memotong kegelapan. Cambuk hitamnya berdesing keras, menghantam udara dengan kekuatan luar biasa, membelah kobaran api Banaspati hingga terpecah menjadi serpihan bara yang beterbangan seperti hujan meteor terbalik.
Banaspati menangkis dengan lengannya yang berubah menjadi perisai api berlapis-lapis. Ia tertawa, bukan karena senang, tapi karena heran-bagaimana mungkin manusia yang hampir mati barusan kini mampu menahan kekuatan purba seperti miliknya?
Banaspati, sambil berputar menyerang, mengejek:
“Apa kau bertarung untuk cinta yang lemah itu? Dunia ini tidak butuh penyelamat bodoh seperti dirimu, bocah!”
Tapi Arno tidak menjawab. Dia hanya bergerak.
Bayangan di belakangnya menggeliat, berubah menjadi tangan-tangan raksasa yang mencengkeram udara, mencoba meraih Banaspati. Ada tangan yang menarik batu-batu besar, melemparkannya seperti peluru. Ada yang berubah menjadi panah hitam yang ditembakkan ke udara, lalu jatuh menghujani Banaspati tanpa ampun.
Banaspati mengangkat kedua tangannya, memanggil pilar-pilar api dari tanah. Pilar itu menghantam panah bayangan, menciptakan ledakan besar yang membuat seluruh lembah terguncang.
DOOOMM!!!
Tanah retak semakin dalam. Tebing runtuh. Pohon-pohon di pinggir lembah roboh terkena gelombang kejut.
—
Di kejauhan…
Orang-orang dari desa-desa sekitar hanya bisa menyaksikan kilatan demi kilatan itu dari kejauhan, berdiri di balik bukit, di tepi sungai, atau bahkan dari atap rumah mereka.
“Itu bukan petir…” “Itu juga bukan perang biasa…” “Apa itu… para dewa sedang murka?”
Ketakutan mulai tumbuh, tapi rasa penasaran membuat mereka tak bisa berpaling. Malam itu akan menjadi kisah yang diceritakan puluhan tahun ke depan, tentang bagaimana ada dua kekuatan yang bertarung memperebutkan malam.
—
Kembali ke lembah…
Banaspati melesat mendekat, tubuhnya seperti bola api hitam yang memuntahkan semburan api ke segala arah. Dia menebas bayangan Arno dengan bilah api yang memanjang seperti bulan sabit terbalik.
Tapi Arno berbalik dengan cepat. Bayangannya berubah menjadi tameng transparan, seperti kaca hitam yang menahan panas, lalu retak dan pecah menjadi ribuan pecahan kecil yang menyerang Banaspati dari segala arah.
Banaspati meraung, tubuhnya terguncang. Ia mulai menyadari… kekuatannya tidak sepenuhnya kembali seperti biasanya. Sesuatu yang tak terlihat menghalangi aliran kekuatan purba yang biasa mengalir bebas ke dalam dirinya.
Ia mundur sejenak, napasnya berat. Dan di sanalah ia sadar.
Banaspati (mendesah pelan, setengah marah, setengah kecewa):
“Dua titik… sudah tertutup. Siapa yang berani melakukan ini?”
Matanya menatap langit yang kelam, seolah mencari jawaban pada bintang-bintang yang dingin. Tapi Arno?
Ia berdiri di hadapannya, masih dengan napas terengah, masih dengan luka yang belum sembuh… namun dengan tekad yang bahkan lebih panas daripada api Banaspati.
Banaspati, tertawa getir sambil melangkah maju lagi:
“Kau tidak tahu apa-apa, bocah. Kau pikir kekuatan ini datang begitu saja? Dunia ini punya keseimbangan, dan malam ini… kau mengganggunya.”
Arno mengangkat tangannya lagi. Bayangan di belakangnya mulai membentuk sosok baru-seperti singa raksasa bersayap, matanya merah menyala, tubuhnya bergetar seperti badai yang siap menerkam mangsa.
Arno (suara pelan namun tajam):
“Aku tidak peduli soal keseimbanganmu. Yang kupedulikan hanya satu hal… dia kembali dengan selamat.”
—
Banaspati meraung, mengumpulkan seluruh api yang tersisa dalam tubuhnya. Ia membentuk bola api hitam sebesar bukit, lalu melemparkannya ke arah Arno dengan seluruh kekuatan yang tersisa.
Arno merentangkan kedua tangannya. Bayangan di belakangnya berubah menjadi mulut raksasa yang terbuka, menelan bola api itu bulat-bulat.
Tabrakan dahsyat itu menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Batu-batu beterbangan, debu menutupi langit, dan tanah berguncang seperti hendak runtuh.
—
Akhir Banaspati
Dari balik debu dan asap, Arno masih berdiri. Tubuhnya berlutut, kepayahan, tapi masih utuh.
Banaspati terhuyung. Tubuhnya masih menyala, tapi nyalanya kini redup, seolah sebagian nyawanya ikut terbakar dalam ledakan tadi.
Banaspati, menatap Arno dengan sorot mata yang mulai kehilangan panasnya:
“Kau… bukan sekadar manusia… tapi kau juga… bukan pahlawan.”
Arno mendongak perlahan.
Arno (pelan, seperti gumaman):
“Aku tidak pernah ingin jadi pahlawan.”
Namun pertempuran itu telah memutuskan jalannya sendiri. Retakan tanah di bawah kaki Banaspati terbuka, dan titik api terakhir yang selama ini menopang kekuatannya mulai menariknya masuk. Tubuh Banaspati memuai, menyala lebih terang sesaat, sebelum perlahan-lahan tersedot ke dalam pusaran kecil itu.
Banaspati (dengan tawa getir, suara terakhirnya lenyap bersama api):
“Suatu saat… bayanganmu akan menuntut harga… bocah.”
Dalam sekejap, tubuhnya lenyap, dan titik api terakhir menutup rapat.
Semua menjadi sunyi.
—
Pertemuan Kembali
Arno berdiri terhuyung, tubuhnya mulai kehilangan lapisan bayangan yang selama ini melindunginya. Nafasnya berat, langkahnya goyah, tapi hatinya tetap terarah pada satu hal.
Di balik reruntuhan batu besar, ia menemukan sosok itu.
Aini.
Tubuhnya terbaring tak sadarkan diri, wajahnya tenang namun pucat. Seperti sedang tidur dalam dinginnya malam yang keras.
Arno berlutut, menyingkirkan batu dan debu, lalu mengangkat tubuh Aini dengan hati-hati.
Arno (pelan, lirih namun mantap):
“Kita pulang…”
Dengan langkah perlahan namun pasti, ia meninggalkan lembah itu, bayangan di tubuhnya lenyap sepenuhnya, menyisakan dirinya yang kembali ke wujud manusia biasa-terluka, letih, tapi utuh.
—
Dan malam itu…
Orang-orang dari desa yang melihat dari kejauhan hanya bisa berbisik di antara ketakutan dan keheranan.
Kilatan itu telah padam.
Suara ledakan itu telah lenyap.
Tapi cerita tentang malam itu baru saja dimulai.
—
Bab: Setelah Segalanya Reda
Malam itu perlahan menyerah pada keheningan yang baru. Suhu panas yang tadi membakar tanah patahan batu di selatan kini lenyap, menyisakan hanya udara dingin dan lembab seperti biasa. Haryo berdiri sambil menghela napas panjang, menatap retakan batu yang kini tampak seperti hanya celah tua yang dilupakan waktu. Tidak ada lagi cahaya merah, tidak ada lagi hawa panas yang menyesakkan.
Ki Prayitno dan Mbah Suro menghampirinya pelan. Mereka tahu, apa pun yang baru saja terjadi, telah selesai untuk sekarang.
“Sudah?” tanya Ki Prayitno singkat.
Haryo mengangguk, sambil mengusap dahinya yang basah oleh keringat. “Sudah. Setidaknya, untuk malam ini.”
Mbah Suro menatap patahan batu itu dengan sorot mata curiga. “Kau yakin tak akan terbuka lagi dalam waktu dekat?”
Haryo tersenyum miring, mulut lebarnya masih seperti tokek yang siap bercanda meski lelah jelas terpancar di wajahnya. “Yakin? Tidak pernah. Tapi… untuk sementara, kita bisa pulang tanpa dikejar api.”
Ki Prayitno hanya menghela napas, tak ingin memperpanjang kata-kata. Ia tahu, istirahat mereka tidak akan lama. Tapi malam ini… mereka bisa diam sebentar.
—
Di sisi lain hutan, Pak Parman dan Romo Seto berdiri kebingungan, menatap area Wonosadi yang tadi begitu panas, kini tenang seperti ladang biasa setelah hujan. Tak ada jejak api, tak ada bekas kekacauan.
Di hadapan mereka berdiri Pura-pria jangkung berkulit cerah yang baru saja menyelesaikan tugasnya tanpa banyak bicara. Dia hanya menepuk-nepuk celana panjangnya yang berdebu, lalu menatap keduanya dengan senyum tipis.
Pak Parman akhirnya memecah keheningan. “Kau… siapa sebenarnya?”
Pura hanya mengangkat bahu ringan. “Hanya orang lewat. Kebetulan tahu caranya menutup lubang seperti itu.”
Romo Seto masih menatap curiga, namun dalam hatinya ia bersyukur atas kehadiran pria itu. Meski tak mengenalnya, jelas tanpa bantuan orang ini mereka mungkin sudah terjebak lebih dalam dalam bencana yang belum mereka pahami sepenuhnya.
Pura menatap langit sebentar, lalu berbalik perlahan, melangkah pergi meninggalkan mereka dalam kebingungan dan kelegaan yang belum sepenuhnya mereka cerna.
—
Malam yang tadi penuh gejolak kini terasa asing dalam keheningannya. Seolah dunia baru saja menutup halaman yang paling berbahaya dari kisahnya, namun tak ada yang tahu apakah halaman berikutnya akan lebih tenang atau justru lebih gelap.
Dan jauh di antara kegelapan yang memisahkan patahan batu dan hutan Wonosadi, dua orang itu-Haryo dan Pura-masih berjalan di jalan mereka masing-masing. Tak saling melihat malam itu, tapi masing-masing tahu bahwa yang satu pasti sedang menjaga seperti yang lainnya.
Untuk malam ini, setidaknya, dunia masih bertahan.
—
Di Tempat Lain, dalam Bayang-Bayang Malam
Di kejauhan, jauh dari lembah yang kini telah sunyi, seorang pria berdiri di atas tebing yang menghadap ke arah pertempuran yang baru saja usai. Wajahnya setengah tertutup oleh topeng retak berwarna kelam, sisanya menampilkan senyum miring yang dingin dan penuh perhitungan.
Matanya memandang ke arah langit malam yang perlahan kembali tenang, tapi sorotnya bukan kecewa-justru puas, seperti menyaksikan satu bagian dari rencananya berjalan sebagaimana mestinya.
Pria Misterius (berbisik pelan, seperti berbicara kepada kegelapan di sekitarnya):
“Tumbal manusia biasa… memang terlalu rapuh untuk menjadi wadah sejati para roh purba. Mereka hanya cangkang yang retak, tak sanggup menahan amarah zaman yang lahir sebelum manusia bermimpi.”
Ia menyeringai, suara tawanya nyaris tenggelam dalam desir angin malam.
“Tapi tak apa… Masih ada waktu. Masih ada yang lebih cocok… Dan kelak, bayangan serta api hanyalah permulaan dari gelombang berikutnya.”
Dengan langkah tenang, pria itu berbalik, bayangannya menyatu dengan kabut, meninggalkan tempat itu tanpa jejak.
Rencana besarnya baru saja dimulai.
Dan dunia, tanpa sadar, sudah terlambat menyadarinya.
—
Di Atas Sebuah Gedung Lama di Jogja
Di atas sebuah gedung tua yang nyaris terlupakan di sudut kota Jogja, seorang pria tua yang sama berdiri sendirian, bersandar pada pagar berkarat yang menghadap ke arah utara. Gedung itu sudah lama kosong, hanya dihuni angin malam dan suara kota yang tak pernah benar-benar tidur.
Dari ketinggiannya, ia menatap langit yang masih menyisakan jejak samar dari pertempuran di kejauhan. Kilatan cahaya yang sempat menerangi cakrawala, kini perlahan meredup, meninggalkan gelap yang dingin.
Pria tua itu menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip pengakuan diam, bukan kebanggaan.
Ia hanya pengamat. Sejak awal memang begitu. Tidak lebih.
Pria Tua itu bergumam pelan, nyaris tak terdengar oleh siapa pun kecuali malam:
“Jalan hidupnya… akhirnya mulai bergerak. Entah ke mana ujungnya.”
Ia menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan, matanya tenang namun dalam, seperti menyimpan banyak kisah yang enggan diceritakan.
“Dunia memang butuh pemain baru. Tapi tidak semua orang sadar, bahwa setiap cahaya baru… melahirkan bayangan baru pula.”
Dengan langkah perlahan, ia meninggalkan tepian atap itu, menyusuri lorong gelap tanpa terburu-buru, seolah tahu bahwa dunia akan terus berputar, dengan atau tanpa dirinya.
Ia bukan bagian dari permainan itu. Hanya seseorang yang memilih menonton… setidaknya untuk saat ini.




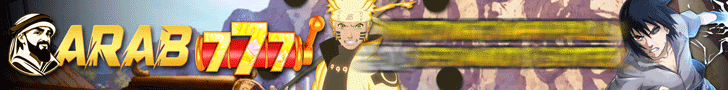
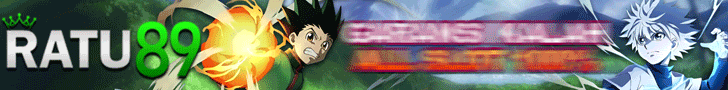



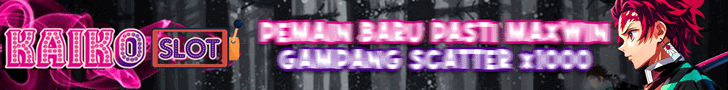

Comment