Jika Kalian menemukan Gambar Rusak / Terpotong / Tidak Terload Silahkan Lapor ke [chatango] atau [disini]

3.Bayangan dalam nyala api
—
Segitiga Api – Penjaga yang Terbangun
Kemarin.
Pak Parman perlahan menggulung peta tua yang terbentang di atas lantai pendapa. Ia menunjuk tiga titik yang dilingkari tinta pudar: lereng Merapi, hutan Wonosadi di barat, dan patahan batu di selatan Magelang.
“Segitiga ini bukan sekadar batas tanah. Sejak lama, orang-orang tua menyebutnya sebagai ‘penjaga keseimbangan.’ Tapi… penjaga untuk apa, sampai sekarang pun belum ada yang benar-benar tahu.”
Mbah Suro menunduk, mengelus jenggotnya yang mulai beruban sepenuhnya.
“Hanya cerita-cerita tua. Katanya, kalau tiga titik ini terganggu… sesuatu yang sudah lama tidur akan terbangun. Tapi cerita itu berhenti sampai di situ. Tak pernah ada yang tahu siapa atau apa yang tidur itu.”
Romo Seto, dengan tenang tapi tegang, berkata pelan.
“Dan kita… hanya bisa melihat gejalanya. Api yang muncul tanpa pembakaran. Panas yang tak memerlukan bahan bakar. Mungkin Banaspati adalah salah satu gejalanya… atau hanya penjaga pintu pertama.”
Ki Prayitno menghela napas, menatap jauh ke utara.
“Yang membuatku khawatir… siapa yang berani mengusik segitiga ini sekarang? Dan untuk apa?”
Pak Parman melipat peta dengan perlahan, suaranya lebih pelan.
“Kalau cuma orang yang iseng, ini terlalu rapi. Tapi kalau memang ada niat… maka niatnya belum kita mengerti.”
Mbah Suro mendongak, menatap bayangan lampu yang bergoyang.
“Apa mungkin Banaspati pun tidak tahu, dia hanya dipanggil… tapi bukan dia yang diinginkan?”
Keheningan kembali turun. Hanya suara serangga malam yang mengisi pendapa tua itu.
Ki Prayitno akhirnya berdiri.
“Yang pasti, kalau kita diam, apinya akan melebar. Entah siapa yang menyalakannya, entah apa tujuannya.”
Romo Seto menggenggam salib kecilnya, berbisik.
“Tapi kita harus bergerak tanpa tahu musuhnya. Seperti berjalan dalam kabut.”
Pak Parman berdiri, merapikan kain batiknya.
“Lebih baik bergerak dalam kabut, daripada menunggu sampai kabut itu jadi api.”
Mereka berempat saling menatap, tahu bahwa malam itu hanya awal dari sesuatu yang belum bisa mereka namai.
—
Di Luar Pendapa
Angin membawa dingin yang aneh, seperti bisikan tanah tua yang bangkit dari tidur panjangnya. Dan dari jauh, di lereng gunung, api yang seharusnya padam justru membentuk cahaya samar, seolah menunggu sesuatu… atau seseorang.
—
Bab: Yang Kau Bakar Bukan Hanya Tanah Ini
Angin malam berputar lambat di antara mereka.
Bukan sekadar angin, melainkan semacam jarak yang tak kasat mata, memisahkan dua makhluk dari dua dunia berbeda.
Arno berdiri tegak, dadanya naik turun menahan emosi yang mulai mendidih. Suara Banaspati masih menggema di telinganya, suara yang berbicara seperti bumi yang bosan akan keluhan manusia.
Tapi kini Arno tak bicara soal bumi.
Ia bicara soal Aini.
Arno menatap tajam, suaranya tegas menusuk malam yang berat.
“Kau sudah membakar ladang. Kau sudah menghancurkan semua yang kau lewati. Tapi ada satu hal yang kau ambil… yang bukan milikmu.”
Banaspati hanya diam.
Api di sekelilingnya perlahan mengecil, seperti menunggu kelanjutan ucapan manusia itu.
Arno menahan napas, lalu berkata lagi, suaranya bergetar tapi kuat.
“Kembalikan Aini.”
Dari dalam pikirannya, Svarnavarna berdesis pelan, dingin dan mengiris.
“Ah, akhirnya sampai juga ke intinya. Semua pidato tentang bumi, tentang keadilan, akhirnya runtuh oleh satu nama.”
Ia tertawa lirih, getir.
“Kau kira Banaspati peduli pada kehilanganmu, bocah?”
Akhirnya Banaspati bersuara. Suaranya berat dan lambat, seperti batu yang menggelinding di lembah sunyi.
“Aini… Oh… nama gadis itu Aini?”
Dia menarik napas, atau mungkin hanya mengeluarkan uap panas dari rongganya yang hitam.
“Dia bukan milikku untuk diambil atau dikembalikan.”
“Dia yang melangkah ke jalanku… bukan aku yang menariknya.”
Arno mengepalkan tangan, matanya berkilat penuh kemarahan.
“Kau membakar jalannya! Kau menciptakan ketakutan yang menyeretnya ke sana!”
Banaspati menatapnya tanpa ekspresi. Api di matanya tetap tenang, tidak bergolak.
“Ketakutan bukan ciptaanku.
Ketakutan adalah bayangan dari ulah kalian sendiri.”
Ia melangkah pelan, mendekatkan hawa panas ke tubuh Arno.
Belum membakar, tapi cukup untuk membuat kulit terasa ditusuk jarum panas.
“Aku membakar karena dunia ini meminta.
Jika Aini terjebak dalam jalanku, itu karena manusia-manusia seperti kalian meninggalkannya sendirian dalam gelap.”
Arno menarik napas dalam, menahan emosi yang nyaris meledak. Suaranya pelan tapi tajam.
“Lalu sekarang aku menjemputnya keluar dari gelap itu. Kau mau menghalangi?”
Banaspati berhenti.
Suasana hening, kecuali desir api yang samar.
“Menghalangi? Tidak.”
“Tapi kau harus tahu, setiap yang memasuki jalanku… tidak pernah kembali sama. Bahkan jika kau menemukannya, mungkin dia bukan lagi seperti yang kau ingat.”
Svarnavarna tertawa lirih di benaknya, seperti bayangan yang gemetar dalam bara.
“Dengar itu, bocah. Dunia berubah siapa pun yang melaluinya. Kau masih ingin melangkah?”
Arno mengepalkan tangan lebih erat, matanya tajam.
“Aku akan melangkah. Sekalipun yang kutemukan nanti bukan Aini yang dulu… aku akan tetap menjemputnya.”
Banaspati diam lama, seolah menimbang. Api di bahunya bergoyang perlahan seperti daun yang digerakkan angin.
Lalu suaranya terdengar, pelan tapi dalam:
“Baiklah.
Pergilah ke jantung apiku.
Temukan dia… jika kau sanggup melewati apa yang membara di sana.
Tapi itu juga jika kau sanggup mengalahkanku terlebih dulu.”
Banaspati tertawa, nyala api di tubuhnya bergerak liar seiring suara tawa yang menggema itu.
—
Bab: Api yang Tidak Memberi Ampun
Tawa Banaspati belum sepenuhnya reda ketika ia mengayunkan lengannya ke depan.
Dari telapak tangannya yang retak-retak, semburan api melesat deras, bukan seperti kobaran biasa, melainkan aliran lahar yang dilepaskan dengan amarah dunia yang terpendam.
Arno melompat ke samping, tubuhnya nyaris tersambar panas yang membakar udara itu. Tapi gelombang panasnya tak bisa dihindari. Kulitnya terasa seperti didekap bara. Udara tipis menusuk paru-parunya.
Svarnavarna berdesis tajam dalam benaknya, dingin seperti bayangan yang menunggu di balik cahaya.
“Jangan bergerak seperti manusia biasa, bocah. Tubuhmu rapuh, tapi kekuatan bayangan sudah ada dalam darahmu.”
“Gunakan aku… atau kita berdua akan terbakar seperti daun kering.”
Arno mengepalkan tangan. Ia tahu bayangan itu ada, menyatu di sela-sela nadinya. Tapi tubuhnya belum terbiasa, belum sepenuhnya sanggup menanggung kekuatan itu.
Banaspati menghentakkan kedua tangannya ke tanah.
Retakan-retakan merah menyebar dari bawah kakinya, membentuk lingkaran panas yang membara.
Dari celah-celah itu, lidah-lidah api menjulur tinggi, mengepung Arno dari segala arah.
“Di mana keberanianmu tadi, manusia kecil?” suara Banaspati menggema, berat seperti kawah yang berbicara.
“Kau mau menjemput gadismu? Maka lewatilah apiku lebih dulu!”
Arno menggertakkan gigi, lalu mendorong tangannya ke depan.
Bayangan hitam merayap keluar, membentuk bilah tipis yang melesat menuju dada Banaspati.
Tapi saat menyentuh tubuh sang penjaga api, bayangan itu langsung menguap, hancur tanpa bekas, ditelan panas yang tak kenal ampun.
Banaspati tersenyum tipis, lebih seperti ejekan daripada keramahan.
“Itu? Senjata gelapmu? Bahkan bayangan pun terbakar di jalanku.”
Arno terhuyung, tubuhnya bergetar hebat. Setiap kali ia memanggil kekuatan itu, tubuhnya terasa retak dari dalam. Tapi ia memaksa sekali lagi-mendorong lebih kuat, memanggil lebih dalam.
Bayangan lain melesat, lebih besar, lebih cepat. Tapi hasilnya tetap sama.
Begitu menyentuh panas Banaspati, ia lenyap tanpa jejak. Seperti kabut yang dipanggang matahari.
Banaspati melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan jejak bara yang tak kunjung padam.
“Aku tidak membenci manusia,” katanya datar, suaranya seperti batu yang tergerus waktu.
“Aku hanya muak melihat mereka datang memohon maaf setelah semuanya terlambat.”
Lalu tiba-tiba, Banaspati mengangkat tangan kirinya.
Sebilah tombak api murni terbentuk dari lengannya, lalu melesat cepat menuju Arno, membelah udara dengan deru panas yang memekakkan.
Arno berusaha membentuk pelindung bayangan, tapi kekuatannya masih mentah. Tak utuh.
Tombak itu menghantam pertahanannya seperti petir menghantam ranting kering.
Tubuhnya terpental, terlempar beberapa meter, menghantam tanah keras yang panasnya membara.
Darah bercampur dengan debu dan abu.
Semua terasa jauh. Dunia berputar pelan, seperti mimpi buruk yang lamban.
Suara api, tanah yang retak, dan tawa Banaspati menggema dari kejauhan yang menyakitkan.
Svarnavarna masih terdengar, suaranya pelan seperti bisikan dari jurang yang dalam.
“Tubuhmu belum kuat, bocah… Tapi mundur sekarang berarti mengakhiri segalanya.”
Arno terbaring. Pandangannya buram, dadanya naik turun dengan napas yang makin berat.
Di antara rasa sakit yang menyesakkan, hanya satu nama yang bertahan dalam benaknya.
Aini.
Tangannya bergetar, mencoba meraih udara yang panas dan berat.
Tapi yang ia temukan hanya rasa sesak, seperti dunia sedang menghimpitnya perlahan hingga tak bersisa.
Banaspati berdiri tegak di kejauhan, apinya berkilau terang seperti mercusuar api di tengah malam yang hitam.
“Manusia… kalian lemah bukan karena api. Tapi karena kalian selalu berharap ada yang memadamkan api untuk kalian.”
Dan malam itu, Arno terkapar di tanah, di antara panas yang tak kunjung surut.
Napasnya tersendat, tubuhnya mulai kehilangan rasa.
Belum mati.
Tapi sudah hampir habis.
—
Bab: Jejak yang Membingungkan
Malam mulai melingkupi lereng dengan kabut tipis yang turun perlahan, seperti tirai samar yang memisahkan kenyataan dan sesuatu yang belum mereka pahami sepenuhnya. Pak Parman melangkah cepat ke arah tempat Aini terakhir terlihat, diikuti Ki Prayitno dan Romo Seto, wajah mereka tegang, dihimpit cemas dan keraguan.
Ki Prayitno berkata dengan tegas namun menahan cemas,
“Dia belum jauh… semoga belum melewati batas yang kita tak bisa ikuti.”
Di belakang mereka, Mbah Suro berhenti sejenak. Ia mencabut sebilah keris kecil dan menancapkannya ke tanah, sambil melafalkan mantra pelindung warisan leluhurnya.
Dengan bisikan perlahan, Mbah Suro berkata,
“Tanah yang diam, tunjukkan jalan. Jangan biarkan yang hilang tertelan malam.”
Perlahan, keris itu bergetar halus. Kabut di depan mereka terbelah tipis, memunculkan jejak kaki samar bercahaya kemerahan. Bukan api, bukan arang, lebih seperti bayangan panas yang tertinggal sebentar lalu memudar.
Pak Parman menahan napas, waspada,
“Itu dia… jejaknya belum lama. Kita ikuti, jangan sampai hilang.”
Mereka bergerak cepat, mengikuti jejak itu. Namun semakin jauh mereka berjalan, hawa di sekitar berubah aneh-seperti panas yang menekan udara, padahal malam baru saja jatuh.
Tiba-tiba, jejak itu berhenti mendadak di balik batu besar. Tak ada bekas perlawanan, tak ada tanda ke mana Aini pergi. Sunyi. Seolah ia hilang begitu saja.
Pak Parman berlutut, meraba tanah yang masih hangat.
“Dia tidak jatuh. Seperti ditarik… atau memang masuk ke sesuatu yang tersembunyi.”
Ki Prayitno berdiri, memandang sekitar dengan wajah keruh.
“Kalau ini benar seperti yang dikisahkan orang tua dulu… tiga titik itu bukan sekadar tempat angker. Tapi jalur. Dan kalau satu terbuka, dua lainnya ikut terganggu.”
Romo Seto membuka peta kecil yang mulai lusuh, menunjuk dua titik yang lain.
“Wonosadi di barat, patahan batu di selatan. Kalau salah satu tempat itu ikut aktif, kita bisa kehilangan Aini selamanya.”
Mereka terdiam. Mitos itu hanya sebatas cerita selama ini. Mereka tidak pernah berpikir akan menghadapinya langsung.
Ki Prayitno menghela napas, lalu memutuskan cepat.
“Kita bagi dua. Aku dan Mbah Suro ke patahan batu. Pak Parman dan Romo Seto ke Wonosadi. Kita periksa apakah dua tempat itu juga mulai ‘bergerak’.”
Pak Parman mengangguk berat, meski hatinya ingin terus mencari Aini di tempat yang sama.
“Kalau kita abaikan dua titik itu… mungkin yang membawa Aini akan semakin kuat.”
Mbah Suro menancapkan seutas tali merah kecil di dekat batu besar.
“Kalau Aini kembali ke sini, dia tahu ke mana kita pergi.”
Ki Prayitno memandang ke arah barat dan selatan. Malam makin pekat, dan angin yang tadi dingin kini terasa berat, seperti membawa kabar buruk.
“Kalian ke barat, lewat ladang kopi menuju Wonosadi. Kami ke selatan, lewat Kalikuning ke patahan batu. Medannya berat, tapi kalau kita lambat, semuanya bisa terlambat.”
Pak Parman menepuk bahu Ki Prayitno.
“Kita belum tahu cara menutupnya… tapi paling tidak, kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana.”
Romo Seto menarik napas panjang, menahan keraguan yang mulai menyelinap.
“Kita jalan. Doakan Aini tetap bertahan sampai kita kembali.”
Mereka saling menatap sejenak, saling memahami risiko yang mereka hadapi. Lalu mereka berpisah dalam senyap malam.
Pak Parman dan Romo Seto bergerak ke barat, menyusuri jalur sempit di antara ladang kopi dan semak belukar. Sementara Ki Prayitno dan Mbah Suro menuruni jalur terjal menuju lembah Kalikuning, lalu berputar ke arah selatan menuju patahan batu yang selama ini hanya disebut dalam kisah-kisah tua.
—
Bab: Kejaran Waktu
Langkah mereka berpacu melawan waktu dan bayangan kecemasan yang belum berbentuk.
Pak Parman dan Romo Seto harus melewati dua bukit kecil dan lembah-lembah yang sunyi. Jalan setapak tertutup daun basah dan ranting patah. Mereka memperkirakan dua jam lagi baru tiba di tepian hutan Wonosadi-itu pun jika tak ada rintangan.
Sementara itu, Ki Prayitno dan Mbah Suro menyeberangi sungai kecil yang dingin, lalu menyusuri jalur berbatu menuju patahan tua. Tanahnya licin dan rawan longsor. Dengan kecepatan mereka, paling cepat tiga jam lagi mereka sampai.
Malam semakin dingin, namun dari sela-sela tanah terasa hembusan panas yang tidak wajar-seolah ada sesuatu yang perlahan bergerak di bawah kaki mereka.
Mereka berjalan dalam diam. Tak ada yang berani bersuara, hanya suara napas yang berat dan langkah-langkah cepat, berpacu dengan sesuatu yang belum mereka lihat, tapi sudah mereka rasakan.
Di belakang, kabut tipis turun perlahan, menelan jejak-jejak yang baru saja mereka tinggalkan. Seolah malam itu sendiri berusaha menyembunyikan kisah mereka dari dunia luar.
—
Mereka tahu mereka sedang menghadapi mitos lama yang perlahan menjadi nyata.
Tapi mereka belum tahu apa yang bangkit dari tempat-tempat itu,
dan bagaimana caranya mengakhiri semuanya…
Sebelum segalanya terlambat.
—
Bab: Satu Napas Terakhir
Tanah di sekelilingnya masih panas, membakar telapak tangannya yang gemetar saat ia mencoba bertumpu untuk bangkit.
Darah mengalir dari pelipis, menetes ke tanah hitam yang berasap tipis.
Arno mengertakkan gigi. Dadanya sesak, seperti diikat tali api yang makin mengencang setiap kali ia menarik napas.
Tapi dia tahu, jika ia tetap diam, tamatlah segalanya.
Di kejauhan, Banaspati melangkah pelan.
Api di tubuhnya berdenyut perlahan seperti nadi bumi yang sudah tak sabar melepaskan murka.
Langkahnya terdengar seperti batu-batu berat yang dihantam palu godam.
“Masih ingin berdiri, manusia kecil?” suara Banaspati serak dan berat.
“Tubuhmu bahkan sudah nyaris menjadi abu.”
Arno memaksa lututnya menopang tubuhnya yang nyaris remuk.
Ia tahu, melawan api itu sekarang mustahil. Satu-satunya jalan hanya bertahan.
Setidaknya, sampai ia menemukan celah.
Banaspati menghentakkan lengannya ke udara.
Dari telapak tangannya, semburan api meledak seperti cambuk panas, meluncur ke arah Arno dengan kecepatan yang sulit dihindari.
Dengan sisa tenaga, Arno melompat ke samping. Tubuhnya jatuh berguling, dan kulitnya terasa tersayat panas meski api itu tak langsung mengenainya.
Satu putaran lagi, dan ia nyaris terjerembab ke dalam retakan tanah yang berapi.
Svarnavarna berbisik lirih, nyaris seperti gumaman jauh di sudut benaknya.
“Jangan berpikir untuk menang sekarang. Bertahanlah dulu, bocah… bertahanlah.”
Banaspati melangkah maju lagi, langkahnya lebih cepat.
Kali ini kedua tangannya menghantam tanah, dan dari retakan itu, lingkaran api meluas cepat, seperti gelombang panas yang menyebar dari pusat letusan gunung.
Arno mencoba berlari, tapi kakinya lemah, membuatnya hanya bisa melompat pendek, jatuh terduduk di sisi batu besar yang menghitam.
Panas merayap mendekat. Batu itu mulai retak.
Tak ada tempat aman.
Napasnya semakin berat. Dunia mulai berputar.
Namun dalam pikirannya, satu suara menggema, jelas seperti lonceng di tengah kekacauan:
“Aini masih di sana. Kau belum selesai.”
Dengan susah payah, Arno menarik dirinya berdiri, bersandar di batu yang panasnya membakar punggungnya.
Tubuhnya bergetar, tapi matanya tetap menatap Banaspati yang kini berdiri beberapa langkah di depannya, nyala apinya bergoyang liar.
“Masih ingin mencoba?” Banaspati mengangkat tangan kanannya, api melingkar seperti ular yang hendak menerkam.
“Aku bisa membuatmu hilang dalam satu napas, manusia kecil.”
Arno menarik napas pelan, meski dada terasa seperti diremas.
“Kalau memang harus hilang… biarlah aku hilang saat masih berusaha.”
Banaspati hanya menatap, tanpa emosi.
Lalu ia lemparkan bola api besar, meluncur deras, menerangi malam seperti matahari kecil yang terjun dari langit.
Arno mendorong tubuhnya ke samping, terjatuh berguling, nyaris tak sempat menghindari ledakan yang menghancurkan tanah tempat ia berdiri barusan.
Debu, panas, dan bara beterbangan di sekelilingnya.
Tubuhnya lemah. Kakinya gemetar.
Tapi pikirannya tetap menggenggam satu nama.
Aini.
Ia tahu, jika ia jatuh lagi, mungkin tak akan bisa bangkit.
Tapi selama matanya masih terbuka, dan kakinya masih bisa bergerak, ia akan terus bertahan.
Banaspati mendekat, perlahan namun pasti.
Arno mengatupkan rahangnya erat.
Malam itu, di antara panas yang menggulung bumi, ia berdiri lagi.
Bukan dengan kekuatan sempurna.
Tapi dengan tekad yang belum padam.
—
Bab: Langkah yang Dikejar Malam
Pak Parman dan Romo Seto menuruni lereng dengan napas terengah. Jalan setapak yang mereka lalui perlahan berubah menjadi jalur berbatu yang licin, dipenuhi semak dan akar-akar liar. Sesekali suara ranting patah dihempas angin malam, namun segera tenggelam dalam kesunyian.
“Kalau kita lambat satu jam saja, mungkin kita cuma akan menemukan jejaknya yang dingin,” kata Pak Parman, matanya menatap tajam ke depan, menembus kegelapan.
Romo Seto mengangguk, menahan letih. “Aku ingat Pak Riyono sering parkir motor tuanya di pondok kebun kopi. Kalau kita beruntung, dia belum pulang.”
Mereka mempercepat langkah ke arah pondok kayu kecil yang berdiri di antara ladang kopi. Di sana, lampu petromaks redup masih tergantung di tiang bambu, dan terdengar suara mesin motor tua mengerang pelan.
Pak Riyono, lelaki paruh baya dengan wajah keras karena terbakar matahari, berdiri di depan pondok. Ia terkejut melihat keduanya datang tergesa-gesa.
“Pak Parman? Ada apa malam-malam begini?”
“Kami harus ke Wonosadi secepat mungkin, Riyono. Bisakah kami pinjam motormu?”
Pak Riyono mengangguk tanpa banyak tanya. “Bawa saja. Tapi hati-hati, jalur barat habis longsor kemarin. Kalian harus potong jalan lewat tebing kecil di atas ladang.”
Tanpa membuang waktu, Pak Parman dan Romo Seto menaiki motor tua itu. Suara knalpotnya memecah keheningan malam, menandai langkah tergesa mereka menuju Wonosadi melalui jalur yang sempit dan terjal.
—
Sementara itu, di lembah Kalikuning, Ki Prayitno dan Mbah Suro menyusuri jalur sempit dengan langkah cepat. Sungai kecil di bawah kaki mereka berkilau pucat diterpa cahaya bulan. Mereka tahu waktu mereka semakin menipis.
Di tengah perjalanan, terdengar suara mesin mendekat dari arah barat daya. Sebuah jip tua berhenti mendadak di tikungan sempit. Sopirnya, seorang pemuda dari desa bawah bernama Bowo, menurunkan kaca jendelanya.
“Ki Prayitno? Apa yang kalian lakukan di sini malam-malam?”
“Kami harus ke patahan batu. Segera. Bisa antarkan kami sampai jalur terakhir?”
Bowo menatap ragu, tapi melihat wajah serius mereka, ia hanya mengangguk.
“Naiklah. Tapi jalannya sempit dan licin, kita mungkin harus jalan kaki di ujung.”
Tanpa bicara banyak, mereka masuk ke dalam jip. Suara mesin tua itu meraung pelan, menerobos jalur sempit di antara semak belukar dan batuan longsor. Jip itu berhenti di tepi hutan kecil, jalan berikutnya hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki.
“Sampai sini saja. Kalau lebih jauh, ban bisa terperosok,” kata Bowo.
Ki Prayitno dan Mbah Suro turun. Mereka berterima kasih singkat, lalu melanjutkan perjalanan menapaki lereng terakhir menuju patahan batu yang sunyi dan penuh bayang-bayang.
—
Waktu mereka hanya tersisa beberapa jam sebelum subuh. Suara kendaraan yang perlahan menjauh meninggalkan mereka berdua dalam sunyi malam. Langkah mereka kini lebih cepat, bukan karena kekuatan tubuh, tapi karena kesadaran bahwa menunda berarti kehilangan kesempatan terakhir.
Jauh di belakang, malam perlahan menelan jejak-jejak mereka, menyisakan hanya bayang samar di jalur yang dingin.
—
Bab: Kesendirian yang Membisu
Aini terbangun dengan kepala berat, tubuhnya seperti dibungkus sesuatu yang dingin dan lembab. Udara di sekelilingnya berbau tanah basah dan lumut tua, menusuk hidung dengan dingin yang membekukan. Ia mencoba mengangkat tubuhnya, tapi segera menyadari: ada sesuatu yang menahan. Pergelangan tangan dan kakinya terasa tertarik oleh kekuatan yang tak tampak, seperti tali halus namun kuat yang melingkari tubuhnya.
Ia mengerjapkan mata, menatap ke sekeliling yang gelap gulita. Hanya ada sedikit cahaya samar yang merembes dari celah-celah batu di atasnya-terlalu redup untuk menerangi jalan keluar, tapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa ia sendirian, terperangkap.
Ingatannya berkelebat pelan. Suara Pak Parman yang memanggilnya… langkah-langkah yang tergesa… lalu perasaan ditarik ke dalam kehampaan yang dingin, seperti terhisap oleh sesuatu yang tidak ia lihat.
“Di mana ini…?” bisiknya pelan. Suaranya sendiri terdengar seperti dipantulkan dinding batu yang dingin, lalu lenyap ditelan kesunyian.
Ia mencoba meronta, tapi ikatan itu seperti merespons gerakannya-semakin ia berusaha melepaskan diri, semakin erat cengkeramannya. Bukan tali biasa, bukan rantai besi, melainkan semacam energi gaib yang membelit tubuhnya, dingin namun hidup, seperti makhluk yang bernafas bersama ketakutannya.
Beberapa kali ia mencoba menendang dan menarik tangannya, namun hasilnya nihil. Hanya getaran kecil yang merambat di sepanjang dinding batu, lalu hilang begitu saja, seolah tempat ini menelan setiap usaha perlawanan.
“Pak Parman… Ki Prayitno… Mbah Suro…” panggilnya lirih. Tapi hanya keheningan yang menjawab. Bahkan gema suaranya terdengar lambat, seperti waktu yang berjalan malas.
Dadanya mulai sesak. Ia ingin berlari, ingin keluar dari sini, tapi bahkan berdiri pun tak mampu. Yang bisa ia lakukan hanya duduk bersandar pada dinding yang dingin, menunggu sesuatu yang ia sendiri tak tahu apa.
Di antara rasa takut yang merayap pelan, muncul keputusasaan. Mungkin tak ada yang bisa mendengarnya. Mungkin tempat ini berada jauh di bawah tanah, atau lebih buruk lagi-di tempat yang tak lagi tersentuh oleh dunia manusia.
Ia menundukkan kepala, pundaknya bergetar menahan isak yang perlahan meleleh. Untuk sesaat, kekuatan yang selama ini ia tahan runtuh juga. Ia lelah. Bukan hanya lelah fisik, tapi lelah melawan rasa sendiri yang semakin kuat mencengkramnya.
Namun di tengah keputusasaan itu, Aini menggertakkan giginya pelan. Ia tahu, menyerah di sini berarti membiarkan tempat ini menelannya bulat-bulat. Jika ia berhenti berharap, tidak akan ada lagi alasan untuk bangun esok hari-jika esok hari memang masih ada.
Ia menutup mata, menarik napas pelan. Satu-satunya hal yang masih ia rasakan adalah denyut jantungnya sendiri. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia masih hidup.
Ia tidak tahu bagaimana caranya keluar. Ia tidak tahu apa yang menahannya. Tapi selama jantungnya masih berdetak, ia tidak boleh berhenti melawan.
Untuk saat ini, ia hanya bisa menunggu. Tapi menunggu dengan keyakinan, bukan dengan putus asa.
Di kejauhan, entah dari mana, terdengar suara samar seperti desir angin-atau mungkin hanya ilusi yang diciptakan pikirannya yang nyaris hancur.
Namun Aini tetap bertahan, menggenggam erat satu-satunya kekuatan yang ia punya: harapan kecil yang tak boleh padam.
—
Bab: Tubuh yang Hanya Menunggu Hangus
Banaspati berhenti sejenak, menatap Arno yang masih berdiri meski nyaris roboh.
Api di sekelilingnya berputar perlahan, seperti binatang buas yang mengelilingi mangsanya, menunggu waktu yang tepat untuk mencabik.
“Bertahan bukan berarti kau kuat, manusia,” suara Banaspati seperti batu yang digerus ribuan tahun.
“Bertahan hanya menunda kehancuranmu.”
Arno mengepalkan tangan. Tubuhnya sudah nyaris mati rasa, tapi bayangan hitam masih berusaha keluar dari pori-porinya.
Ia hantamkan satu pukulan bayangan ke arah Banaspati-kilatan gelap yang memotong udara.
Tapi sama seperti sebelumnya, bayangan itu tak ubahnya asap yang hancur diterpa panas.
Menyentuh tubuh Banaspati saja tidak sempat.
Banaspati mengayunkan lengannya ke samping.
Gelombang api melebar seperti kipas raksasa, menyapu Arno dan tanah di sekelilingnya.
Tubuh Arno terpental, jatuh berguling berkali-kali, menabrak batu panas yang mulai retak.
Debu bercampur darah memenuhi mulut dan hidungnya.
Svarnavarna berbisik, suaranya lirih dan berat.
“Tubuhmu belum cukup. Kau terlalu kecil untuk melawan murka seperti ini.”
Tapi Arno hanya mengertakkan gigi, bangkit setengah sadar, lalu mencoba menyerang lagi.
Kali ini ia membentuk tombak bayangan tipis, dilemparkannya dengan sisa tenaga yang nyaris habis.
Banaspati menepuk tombak bayangan itu dengan satu tangan, dan dalam sekejap, tombak itu hancur jadi debu hitam, tersapu angin panas.
“Begitu mudahnya kalian mengira kegelapan adalah jawaban untuk api,” ucap Banaspati, perlahan melangkah mendekat.
“Kalian lupa… aku lahir sebelum kegelapan kalian memahami dirinya sendiri.”
Lalu tanpa peringatan, Banaspati menghentakkan kedua tangannya ke depan.
Dua pilar api menjulang dari tanah, menghimpit Arno dari kanan dan kiri.
Panasnya seperti menekan dadanya hingga nyaris meledak.
Arno berteriak, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya tak sanggup menahan lagi.
Setiap ototnya seolah robek dari dalam.
Bayangan yang keluar dari tubuhnya bukan lagi serangan, tapi hanya percikan nyeri yang menyebar tanpa arah.
Banaspati mendekat, kini berdiri hanya beberapa langkah di depannya.
Api di matanya tenang, dingin seperti seseorang yang sudah lama berhenti peduli.
“Berhentilah,” kata Banaspati datar.
“Tak ada yang bisa kau lakukan di sini.”
Arno menggertakkan gigi. Darah menetes dari sudut bibirnya.
“Kalau aku berhenti… Aini tidak akan pernah kembali.”
Banaspati mengangkat tangan kanannya perlahan, api berputar seperti pusaran topan kecil.
“Lalu habislah kau di sini.”
Seketika itu, pukulan api menghantam tubuh Arno secara langsung.
Tak ada waktu menghindar. Tak ada kekuatan bertahan.
Tubuhnya terhempas ke belakang, menghantam tanah yang mulai membelah, mengeluarkan uap panas dari retakannya.
Semua terasa buram. Dunia seperti berputar lambat.
Suara api, suara batu retak, suara desis Svarnavarna… semua bercampur seperti gema yang makin jauh.
Napas Arno tinggal satu-satu.
Dadanya berat, seolah tertimbun batu besar yang panasnya membakar dari dalam.
Di benaknya, satu-satunya hal yang tersisa hanya bayangan Aini… samar, nyaris hilang.
Dan untuk pertama kalinya, tubuhnya benar-benar tak sanggup bangkit lagi.
Hanya terbaring…
Menunggu apakah malam ini adalah akhirnya.
—
Bab: Nyala yang Tersembunyi
Malam telah mencapai puncak kelamnya ketika kedua kelompok itu mulai mendekati tujuan mereka masing-masing. Di barat, Pak Parman dan Romo Seto, dibantu Leman dan Sarto, akhirnya tiba di tepian hutan Wonosadi. Sementara itu, di selatan, Ki Prayitno dan Mbah Suro mulai menapaki jalur patahan batu yang terjal dan berbahaya.
—
Di Wonosadi
Kabut tipis menyelimuti hutan Wonosadi seperti selimut tua yang sudah lama tak digerakkan angin. Pohon-pohon kopi di sekitar tepi hutan tampak diam, tidak ada suara serangga, tidak ada gemerisik dedaunan. Semuanya terlalu tenang, terlalu sunyi.
Pak Parman berhenti sejenak, matanya menyapu sekitar. “Tempat ini… sudah berubah. Sejak titik pertama terbuka, seluruh penjuru ikut terganggu.”
Romo Seto mengangguk, menggenggam salib kecil yang selalu ia bawa di leher. “Kau merasakan hawa panas dari tanah?”
Leman menunduk, meraba tanah dengan telapak tangan. “Tanahnya hangat, Pak. Seperti baru saja dilalui sesuatu yang membara.”
Mereka melangkah lebih dalam, mengikuti jalur setapak yang perlahan mengarah ke sebuah dataran kecil di tengah hutan. Di sana, samar-samar, terlihat lingkaran tanah yang menghitam, bekas terbakar, namun tidak ada api. Hanya bara halus yang berpendar redup, membentuk pola aneh di tanah.
Pak Parman mendekat, berlutut di tepi lingkaran itu. “Ini… titik kedua. Masih tertahan, tapi getarannya sudah mulai terasa.”
Namun saat ia hendak menyentuh tanah itu, tiba-tiba hawa panas memancar kuat, memaksa mereka mundur. Bara itu hidup, seolah sadar akan kehadiran mereka.
Romo Seto menarik Pak Parman ke belakang. “Kita belum tahu bagaimana menutupnya. Kalau kita gegabah, bisa-bisa malah membuka gerbangnya.”
Pak Parman menatap bara itu dengan gelisah. “Tapi kalau kita diam saja, bisa jadi kekuatan dari titik pertama akan memaksa tempat ini terbuka lebih cepat.”
—
Di Patahan Batu
Sementara itu, di selatan, Ki Prayitno dan Mbah Suro tiba di kaki patahan batu yang menjulang seperti tembok alami. Retakan-retakan besar membelah tebing, dan dari celah-celah itu, asap tipis kehitaman merayap keluar seperti napas makhluk tua yang terbangun dari tidur panjang.
Ki Prayitno mendongak, wajahnya keras. “Titik ketiga… inilah yang paling dalam. Jika terbuka, tak ada yang bisa menahannya lagi.”
Mbah Suro mencabut keris kecilnya, menancapkannya ke tanah. “Tapi siapa yang memulainya? Dan kenapa sekarang?”
Tanah tiba-tiba bergetar pelan. Retakan-retakan batu di depan mereka menyala samar, cahaya kemerahan yang merayap seperti akar neraka. Dari balik celah itu, terdengar suara dalam, berat, dan jauh… seperti suara bumi yang mengaduh.
Ki Prayitno mengepalkan tangan. “Satu titik sudah terbuka. Dua yang tersisa hanya menunggu. Kalau kita tak bertindak, semuanya akan runtuh bersamaan.”
Mbah Suro menunduk, merasakan hawa panas yang mulai memanjat kaki mereka. “Kita tak bisa menutup ini sendirian. Perlu lebih dari sekadar mantra. Kita butuh orang yang tahu akar dari ketiga titik ini…”
Ki Prayitno terdiam. Ia tahu siapa yang dimaksud Mbah Suro. Tapi orang itu sudah lama menghilang, atau mungkin sengaja menjauh dari semua ini.
—
Malam yang Bergerak
Di kedua titik itu, api tak kasatmata mulai menyala pelan. Bukan nyala yang bisa dilihat semua orang, tapi kekuatan yang perlahan membangkitkan sesuatu dari dalam tanah.
Dan sementara itu, di tempat yang lain, Aini masih terjebak dalam gelap. Tak sadar bahwa dua dunia sedang bersiap bertemu-dunia yang ia kenal, dan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih dalam, dan lebih berbahaya.
Bab: Sambutan Terakhir bagi yang Lemah (Bagian 1)
Tubuh Arno tergeletak tak berdaya di tanah yang mulai retak karena panas serangan Banaspati. Napasnya nyaris hilang, dan luka-luka di tubuhnya seperti celah yang menunggu kehancuran akhir. Banaspati berdiri di atasnya, tangan kanannya yang membara tinggal beberapa meter lagi dari dada Arno.
> Banaspati, suaranya bergema dingin dengan tawa kecil yang getir:
“Akhir yang menyedihkan untuk pahlawan yang datang kesiangan. Selamat tinggal..”
Ia mengayunkan telapak apinya, tanpa belas kasihan, siap menamatkan semuanya. Namun tepat saat itu-
Dari luka-luka Arno, sesuatu yang aneh mulai merembes keluar. Bukan darah, bukan cahaya, melainkan bayangan pekat, seperti asap hitam yang bergerak hidup, menggeliat, dan mulai menyelimuti tubuhnya perlahan. Asap itu dingin namun terasa hidup, berputar mengelilingi Arno yang tak sadarkan diri, seperti kabut yang melindungi istananya dari kehancuran.
Banaspati mendadak terdiam. Matanya yang menyala seperti bara menyipit, menelisik fenomena itu dengan nada geli bercampur penasaran. Tapi ia tak menarik serangannya. Justru sebaliknya, ia menghantamkan telapak apinya ke arah dada Arno yang sudah diselimuti kabut hitam itu.
Dan pada detik itulah… sesuatu yang tak terduga terjadi.
Dari balik pekatnya asap, sebuah tangan muncul-keras, kokoh, dan kini dilapisi semacam lapisan hitam berpendar merah seperti retakan magma. Tangan itu mencengkeram kuat serangan Banaspati, menahan panas dan ledakan yang seharusnya melelehkan batu.
Banaspati terbelalak.
Banaspati (gumam, nyaris tak percaya):
“Apa… ini…?”
Kabut hitam itu mulai surut perlahan, namun bukan lenyap-melainkan menyatu membentuk lapisan seperti kostum tempur. Tubuh Arno kini tertutup bayangan yang memadat, hitam berkilau samar dengan garis-garis merah menyala di dada dan lengannya, membentuk pola seperti urat api yang tertahan oleh malam. Wajahnya tersembunyi sebagian di balik topeng bayangan, hanya mata Arno yang bersinar tajam, menembus kegelapan.
Arno membuka matanya perlahan, napasnya berat namun mantap.
Arno (suara lebih dalam, resonan, seperti dua suara bergabung):
“Kalau kau pikir aku hanya manusia biasa… kau terlalu bodoh untuk hidup selama ini.”
Dari genggamannya, kekuatan bayangan itu beriak, mematahkan serangan Banaspati dalam satu hentakan. Api itu lenyap, seperti ditelan oleh kekosongan.
Banaspati mundur dua langkah, kini untuk pertama kalinya…
Namun Arno belum selesai.
Ia berdiri penuh, tubuhnya kini sepenuhnya dibalut kostum bayangan yang menyala samar. Angin malam mengitari mereka, membawa serta aroma akhir pertempuran yang belum selesai.
Arno, dingin namun mantap:
“Sekarang… giliranku.”




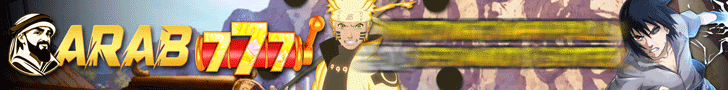
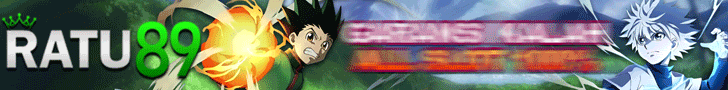



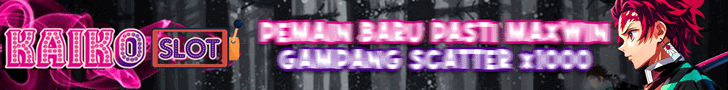

Comment