Jika Kalian menemukan Gambar Rusak / Terpotong / Tidak Terload Silahkan Lapor ke [chatango] atau [disini]

2.Pilihan yang tak bisa batalkan
Bab: Penyatuan yang Terlambat
Hujan turun deras, menusuk lorong-lorong kumuh yang sudah lama melupakan cahaya pagi. Bau besi karat, darah, dan air kotor bercampur jadi satu.
Arno jatuh berlutut. Tangan kirinya menekan luka besar di perut, sementara tangan kanannya gemetar tanpa daya. Nafasnya tersendat seperti pisau tumpul yang dipaksa menembus tenggorokan. Dunia berputar perlahan, kabur.
Langkah-langkah mendekat dari belakang, diseret bersama dendam.
“Sudah selesai, Arno!” “Kau pikir bisa lari selamanya?” “Semua utangmu lunas malam ini-dengan darahmu sendiri!”
Tak ada celah. Lorong sempit. Tubuh lemah. Udara dingin.
Lalu… sesuatu berubah.
Dari sudut lorong yang seharusnya kosong, muncul kabut hitam. Tipis, berputar pelan seperti asap rokok basi, lalu mengeras perlahan menjadi bayangan hitam tinggi, bermata kuning redup. Sosok itu berdiri diam, nyaris tanpa wujud, seperti mimpi buruk yang lupa bagaimana caranya bangun.
Arno mendongak. Pucat. Antara takut dan terlalu letih untuk takut.
“…Siapa… siapa kau?” suaranya serak, patah-patah.
Bayangan itu tertawa. Pelan. Suaranya seperti besi tua bergesekan di ruang kosong.
“Kau lucu sekali. Di ambang kematian, masih sempat bertanya basa-basi.”
“Aku? Ah, aku cuma… penyelamat sementara.”
Arno menyipitkan mata, mencoba tetap sadar.
“Penyelamat?”
“Kalau mau mengambil nyawaku, lakukan saja. Aku tak punya waktu dengar candaan setan.”
Bayangan itu mendekat perlahan. Kabutnya menyentuh tanah.
“Ah, justru itu masalahnya. Membunuhmu? Terlalu mudah. Terlalu membosankan.”
“Aku lebih suka… Memberi satu tawaran kepadamu.”
Arno meringis karna luka-lukanya terasa perih, lalu dengan sisa tenaganya dia menjawab;
“Sejujurnya.. Aku tidak punya waktu.. untuk tawar menawar..tapi sebelum aku mati.. Paling tidak aku.. akan dengar tawaranmu iblis.”
Sosok hitam itu tertawa terkekeh;
“Hehehe..tanpa basa-basi langsung saja; aku ingin meminjam tubuhmu sebentar. Sebagai gantinya, aku akan membantumu membereskan mereka dan..”
“Kau bisa hidup cukup lama untuk menyesalinya, tentu saja.”
Arno terdiam menahan batuk berdarah. Tubuhnya mulai limbung. Suara hujan menelan pikirannya.
“Kau… apa ini? Sebenarnya kau ini apa…?”
“Atau… neraka yang datang lebih cepat?”
Bayangan itu terkekeh, sinis.
“Kalau ini neraka, kau tak akan punya pilihan.”
“Tapi lihat dirimu sekarang. Bahkan untuk mati saja, kau butuh pertolongan.”
Langkah-langkah keras terdengar semakin dekat. Teriakan pengejar tak sabar.
“Cepat habisi dia!”
“Jangan main-main lagi!”
Bayangan itu mendesah pura-pura bosan.
“Ah, lihat. Waktumu habis. Ini kesempatan terakhir.
Terima aku. Pinjam kekuatanku. Dan sebagai gantinya… biarkan aku… tinggal sebentar.”
Arno menggertakkan gigi, darah menetes di bibirnya.
“Tinggal? Di mana? Badanku?”
Bayangan itu tertawa keras, nyaring seperti cemoohan alam semesta.
“Tepat sekali! Akhirnya kau paham. Kita berbagi ruang. Aku jadi tamu, kau… jadi tuan rumah yang sekarat.”
Arno menunduk, pasrah, namun masih bertanya:
“Kalau aku tolak?”
Bayangan itu tersenyum, suaranya seperti bisikan maut.
“Maka ini… adalah akhir yang sangat membosankan.”
Langkah para pengejar sudah hampir menyentuh punggungnya.
Arno mendesah lemah.
“…Baiklah. Untuk sekarang.”
Bayangan itu menyeringai puas.
“Selamat datang di kontrak yang tak bisa dibatalkan.”
Dan dalam sekejap, bayangan itu melesat, menyelubungi tubuh Arno. Kabut hitam itu masuk ke mulut, hidung, luka-luka terbuka.
Tubuhnya kejang hebat. Matanya membelalak. Rasanya seperti listrik dan api mengiris organ dalamnya.
“AAARRRGGHH-!!”
Di dalam pikirannya, suara itu terdengar lebih dingin, lebih dekat.
“Jangan melawan. Terima saja. Semakin kau melawan, semakin kau menderita.”
—
Pertarungan Dimulai
Tubuh Arno perlahan berdiri, gemetar, tapi tegak. Nafasnya kini stabil. Luka masih terbuka, tapi nyaris tak terasa.
Tiga pengejarnya berhenti. Mata mereka menyipit, bingung.
“Apa-apaan itu…?”
“Jangan ragu! Dia sudah sekarat!”
Salah satu dari mereka mengayunkan linggisnya, keras, ke arah kepala Arno.
Tapi Arno bergerak. Terlalu cepat. Tangannya menangkap linggis itu seolah hanya sepotong kayu rapuh.
Arno menatap si penyerang. Senyum tipis, dingin.
“Sayangnya aku tak sesekarat yang kalian bayangkan.”
Sekali hentak, ia memutar linggis itu dan menghantamkan ke dada pria itu. Suara tulang remuk menggema, tubuh itu terpental menghantam dinding dan terkapar.
Dua lainnya langsung menyerbu, satu dengan rantai berkarat, satu lagi dengan pisau panjang.
Svarnavarna berbisik sinis di kepalanya:
“Jangan bertahan. Hancurkan.”
Arno bergerak seperti bayangan yang mencambuk udara. Ia berputar, melompat ke dinding licin, meluncur turun, dan menghantam musuh kedua dengan lutut tepat ke rahang. Darah muncrat, pria itu terhempas ke tanah, tak bergerak.
Orang terakhir gemetar hebat, mundur dengan langkah terhuyung.
“Kau… bukan Arno… Kau apa… iblis?!”
Arno mendekat pelan, langkahnya mantap. Suaranya datar.
“Iblis? Bukan. Cuma sisa manusia yang kau buat putus asa.”
(Dalam kepala Arno sendiri: “Apa ini…? Tubuhku bergerak sendiri… Kenapa aku… bisa begini?!”)
Svarnavarna tertawa pelan, kejam:
“Lemah sendirian. Lengkap bersamaku. Sesederhana itu.”
Pria itu mencoba lari. Arno menendang tong logam di sampingnya-tong itu terbang dan menghantam punggung pria itu, menjatuhkannya ke genangan air kotor.
Arno berlutut di dekat kepala lawannya, berbisik pelan, hampir seperti lirih doa terbalik:
“Ingat wajahku… sebelum gelap menelanmu.”
Dan dengan satu pukulan terakhir, semua menjadi hening.
—
Setelah Pertarungan
Hujan masih mengguyur lorong yang kini penuh genangan darah.
Arno berdiri tegak, dadanya naik turun. Bajunya koyak, basah oleh darah dan hujan. Nafasnya berat, tapi stabil.
Di dalam pikirannya, suara itu masih terdengar, santai, seperti sedang menikmati secangkir teh di sore hari.
“Mudah, kan? Bertahan hidup itu soal berhenti berpura-pura jadi manusia sepenuhnya.”
Arno menatap kedua tangannya, gemetar. Tapi bukan karena dingin-karena takut pada dirinya sendiri.
“Kau… Siapa kau?” suaranya pelan.
Svarnavarna terkekeh.
“Seorang preman sekarang sudah berubah jadi wartawan ya?
Nama? Svarnavarna.
Gelar? Tidak penting.
Bayangan di kepalamu? Untuk sekarang… ya.”
Arno menunduk, menahan rasa muak dan takut bercampur jadi satu.
Ia tahu satu hal pasti: hidupnya tak akan pernah sama lagi.
—
Keesokan Harinya
Berita pagi penuh dengan kabar heboh.
“Pembantaian Brutal di Lorong Kota Tua! Tiga preman ditemukan tewas mengenaskan tanpa saksi mata.
Polisi belum bisa memastikan siapa pelakunya.
Warga sekitar mengaku mendengar teriakan, lalu hening seperti tak pernah terjadi apa-apa.”
Dan di lorong itu, hanya sisa genangan darah dan jejak kaki samar yang perlahan hilang ditelan hujan malam.
—
Bab: Suara yang Tidak Diam
Kilasan senja itu menghilang perlahan dari benaknya. Arno tersadar, duduk sendirian di bangku taman yang dingin, dengan teh manis yang sudah dingin di lambungnya. Napasnya pelan, tapi dadanya berat.
Dalam pikirannya, suara yang sudah ia kenal kembali menyapa, kali ini dengan nada seperti menggoda rasa sentimentilnya.
Svarnavarna:
“Romantis sekali. Kau melamun soal perempuan, sementara dunia masih menunggumu jatuh lagi.”
Arno menghela napas pendek.
Arno:
“Diamlah. Setidaknya dia… bukan bayangan yang ingin menguasai tubuh orang lain.”
Svarnavarna terkekeh kecil, nadanya seperti angin dingin yang masuk dari celah pintu.
Svarnavarna:
“Ah, tapi bukankah kita sama? Dia menulis tentang bayangan yang melindungi diam-diam. Aku? Bayangan yang melindungi dengan caraku sendiri. Cuma… metodenya sedikit lebih berdarah.”
Arno mengerutkan dahi.
Arno:
“Kau pikir semua yang kulakukan kemarin itu… penyelamatan?”
Svarnavarna mendesis pelan.
Svarnavarna:
“Tidak. Itu bertahan hidup. Jangan anggap dirimu pahlawan, Arno. Kita berdua tahu: malam itu kau hanya memilih cara mati yang lebih lambat.”
Diam sebentar. Hanya suara daun jatuh dan anak kecil bermain sepeda di kejauhan.
Arno bersandar, menatap langit yang perlahan menggelap.
Arno:
“Apa kau akan selalu ada di sini? Terus bicara seperti ini?”
Svarnavarna terdengar tertawa renyah.
Svarnavarna:
“Sampai batas waktu yang tidak bisa kutentukan, hmm..atau mungkin sampai salah satu dari kita menghilang. Yang mana yang lebih dulu… kita lihat saja.”
Arno menutup mata sebentar, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan.
Arno:
“Baiklah. Untuk sementara, kita bertahan dulu. Tapi dengar baik-baik… satu langkahmu yang membuatku kehilangan kendali, aku akan cari cara mengusirmu. Dengan cara apapun.”
Svarnavarna diam beberapa detik, lalu menjawab dengan nada setengah kagum, setengah mengejek:
Svarnavarna:
“Ancaman yang indah. Akhirnya kau mulai bicara seperti pemilik tubuhmu sendiri. Begitu terus, Arno. Kita akan bersenang-senang.”
Arno berdiri, merapikan ranselnya.
Langkahnya pelan, tapi kini sedikit lebih mantap dari biasanya.
Masih tanpa arah yang pasti, tapi paling tidak, kali ini ia tahu satu hal:
Perjalanannya belum selesai.
Dan di dalam dirinya… ada dua suara yang sama-sama tidak mau kalah.
—
Bab: Pertemuan di Tengah Tanda Tanya
Langkah Arno baru beberapa meter meninggalkan taman ketika suara berat tapi santai menghentikannya:
“Mas… jalan kok kayak baru kalah main catur sama hidup. Pelan amat.”
Arno menoleh pelan.
Di bawah lampu taman yang temaram, berdiri seorang pria paruh baya. Jas lusuh warna cokelat, topi pet miring, dan celana kain yang bagian lututnya mulai pudar. Tangan kirinya memegang bungkus rokok kosong, sementara tangan kanannya sibuk mencari korek yang entah di mana.
Senyumnya ramah, khas orang yang lebih sering ditertawakan hidup daripada tertawa karna bahagia.
“Nama saya Sidik. Bukan siapa-siapa, cuma petugas kecil yang kebagian ngintipin orang main judi malam-malam.”
(ia menunjuk ke arah gang kecil di belakang taman)
“Tadi ada kabar ada meja ceki liar. Eh, malah kosong. Dunia memang suka bercanda, Mas.”
Svarnavarna (berdesis pelan di kepala Arno):
“Ah, hebat. Udah tua, kerjaannya ngintipin orang main kartu. Luar biasa produktif, manusia satu ini.”
Sidik mendekat sedikit, masih dengan senyum santainya.
Sidik:
“Eh, saya lihat Mas duduk sendirian tadi. Nunggu temen ya? Atau lagi mikirin kenapa hidup nggak ada tombol reset-nya?”
Arno hanya menatap sebentar, lalu menghela napas pelan.
Arno:
“Lagi jalan aja, Pak. Angin sore, lumayan buat ngilangin beban kepala.”
Svarnavarna (nyinyir):
“Iya, ngilangin beban kepala… sayangnya hatimu masih berat kayak karung beras basah.”
Sidik tertawa pelan sambil akhirnya menemukan koreknya. Menyalakan sebatang kretek yang sudah setengah patah.
Sidik:
“Wah, bener juga. Jogja tuh kecil, tapi masalah orang-orangnya… kayak sungai kering musim kemarau. Kelihatan tenang, padahal retaknya di mana-mana.”
Ia meniup asap pelan, lalu menepuk kantong celananya sambil melirik Arno.
Sidik:
“Yowes lah, Mas. Tak ganggu bentar aja. Saya lanjut ngintipin orang main judi lagi. Siapa tahu dapet bonus lihat orang ribut soal hutang kalah kartu.”
Ia mulai melangkah pergi, tapi sebelum jauh, ia menoleh sambil tersenyum miring:
Sidik:
“Kalau besok sore Mas lewat sini lagi, jangan lupa bawa cerita baru. Biar saya nggak cuma ngobrol sama bayangan sendiri.”
Svarnavarna (sarkas pelan):
“Percaya deh, ngobrol sama bayangan sendiri jauh lebih waras daripada ngobrol sama kamu, Pak.”
Arno tersenyum tipis, akhirnya mengangguk pelan.
Arno:
“Iya, Pak. Hati-hati di jalan. Jangan sampai malah ikut main.”
Sidik tertawa lepas, melambaikan tangan santai.
Sidik:
“Kalau kalah main, tinggal ketawa. Yang penting jangan kalah hidup, Mas.”
Ia berlalu, menyusuri jalanan yang mulai sepi, meninggalkan bau kretek yang tertinggal samar.
Arno menatap langit yang mulai menghitam.
Svarnavarna (lembut tapi sinis):
“Lihat? Bahkan orang kayak dia masih bisa tertawa. Kamu kapan?”
Bab: Bayangan Api yang Bangkit
Malam belum sepenuhnya gelap ketika hawa panas aneh mulai merayap di sudut-sudut kota. Dari reruntuhan pabrik tua di pinggiran Kali Code, sesosok bayangan perlahan muncul dari kobaran api kecil yang menyala tanpa sebab. Sosok itu tinggi besar, tubuhnya seperti dilapisi arang yang retak-retak, dan dari celah retakan itu menyala bara merah membara.
Namanya hanya terdengar dari cerita rakyat yang sering di kisahkan orang tua jaman dulu: Banaspati.
Legenda lama menyebut Banaspati sebagai roh api yang dikutuk berjalan di bumi, membakar apa saja yang disentuhnya tanpa ampun. Tapi ini bukan sekadar cerita. Malam ini, ia berjalan nyata. Hawa tubuhnya membuat besi berkarat mengelupas, kayu kering meledak begitu disentuh, dan udara menjadi tipis seperti ditiupkan dari tungku purba.
Dari mulutnya, terdengar gumaman berat:
“Api tidak butuh alasan untuk membakar. Hanya butuh dunia yang terlalu dingin untuk hidup.”
Banaspati mengangkat tangannya, dan seketika itu pula, pipa-pipa tua di pabrik itu meledak satu per satu, memuntahkan lidah api ke langit malam. Kilat menyambar, tapi bukan menyambar tanah-kilat itu tertarik ke arah Banaspati, seolah api dan petir berebut singgasana.
—
Di Sudut Kota
Di pos penjagaan kecil dekat stasiun Tugu, alat pengukur suhu mendadak berbunyi nyaring. Angka-angka melonjak tak wajar.
“Suhu sekitar Kali Code naik 20 derajat dalam 5 menit! Ini bukan kebakaran biasa!”
Sementara itu, di pinggir jalan Malioboro, para pedagang kaki lima terpaksa menutup lapak lebih awal. Kompor sumbu mereka menyala terlalu besar, api obor menyembur liar, dan logam-logo becak terasa panas disentuh.
—
Kembali ke Pabrik
Banaspati melangkah pelan, tapi setiap langkahnya membakar jejak di tanah. Burung-burung malam berterbangan panik, udara terasa seperti terbakar dari dalam. Ia tak tergesa, karena api tidak pernah terburu-buru. Api hanya menunggu semua yang rapuh untuk jatuh dengan sendirinya.
Dari kejauhan, siluetnya tampak seperti raksasa bara yang berjalan di tengah dunia dingin.
—
Svarnavarna (suara dalam benak Arno, meski mereka jauh dari sana):
“Nah, bocah, lihatlah… satu lagi makhluk kesepian yang membakar dunia agar ada yang memperhatikannya.”
“Kalau kau pikir aku berisik, tunggu sampai kau dengar api itu bicara.”
“Tapi tenang, bocah. Kita belum waktunya bermain-main dengannya. Biarkan kota ini kepanasan dulu, siapa tahu ada yang sadar bahwa hidup itu nggak selalu sedingin hatimu.”
—
Tapi untuk malam ini, Banaspati belum mencari musuh. Ia hanya berjalan, membakar jalan setapak dunia yang terlalu lama diam dalam bayang-bayang.
—
Bab: Kota yang Mulai Resah
Malam itu, Jogja terasa seperti menahan napas. Jalanan yang biasanya riuh oleh suara angkringan dan obrolan santai mendadak lebih cepat sepi. Angin membawa hawa aneh-bukan dingin, bukan panas, tapi seperti ada sesuatu yang salah di udara.
Di sekitar Kali Code, beberapa warga saling menatap heran. Bau hangus samar-samar tercium, tapi tidak ada asap besar, tidak ada kobaran api yang jelas. Hanya… hawa berat yang membuat tengkuk terasa dingin.
“Listrik mati lagi?”
“Bukan, Lik. Ini kayak hawa mau badai, tapi langitnya cerah…”
“Tadi ada suara aneh, kayak… besi patah tapi jauh.”
Mereka saling memandang, mencoba tertawa untuk meredakan kecemasan. Tapi tawa itu terdengar hambar, seperti menunggu sesuatu yang lebih buruk.
—
Di Warung Kopi Pinggir Jalan
Beberapa tukang becak dan pedagang kaki lima berkumpul, membahas kejadian-kejadian kecil yang belum tentu terkait, tapi terasa ganjil:
“Tadi sore di utara, burung-burung tiba-tiba beterbangan semua, kayak dikejutkan sesuatu.”
“Di selatan, katanya sumur Pak Raji tiba-tiba panas. Airnya mendidih padahal nggak ada api.”
“Mungkin cuma kebetulan, Le. Atau… ya, jangan-jangan…”
Mereka berhenti bicara. Tak ada yang mau mengucapkan kata-kata buruk, seolah-olah jika diucapkan, itu akan menjadi nyata.
—
Di Kantor Polisi
Di pos polisi kecil, seorang perwira muda kebingungan membaca laporan warga.
“Pak, laporan kebakaran? Tapi nggak ada api.”
“Gempa? Tapi nggak ada getaran.”
“Terus ini apa? Orang-orang cuma bilang ‘nggak enak hati’, ‘hawanya aneh’.”
Seorang petugas senior hanya mendesah, menatap langit malam yang memerah samar dari kejauhan.
“Kalau hawanya begini… biasanya ada yang nggak beres. Tapi kita tunggu saja. Kadang jawaban datang sendiri.”
—
Di Rumah-rumah Tua
Orang-orang tua duduk di teras, diam, hanya memandangi langit. Beberapa menggenggam tasbih, sebagian lagi hanya menatap kosong.
Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi naluri tua mereka tahu: malam ini bukan malam biasa.
—
Di Kepala Arno
Svarnavarna tertawa lirih, nada suaranya seperti bayangan yang sedang menyeringai.
“Lihatlah, bocah… betapa lucunya manusia. Ketika mereka tidak tahu apa yang datang, mereka pura-pura tidak ada yang datang.”
“Padahal… sesuatu sedang bangkit. Dan mereka hanya duduk minum kopi sambil pura-pura sibuk mengobrol.”
Arno hanya menghela napas. Dia pun belum tahu apa yang sedang bangkit. Tapi nalurinya berkata: malam ini baru permulaan.
Bab: Bayangan yang Menyebar
Malam itu bukan hanya milik satu gang di Jogja.
Desas-desus tentang bayangan panas itu perlahan merambat ke luar kota.
Dari pasar-pasar tua di Kotagede, sampai terminal gelap di Sleman, dan bahkan jalan-jalan sunyi yang membelah persawahan menuju Magelang.
Di sebuah halte tua dekat Secang, seorang sopir truk yang biasa mengangkut hasil bumi berhenti mendadak. Mesin truknya mati tanpa sebab, lampu jalan berkedip-kedip seperti ketakutan.
Lalu… ia melihatnya.
Di antara kabut dini hari dan bayang pohon bambu, sesosok tubuh tinggi besar berjalan pelan, menyisakan jejak hangus di rerumputan basah.
Tak ada suara. Hanya hawa panas yang merayap pelan, membuat kulit seperti terbakar dari dalam.
Sopir itu tak berani turun. Ia hanya menutup wajah dengan tangan, berharap bayangan itu tak melihatnya.
—
Kabar yang Membingungkan
Keesokan paginya, kabar itu menyebar seperti air bah.
Tapi setiap orang menceritakannya dengan versi berbeda:
Ada yang bilang itu hantu api dari zaman Mataram kuno.
Ada yang bilang itu tentara Jepang yang arwahnya belum selesai membalas dendam.
Ada pula yang percaya, itu kutukan dari gunung di utara, yang bangkit karena manusia terlalu serakah.
Tapi satu hal sama:
Semua merasa lebih panas, lebih takut, dan lebih bingung.
—
Di Pos Polisi Magelang
Beberapa laporan warga mulai masuk:
“Pak, semalam ada sesuatu di sawah… ayam-ayam saya gosong semua, padahal nggak ada api!”
“Pak, jalan setapak di hutan Secang tiba-tiba hitam, kayak habis dibakar, tapi nggak ada bekas bara sama sekali.”
Petugas hanya saling pandang.
Tidak ada yang paham.
Tidak ada yang mau patroli ke sana… apalagi sendirian.
—
Reaksi Svarnavarna (dalam kepala Arno)
“Haha, bocah. Ini baru pemanasan. Kota kecilmu terlalu sempit buat kaki-kaki neraka seperti dia. Lihat… sampai Magelang pun ikut panas dingin.”
“Tapi tenang… Banaspati bukan mencarimu. Belum. Dia cuma sedang… jalan-jalan.”
Arno hanya menatap peta Jogja dan sekitarnya di dinding sebuah warung.
Titik-titik gelap mulai tersebar.
Dan ia sadar:
Dunia ini perlahan membentuk medan perang yang lebih besar dari yang ia bayangkan.
—
Bab: Doa yang Tersisa di Udara Malam
Di sebuah pendopo kecil di lereng Menoreh, asap kemenyan menari perlahan di udara.
Beberapa warga berkumpul, wajah-wajah mereka letih namun tegar.
Mereka bukan orang-orang yang mudah percaya mitos, tapi apa yang mereka lihat malam itu bukan sekadar cerita warung kopi.
Seorang lelaki tua, Mbah Wiryo, duduk bersila. Ia dikenal sebagai orang pintar di daerahnya. Dahulu membantu mencari orang hilang di hutan, kini diminta menenangkan ketakutan yang jauh lebih besar.
“Mbah… ini bukan jin biasa, ya?”
“Semalam tanahnya gosong, pohonnya utuh. Ini apaan, Mbah?”
Mbah Wiryo menarik napas panjang, lalu berkata pelan.
“Yang kalian lihat… bukan sekadar makhluk dari alam halus. Ini… amarah yang sudah lama dikubur di tanah Jawa.”
“Namanya mungkin berbeda-beda… Ada yang bilang Banaspati, ada yang bilang Bayangan Api, tapi satu yang pasti-dia tidak mencari korban. Dia mencari peringatan.”
Orang-orang saling berpandangan. Tak tahu mana yang lebih menakutkan: makhluknya atau arti kehadirannya.
—
Rencana yang Goyah
Seorang pemuda berdiri gelisah.
“Kalau cuma peringatan, kenapa ayam-ayam saya mati hangus? Kenapa sawah Pak Karjo kering semalam padahal hujan siang harinya?”
Mbah Wiryo menghela napas.
“Karena manusia keras kepala. Kalau tidak disentuh luka, mana mau berhenti berlari.”
Akhirnya, warga sepakat:
Malam berikutnya, mereka akan mengadakan ritual kecil di punden desa, menyalakan obor, membacakan doa-doa lama yang sudah jarang terdengar.
Bukan untuk mengusir Banaspati.
Tapi untuk mengingatkan diri sendiri, bahwa mereka masih bagian dari bumi ini.
—
Dari Jauh
Di tempat lain, mungkin di sudut Jogja yang lebih sepi, Svarnavarna tertawa pelan dalam kepala Arno.
“Lihat, bocah… manusia selalu berpikir api bisa ditenangkan dengan mantra. Padahal yang marah bukan apinya… tapi yang menyalakannya.”
Arno mengepalkan tangan, menatap gelap yang makin terasa dingin.
“Jadi… siapa yang menyalakannya?”
Svarnavarna hanya tertawa, tidak memberi jawaban.
Bab: Api yang Tidak Meminta Izin
Di tengah gelapnya hutan lereng Gunung Merbabu, di mana malam lebih pekat daripada bayangan manusia, sosok itu berdiri.
Tubuhnya bukan dari daging, bukan dari tanah-hanya kumpulan nyala api yang membentuk wujud kasar manusia. Matanya seperti bara yang belum padam sejak ribuan tahun lalu. Tiap langkahnya meninggalkan jejak gosong, namun pohon-pohon di sekitarnya hanya gemetar, tak terbakar.
Banaspati tidak mengaum. Ia tidak berteriak. Ia hanya berbicara pada udara, pada waktu, pada ingatan yang tak lagi diingat manusia.
“Mereka lupa.”
“Mereka potong akar pohon, bangun rumah di atas sumur tua, dan tertawa di atas tanah yang masih menyimpan janji.”
“Aku datang bukan untuk membakar. Aku datang untuk mengingatkan.”
Di matanya, kota Jogja dan Magelang bukan sekadar titik-titik lampu di kejauhan. Ia melihat retakan-retakan kecil di bawah kota itu-retakan yang dahulu dikunci dengan ritual dan doa, tapi kini dibiarkan terbuka oleh keserakahan dan keangkuhan.
—
Masa Lalu yang Kembali
Suara gemuruh dari dalam tanah membuat hewan-hewan malam diam.
Banaspati mendongak, menatap langit yang seolah berani menantangnya.
“Aku dikurung karena amarahku membakar sawah dan rumah manusia yang lupa hormat.”
“Tapi waktu membuka kembali penjaraku… karena manusia yang sama kini membakar dirinya sendiri.”
Tangannya terangkat. Sebuah pusaran api kecil terbentuk, mengambang pelan di telapak tangannya. Tapi api itu tidak liar. Api itu… terkendali.
“Kali ini, aku tidak akan menjadi liar. Aku akan menjadi pengingat.”
“Satu kota. Satu malam. Lihat apakah mereka masih ingat cara berdoa di tengah api.”
—
Langkah Pertama
Banaspati bergerak perlahan, menuju barat-menuju tepian kota, ke ladang-ladang gersang yang dahulu subur. Ia tidak perlu tergesa. Ia tahu manusia akan lebih takut pada apa yang mereka dengar daripada apa yang mereka lihat.
Dan ketika langkahnya mencapai batas dusun paling pinggir, ia berhenti.
Angin membawa bisikan namanya ke rumah-rumah tua:
Banaspati. Bayangan Api. Makhluk dari batas zaman.
Bab: Api yang Tak Punya Kabar
Malam gelap di lereng utara Jogja hingga perbatasan Magelang terasa lebih sunyi dari biasanya. Ladang-ladang tembakau yang belum panen terhampar luas, sunyi kecuali suara jangkrik dan angin lembab yang berembus pelan.
Di tengah lapangan kosong bekas lumbung, berdiri sosok tinggi berbalut bayangan. Bukan bayangan biasa, karena dari sela-selanya menyala pijaran merah seperti bara yang tak pernah padam. Sosok itu-Banaspati-diam, namun aura panasnya perlahan membuat rumput liar di sekitarnya mulai mengering.
Dari arah jalan setapak, terdengar suara anak-anak muda kampung. Mereka habis nongkrong di pos ronda, membawa lampu petromaks tua dan radio kaset besar yang memutar lagu rock dari pita kaset lusuh. Suara God Bless samar terdengar serak:
“Kota… penuh dengan dusta…”
Mereka tertawa, saling ledek, belum sadar bahaya apa yang mengintai.
Lalu Banaspati mengangkat satu tangannya. Api kecil, sebesar biji kopi, muncul melayang dari ujung jarinya. Tidak panas, tidak gaduh, tapi aneh-karena api itu tak butuh sumbu.
Salah satu pemuda berseru, setengah bercanda:
“Wah, efek sulap nih… Siapa yang bawa korek api terbang?”
Tapi tawa mereka mati mendadak. Api kecil itu membesar, membentuk lingkaran menyala di udara.
Dalam sekejap, lingkaran itu mekar seperti bunga api yang membungkus mereka dalam cahaya kemerahan.
Udara mendadak panas seperti tungku pembakaran batu bata.
Petromaks mereka meledak kecil, kaset mendecit lalu terhenti, dan suara jangkrik pun lenyap.
Salah satu dari mereka mulai berteriak panik:
“Ampun… Ini apa?! Bukan api biasa ini…!”
Banaspati tidak bergerak.
Suara beratnya, seperti debu yang lupa dibersihkan berabad-abad, bergema pelan:
“Aku tidak membakar tubuhmu. Aku membakar ketakutanmu.”
“Berani? Maka bertahanlah. Takut? Maka lenyaplah.”
Dan benar saja. Tak satu pun dari mereka terbakar jasadnya. Tapi tubuh mereka ambruk perlahan, seperti habis disedot tenaganya. Mereka pingsan, bukan karena luka bakar, tapi karena ketakutan yang terlanjur membakar hati mereka sendiri.
Yang tersisa hanyalah lingkaran gosong di tanah. Hitam. Sempurna.
Seolah ada cap dari dunia lain.
—
Kekuatan Banaspati di Era 1983:
Ia tidak butuh listrik, senjata, atau teknologi. Hanya api yang keluar dari kehendaknya.
Api itu membakar batin manusia, bukan hanya fisiknya.
Ia bisa mengubah hawa biasa menjadi panas membakar, tanpa meninggalkan asap.
Kekuatannya muncul seperti legenda yang dulu hanya ditakuti di dongeng-dongeng rakyat Jawa.
—
Banaspati menatap langit barat, di mana lampu kota Jogja masih samar terlihat.
“Wahai manusia kota… Kalian hidup terlalu nyaman. Malam ini hanya permulaan.
Besok-besok… kalian baru akan tahu apa rasanya dijaga oleh ketakutan sendiri.”
Ia melangkah perlahan, dan setiap tanah yang diinjaknya meninggalkan jejak hangus, seperti bara api yang tak sempat padam.
—
Bab: Kabar yang Mengalir Lewat Gelas Kopi dan Radio Tua
Pagi itu, udara masih dingin menusuk. Warung kopi Pak Sarmin di pinggir jalan utama Magelang-Jogja belum ramai. Hanya ada dua tukang becak dan satu sopir colt T120 yang tengah menyeruput kopi hitam panas, sambil mendengarkan radio transistor National tua yang suaranya sember.
Dari radio itu, samar terdengar suara penyiar lokal yang agak tergesa-gesa:
“Berita pagi ini… sejumlah warga di Dusun Kaliputih ditemukan pingsan tanpa sebab jelas. Tidak ada luka bakar, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Namun di sekitar lokasi ditemukan jejak melingkar seperti tanah terbakar…”
Salah satu tukang becak mendengus pelan, menaruh gelasnya.
“Ah… palingan anak-anak kampung main-main bakar ban bekas lagi tuh… Udah biasa.”
Tapi Pak Sarmin, yang sudah lebih dari 30 tahun buka warung, menggeleng pelan.
“Ndak, Le… Ini lain. Tadi pagi Pak Dukuh cerita, waktu dia lewat sana, bau hangusnya bukan kayak ban kebakar. Ini… kayak bau dupa terbakar campur tanah basah. Kayak… ada yang nyulut api dari dalam bumi.”
Sopir colt menyahut sambil menyalakan rokok kretek:
“Ngomong-ngomong, kemarin malam aku nganter barang ke Muntilan… Di jembatan lama itu, aku lihat ada cahaya merah di tengah sawah. Kayak lampu petromaks, tapi besar banget, bulat. Eh… pas aku berhenti, ilang. Tiba-tiba hawa panas banget, kayak deket tungku.”
Tukang becak mulai gelisah, setengah bercanda:
“Jangan-jangan… itu Banaspati, Pak? Kayak yang diceritain orang-orang tua zaman dulu. Api hidup, suka gentayangan malam-malam nyari orang salah jalan!”
Pak Sarmin hanya tersenyum tipis, tapi matanya tak ikut tersenyum.
“Banaspati atau bukan, yang jelas… hati-hati kalau pulang malam. Soalnya kalau sudah urusan api, kita ini cuma arang menunggu waktunya.”
Radio kembali berderak, kini diputarkan lagu lawas dari Deddy Dores yang mengisi keheningan dengan melankoli tipis. Tapi bisik-bisik itu sudah menyebar.
—
Sore Harinya:
Di pasar Beringharjo, di emperan stasiun Tugu, hingga ke angkringan dekat Malioboro, kabar itu terus beredar:
“Ada api gentayangan di lereng. Katanya nyari orang yang hatinya kotor…”
“Kalau lewat sana malam-malam, jangan sombong. Salam dulu sama angin.”
“Radio bilang cuma pingsan, tapi Pak RT bilang mereka itu… kayak dicabut nyawanya sebentar.”
—
Dan seperti biasa, kabar burung berjalan lebih cepat daripada kendaraan dinas.
Sementara itu, Banaspati sendiri masih melangkah di pinggir ladang sunyi, membiarkan ketakutan manusia bekerja lebih efektif daripada apinya.
—
Bab: Saat Yang Bijak Mulai Bicara
Di pendapa Balai Desa Kaliputih, malam itu lampu petromax bergoyang pelan ditiup angin lembab. Suara jangkrik dan kodok bersahut-sahutan, mengisi sela-sela keheningan para lelaki yang duduk melingkar: Kepala Desa Pak Wiryo, Babinsa Serka Karsono, Pak Lurah Budiarto dari dusun sebelah, serta satu orang tua berambut putih yang duduk agak terpisah: Mbah Suro, dukun sepuh yang sudah jarang keluar rumah.
Pak Wiryo membuka rapat dengan suara berat, tapi pelan.
“Saya ndak mau menakut-nakuti warga. Tapi kalau kejadian aneh sudah tiga malam berturut-turut… ini bukan kebetulan.”
Serka Karsono mengangguk, wajahnya kaku. Ia menaruh rokok kretek yang belum sempat dinyalakan.
“Tadi pagi saya lapor ke Koramil. Mereka bilang tunggu perkembangan. Tapi kalau betul ada api gentayangan… saya kira peluru juga percuma.”
Pak Lurah Budiarto menghela napas panjang.
“Orang-orang di pasar sudah mulai takut. Tukang sayur nggak berani lewat jalan kebun, takut lihat api itu. Kalau begini terus, kita bisa lumpuh pelan-pelan. Orang takut keluar rumah.”
Mbah Suro akhirnya angkat suara, lirih tapi dalam, suaranya seperti embun jatuh di atas genting tua.
“Ini bukan api biasa. Bukan maling, bukan perampok. Ini… mungkin Banaspati.”
Semua menoleh.
“Banaspati itu bukan sekadar roh penasaran. Ia… kadang muncul karena ada ketidakseimbangan. Ada dendam yang belum selesai, ada tanah yang terusik, atau… ada manusia yang terlalu serakah mengusik batas.”
Pak Wiryo menatap meja kayu di depannya, berpikir keras.
“Jadi apa yang harus kita lakukan, Mbah?”
Mbah Suro menatap jauh ke luar jendela.
“Untuk sekarang? Jangan cari dia. Jangan ganggu. Biar api itu tenang dulu. Tapi… panggil orang-orang yang mengerti batas dunia. Ki Prayitno di Muntilan, atau Romo Seto di Magelang. Mereka tahu cara bicara dengan api tanpa terbakar.”
Serka Karsono menambahkan:
“Tapi kita tetap harus jaga ronda. Jangan sampai warga panik. Kalau perlu, bilang saja ini hanya satwa liar atau kabar bohong.”
Pak Wiryo setuju, meski hatinya tahu… malam-malam ke depan tak akan semudah menyalakan petromax.
—
Di Tempat Lain
Di Jogja, kabar tentang Banaspati mulai terdengar samar di ruang redaksi koran lokal dan radio. Beberapa reporter mulai tertarik menyelidiki, tapi masih ragu apakah ini berita serius atau sekadar cerita kampung yang biasa muncul menjelang musim kemarau panjang.
Sementara itu, Banaspati masih berkeliaran di batas hutan dan ladang, seolah menunggu sesuatu.
—
Bab: Api yang Tak Bisa Dipadamkan dengan Air
Pendapa Kayu di Muntilan, suatu malam yang sunyi. Bau dupa samar memenuhi udara. Di bawah cahaya lampu teplok, berkumpul empat orang sepuh yang jarang sekali duduk bersama.
Ki Prayitno, pendekar tua yang kini hidup sebagai petani di lereng Gunung Merbabu.
Romo Seto, pastor Katolik yang dikenal mampu membaca pertanda alam.
Mbah Suro, dukun tua dari Kaliputih.
Pak Parman, guru silat dan pelukis batik yang peka pada perubahan energi alam.
Suasana hening lama, sampai akhirnya Ki Prayitno berkata pelan:
“Kalau Banaspati sudah menampakkan diri, artinya ada batas yang dilanggar. Entah batas antara dunia manusia dan roh, atau batas keserakahan manusia sendiri.”
Romo Seto mengangguk, menggenggam salib kecil di tangannya.
“Saya mendengar suara api di angin malam. Bukan suara biasa. Ini… marah. Tapi siapa yang membangunkannya?”
Pak Parman, dengan suara berat:
“Siapapun yang membangunkan Banaspati, mungkin tidak sadar sedang bermain-main dengan neraka.”
Mbah Suro menatap mereka satu per satu.
“Kita harus temukan titiknya. Titik pertama Banaspati muncul. Kalau itu bisa kita tutup, mungkin apinya padam.”
Ki Prayitno menarik napas dalam.
“Kabar burung bilang, titiknya bukan hanya satu. Ada tiga titik cahaya di sekitar Jogja dan Magelang. Seperti segitiga api.”
Semua terdiam. Malam terasa lebih dingin dari biasanya.
—
Sementara Itu: Taman Sore Jogja
Di sisi lain kota, Arno duduk di bangku taman, memandangi langit yang mulai menguning. Pikiran masih berkecamuk. Tentang dirinya. Tentang suara di kepalanya. Tentang malam-malam yang mulai dipenuhi bayangan.
Suara langkah pelan mendekat. Tak asing.
Aini, mengenakan blus biru pudar dan celana kain, rambutnya dikuncir sederhana.
“Masih suka melamun kayak dulu ya, No?”
Arno tersenyum kecil, menahan getir.
“Masih. Cuma sekarang yang saya lamunin bukan PR sekolah, tapi… hal yang lebih absurd.”
Aini duduk di sebelahnya, menjaga jarak seperti biasa.
“Kamu dengar kabar Banaspati?”
Arno mengangguk pelan. Dalam kepalanya, Svarnavarna berbisik sarkastis:
“Oh, bagus. Bahkan wartawan pun ikut membicarakan dongeng api yang bosan tidur.”
Aini menatap tajam.
“Aku tahu kamu terlibat sesuatu, Arno. Mungkin bukan kamu penyebabnya, tapi aku yakin… kamu dekat dengan jawabannya.”
Arno menunduk, senyum pahit.
“Kamu selalu terlalu cerdas, Aini. Itu masalahnya.”
Aini tertawa kecil, lalu berkata pelan:
“Besok aku ikut pertemuan di Muntilan. Katanya beberapa orang pintar mau cari cara menenangkan Banaspati. Mungkin kamu harus ikut. Atau paling tidak, jangan cuma duduk di sini nunggu dunia terbakar.”
Svarnavarna berbisik lagi:
“Lucu ya, bocah. Bahkan manusia biasa tahu kamu nggak bisa diem terlalu lama.”
Arno mendesah. Dunia memang mulai terbakar. Pertanyaannya: dia akan ikut memadamkan api itu… atau malah terbakar bersamanya.
—
Bab: Di Antara Api dan Kata-Kata
Pagi itu, udara Muntilan masih dingin basah embun. Aini tiba di pendapa tua yang tersembunyi di balik kebun kopi dan pagar bambu. Tempat itu tampak biasa saja dari luar-hanya rumah joglo setengah rapuh. Tapi begitu melangkah masuk, ia merasakan hawa berat seperti udara berhenti bernafas.
Di dalam, sudah berkumpul wajah-wajah tua dan muda. Ada yang mengenakan sarung dan surjan, ada yang berjas lusuh, ada pula yang berpakaian seperti guru sekolah biasa. Tapi mata mereka tajam, bicara mereka pelan namun penuh makna.
Ki Prayitno menyambut Aini dengan anggukan lembut.
“Selamat datang, Nona Aini. Wartawan, ya? Jarang ada yang berani datang ke pertemuan seperti ini tanpa undangan.”
Aini tersenyum sopan, menaruh buku catatannya di pangkuan.
“Saya hanya ingin mendengar, Ki. Tidak berniat mengusik.”
Romo Seto menoleh, suara lembut tapi berisi:
“Kadang, yang mendengar lebih berbahaya dari yang bicara. Tapi hari ini… biarlah kau jadi saksi.”
Di atas meja kayu, terbuka sebuah peta tua Jawa Tengah. Ada tiga titik merah menyala-Yogyakarta, Magelang, dan daerah perbukitan Menoreh. Mereka menyebutnya “Segitiga Api”.
Mbah Suro menunjuk salah satu titik dengan tongkat kayunya.
“Di titik inilah Banaspati pertama kali muncul minggu lalu. Api yang tak bisa dipadamkan, bayangan yang membakar tanah tanpa meninggalkan abu.”
Pak Parman menambahkan:
“Dan tadi malam, seorang pendeta di Magelang melihat cahaya merah menyala di kuburan tua. Suara tertawa… seperti bara yang bernafas.”
Aini mencatat cepat. Tapi di sela-sela menulis, ia merasa seperti diperhatikan. Entah siapa yang menatapnya. Atau mungkin hanya perasaan.
—
Tiba-Tiba…
Pintu pendapa terbuka keras. Seorang pemuda berlari tergopoh-gopoh, napasnya masih memburu.
“Ki! Mbah! Ada yang aneh di lereng barat Merapi! Ladang jagung terbakar… tapi tidak ada api. Hanya cahaya merah membakar batang-batangnya, lalu hilang seperti asap disedot langit!”
Semua terdiam. Lalu Ki Prayitno berdiri pelan.
“Kita tak bisa hanya duduk dan bicara. Harus ada yang turun langsung ke sana.”
Romo Seto menoleh ke Aini.
“Kau masih mau ikut, Nona?”
Aini menatap peta, menutup bukunya perlahan.
“Saya datang bukan untuk pulang sebelum tahu jawabannya.”
—
Perjalanan Menuju Lereng Merapi
Aini ikut dalam rombongan kecil itu. Mereka naik truk tua, melintasi jalan tanah, melewati kebun tembakau dan jurang-jurang sunyi. Angin Merapi terasa aneh-hangat seperti embusan napas makhluk yang belum selesai tidur.
Di tengah perjalanan, Aini tak sengaja memandang ke belakang truk. Di kejauhan, samar-samar… seolah-olah ada bayangan besar bergerak di balik kabut gunung. Tak jelas wujudnya. Tapi warnanya-merah membara.
Svarnavarna yang ikut memperhatikan dari dalam batin Arno, berkata pelan dari jauh:
“Ah, bocah-bocah ini berani juga. Tapi seberani apapun, kalau Banaspati sudah bangun sepenuhnya… mereka cuma kayu bakar.”
—
Sampai di Lereng: Api yang Tak Terlihat
Mereka tiba di ladang yang sudah hangus. Tapi anehnya, tidak ada bau asap. Hanya tanah hitam, panas, dan pohon-pohon yang layu tanpa terbakar.
Pak Parman berlutut, menyentuh tanah, lalu mendesis:
“Ini bukan api biasa. Ini api yang lapar. Mencari sesuatu… atau seseorang.”
Ki Prayitno berdiri tegak, menatap gunung di kejauhan.
“Banaspati belum sepenuhnya terbangun. Tapi kalau kita tak cepat… besok mungkin yang terbakar bukan ladang, tapi kota.”
Aini menggenggam buku catatannya lebih erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa cerita yang sedang ia tulis… mungkin tak akan sempat selesai.
—
Bab: Hilang di Tengah Senyap
Senja makin tenggelam di balik punggung Merapi. Ladang hangus itu membisu, seolah menahan napas. Pak Parman dan Ki Prayitno masih berdiri di tepi tanah hitam, saling bertukar pandang dengan cemas.
Aini, yang sedari tadi sibuk menulis, tak sadar kakinya membawa ia menjauh, mengikuti arah angin yang seolah memanggil. Lembar-lembar catatannya terbang, dan ia tanpa sadar mengejar hingga melewati batas ladang, masuk ke jalur setapak yang dilingkupi semak-semak rimbun dan batuan berlumut.
Pak Parman (memanggil, mulai khawatir):
“Mbak Aini! Jangan jauh-jauh! Jalurnya berbahaya!”
Tapi angin tiba-tiba berdesir kencang, menelan suaranya. Seperti ada sesuatu yang tak ingin panggilan itu sampai.
—
Firasat yang Tak Diam
Langit malam di Jogja terasa berat. Angin hanya berhembus pelan, seperti tak berani menyentuh bayang-bayang yang mengendap di jalanan sempit. Arno berdiri di bawah lampu jalan yang berkerlap-kerlip setengah mati, pikirannya melayang-layang.
Svarnavarna bersuara tiba-tiba, nadanya setengah mengejek, setengah menegur.
Svarnavarna:
“Kau pikir duduk termenung bisa menolong siapa pun? Atau kau menunggu Tuhan kirimkan telegram yang bilang ‘Aini dalam bahaya’? Bocah, instingmu sudah bau tanah, bangkitlah.”
Arno menghela napas pelan, menatap jalan kosong di depannya.
Svarnavarna (mengejek):
“Ah, begini ya rupanya pahlawan yang terlambat? Wanita itu mungkin sudah separuh cerita hilang, dan kau masih debat sama bayangan sendiri.”
Diam-diam, dada Arno mulai sesak. Firasatnya sejak sore terasa tak enak, seperti ada tali tak kasat mata yang menariknya ke utara, ke arah gunung. Dan nama Aini berputar di kepalanya, seperti bisikan yang menolak diam.
Arno (pelan):
“Ayo kita bergerak kesana.. Karena jika kita terlambat satu menit saja, mungkin aku tak akan maafkan diri sendiri.”
Svarnavarna tertawa pendek, dingin.
Svarnavarna:
“Kau tak perlu maafkan dirimu, bocah. Dunia juga belum tentu peduli. Tapi setidaknya… kau masih bisa berlari.”
—
Keberangkatan Tanpa Peta
Tanpa banyak pertimbangan, Arno menuruni jalan sempit menuju terminal kecil. Ia tak sempat memikirkan ongkos atau rute. Ia hanya tahu: arah gunung, arah lereng, arah tanah yang terbakar diam-diam.
Bus tua menuju arah Magelang baru saja berangkat, meninggalkan debu di belakang. Arno mengejarnya dengan setengah berlari.
Svarnavarna lagi-lagi menyelutuk:
Svarnavarna:
“Gerakanmu cepat tapi instingmu lambat. Walau tetap saja… seperti kucing kampung ngejar truk pasir.”
Arno naik ke bus, duduk di bangku belakang yang hampir copot sandarannya. Sepanjang jalan, ia hanya menatap keluar, membiarkan semua tanda-tanda samar berputar di benaknya: laporan ladang hangus, kabar burung tentang makhluk bayangan di lereng, dan yang paling menusuk… keheningan dari Aini.
—
Di Antara Kabut Lereng
Perjalanan malam itu menembus kabut dan hening. Setelah turun di perhentian terakhir, Arno masih harus berjalan kaki melewati jalanan tanah yang licin, menyeberangi pematang, dan melewati pohon-pohon yang merunduk ke arah jalan, seolah menutupinya dari mata dunia.
Di kejauhan, samar, ia mulai merasakan hawa panas. Tapi anehnya, tak ada bau asap. Hanya udara yang berat, dan keheningan yang terlalu dalam untuk sebuah hutan malam.
Svarnavarna bersuara lagi, kali ini nadanya lebih datar.
> Svarnavarna:
“Selamat datang di tengah api yang tak butuh kayu. Kau cari perempuan itu, atau cari mati, bocah?”
Dalam Gelap yang Mencekam
Aini perlahan sadar, kepalanya masih berat, tubuhnya serasa terkurung udara panas yang pekat, seperti dinding tak terlihat yang membakar perlahan tanpa api.
Di hadapannya berdiri sosok itu-Banaspati. Tingginya tak wajar, hitam berkilat bagai bara yang belum padam, dengan mata menyala redup, seolah melihat lebih dari sekadar dunia manusia.
Suaranya menggetarkan udara, berat, namun tak sepenuhnya marah. Lebih seperti… suara makhluk yang tahu tujuannya tapi tak peduli pada jalan yang ia lewati.
Banaspati (suara dalam, bergema pelan):
“Kau… Gadis pemberani.. Tapi sayang kau sebentar lagi jadi abu.”
Aini berusaha bangkit, namun seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Bukan rantai, bukan tali-tapi rasa takut yang membeku dalam dada.
“To.. Tolong.. Tolong.. Siapa saja tolong aku!!” Teriaknya.
Tapi seolah tak ada seseorang pun yang mendengarnya.
Banaspati:
“Diamlah, dan dengarkan. Dunia ini akan tahu rasa hangus sebelum pagi datang. Dan kau… cukup jadi saksi dan setelah itu ikutlah terbakar.”
Ia menatap ke arah kaki gunung yang jauh di sana. Senyap, tapi ada sesuatu yang ia tunggu.
Banaspati (lebih pelan, seperti bisikan bara):
“Mereka akan datang. Entah untuk melawan… atau untuk ikut terbakar.”
Aini mengerutkan kening, mencoba merangkai arti kata-katanya lalu memberanikan diri bertanya.
Aini (pelan):
“Siapa… mereka itu?”
Banaspati hanya menoleh singkat, lalu senyumnya samar, lebih dingin daripada panas tubuhnya.
Banaspati:
“Pertanyaan yang bahkan aku tak peduli jawabannya. Aku hanya api… yang menunggu angin datang.”
Kemudian ia berdiri diam, tubuhnya perlahan seperti berbaur dengan kegelapan malam, tapi hawa panasnya tetap membakar tanah di sekelilingnya.
—
Aini hanya bisa menggenggam kuat buku catatannya-tak lagi yakin apakah kisah ini akan berakhir dengan kata “selesai.”
Kebingungan dan ketakutan menggantung. Belum ada yang tahu: apakah Banaspati berdiri di sana karena kehendaknya sendiri… atau karena sesuatu yang lebih besar telah bergerak di balik bayangan.
—
Bab: Jejak yang Membakar Senyap
Langkah Arno pelan namun mantap, membelah malam yang semakin tebal dengan hawa panas yang ganjil. Tanah di bawah kakinya hangus, tapi tidak berbau asap. Hening seperti ladang yang pernah terbakar namun tidak pernah benar-benar padam.
Svarnavarna berbisik di kepalanya, nadanya tetap tajam:
Svarnavarna:
“Bocah, kau sadar kan… kau sedang mendekat ke kompor yang tak pernah padam sejak zaman orang lupa nama mereka sendiri?”
Arno tak menanggapi. Matanya menyapu tanah, menangkap jejak-jejak besar yang dalam, seolah makhluk itu tak sekadar berjalan, tapi menancapkan keberadaannya.
Ia berjongkok, menyentuh permukaan hangus yang masih hangat. Suhu panas itu seperti peringatan halus yang ditinggalkan oleh sesuatu yang tidak terburu-buru, tapi pasti.
Perjalanannya berlanjut perlahan ke lereng yang lebih tinggi. Suasana terasa lebih berat, seperti seluruh alam menahan napas menunggu sesuatu.
Dan di sana, di balik kelokan tanah, Arno akhirnya melihatnya.
Sosok tinggi besar itu berdiri tegak, tubuhnya diselimuti api yang tenang, tidak membara liar, tapi menyala stabil seperti bara dalam perapian tua. Banaspati. Matanya redup, dalam, menatap ke kejauhan seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh siapa pun.
Arno berhenti. Jarak mereka hanya beberapa puluh langkah.
Svarnavarna bergumam pelan, setengah mengejek:
Svarnavarna:
“Nah, akhirnya. Lilin raksasa yang kau cari-cari. Sayangnya, kau lupa bawa korek cadangan.”
Banaspati, tanpa menoleh, berbicara dengan suara berat yang menggema di lereng sunyi itu:
Banaspati:
“Langkahmu… asing, tapi tak asing.”
“Kau datang membawa sesuatu yang tak kuminta, tapi sudah kucium jauh sebelum kau sampai.”
Arno menahan diri untuk tidak bicara sembarangan. Suara itu bukan sekadar gertakan kosong. Ada beban waktu dan kekuatan di baliknya.
Banaspati perlahan berbalik, memperlihatkan tubuhnya yang tersusun dari lapisan-lapisan hitam membara, seperti batu bara hidup. Api melingkari telapak kakinya, tapi tak pernah membakar tanah di sekelilingnya.
Banaspati:
“Aku dipanggil oleh suara yang belum kukenal… tapi api di dadaku berkata itu adalah panggilanku.”
“Dan ketika api sudah bangkit, ia tak lagi bertanya siapa yang menyalakan.”
Svarnavarna terkekeh sinis:
Svarnavarna:
“Bocah, lihat baik-baik. Bahkan makhluk sebesar itu pun tidak sadar dia cuma pion di papan catur orang lain.”
Arno memperhatikan lebih seksama. Ada sesuatu yang janggal-Banaspati tampak seolah-olah yakin akan tujuannya, tapi sorot matanya kosong. Seperti kekuatan yang hidup tanpa kesadaran penuh akan siapa yang mengendalikannya.
Banaspati melangkah maju satu langkah, dan tanah bergetar lembut. Tapi ia tidak menyerang. Ia hanya menatap langit malam yang pekat.
Banaspati (gumam, nyaris seperti bicara ke dirinya sendiri):
“Api menunggu arah. Tapi jika tak ada arah, maka semua akan terbakar tanpa tujuan.”
Hening kembali. Hanya suara angin lembut yang melintas di antara dua makhluk yang berasal dari dua dunia berbeda.
Arno tetap diam, memilih mengamati, bukan menyerang. Ia tahu, pertempuran bodoh hanya akan membuatnya hangus lebih cepat dari yang ia bayangkan.
—
Dari Balik Kegelapan: Senyum yang Tak Terlihat
Jauh di atas sana, tersembunyi di balik semak dan bayang-bayang lereng, seorang sosok diam memperhatikan mereka.
Ia tidak bergerak, hanya tersenyum tipis, samar, seperti seseorang yang puas melihat bidak-bidaknya mulai bergerak sesuai rencana.
Tangan kirinya menggenggam sesuatu yang kecil, memancarkan cahaya redup. Cahaya itu bergetar pelan, seolah terhubung dengan kekuatan Banaspati tanpa disadari makhluk itu sendiri.
Ia berbalik perlahan, menghilang ke dalam gelap yang lebih dalam dari malam itu sendiri, meninggalkan Banaspati dan Arno berdiri di tengah lereng, terpisah oleh api dan misteri yang belum terjawab.




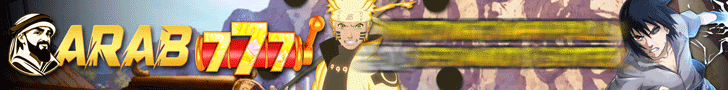
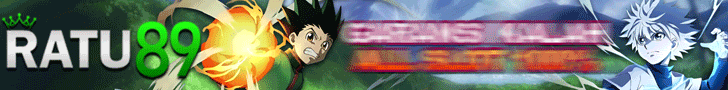



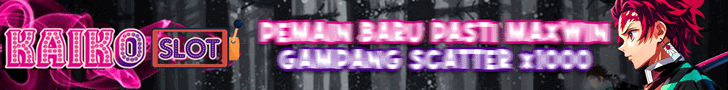

Comment