Jika Kalian menemukan Gambar Rusak / Terpotong / Tidak Terload Silahkan Lapor ke [chatango] atau [disini]

1.Semua orang punya kesempatan
Yogyakarta, April 1983 – Gang Sayidan, jam 02.14 dini hari
Udara malam lembab dan berbau besi.
Lampu jalan mati. Hanya cahaya dari gardu pos ronda yang redup, menyoroti lorong sempit di belakang Pasar Sentul.
Empat pemuda bersenjata celurit dan rantai besi berdiri melingkari satu lelaki di ujung gang.
Tubuh korban sudah babak belur. Wajahnya berdarah. Nafasnya tinggal satu-satu.
“Hajar sekalian, Lek. Udah teriak-teriak dia dari tadi,”
ujar salah satu, sembari meludah ke tanah.
“Udah, matiin aja. Siapa juga yang peduli? Di sini semua orang pura-pura tidur,”
kata yang lain sambil memutar rantainya.
Dan saat mereka bersiap mengayun senjata-
suara sesuatu terdengar dari ujung gang.
Bukan langkah. Bukan suara motor.
Tapi seperti… gesekan bayangan di tembok.
Seorang lelaki muncul dari gelap.
Jaket coklat lusuh. Kaos abu-abu dengan gambar dunia.
Tas kecil menggantung di tangan kirinya. Wajahnya tenang, rambutnya sedikit berantakan, dan tatapannya seperti tak asing dengan kekerasan.
“Udah selesai?” tanyanya pelan.
Empat pemuda itu terdiam sebentar, lalu tertawa kasar.
“Weh, siapa ini? Mau sok jagoan?”
“Mundur, orang gila. Masih banyak lorong lain buat mati!”
Tapi laki-laki itu-tidak bergerak.
Ia hanya menoleh sedikit ke dinding di sampingnya,
tempat bayangannya sendiri mulai menjalar ke atas seperti asap.
Dalam sepersekian detik,
sesuatu melesat dari bayangan itu-membentuk seperti cambuk pekat,
menghantam dada salah satu pemuda dan melemparkannya ke tumpukan gerobak besi di ujung gang.
“APA ITU-?!”
Yang lain bereaksi. Celurit melayang. Rantai diayun.
Tapi pria itu sudah hilang dari posisi berdiri.
Ia seperti lenyap-muncul dari sisi lain gang, di belakang mereka.
Satu hentakan lutut ke perut, satu sapuan bayangan dari belakang kepala-
dan dua dari mereka ambruk sebelum sempat berteriak.
Pemuda terakhir mencoba lari,
tapi bayangan panjang dari kaki pria itu meluncur seperti lidah ular,
melilit pergelangan kakinya dan menarik keras.
Tubuhnya jatuh menghantam batu, pingsan seketika.
Sunyi.
Hanya terdengar napas korban yang tergeletak gemetar.
Pria itu menunduk, memeriksa luka si korban.
Ia masih hidup. Tapi memar di seluruh wajahnya menunjukkan ini bukan pemukulan biasa.
Mereka memang ingin membunuh.
Dia berdiri.
Tak meninggalkan jejak.
Tak membawa korban.
Hanya menoleh ke dinding belakang gang,
mengambil sepotong kapur dari kantongnya,
dan menulis pelan:
YAMA
Lalu ia berjalan pergi.
Bayangannya mengikuti-tidak seperti milik manusia biasa.
Bayangan nya hidup, dan dunia mulai menyadarinya.
Malam Ketiga Puluh – Kota Tanpa Jam
Beberapa orang bilang waktu bisa diprediksi dari suara;
lonceng pos ronda, deru trembesi, atau siaran RRI dari radio tua yang tak pernah pindah frekuensi.
Tapi di beberapa sudut kota,
malam seperti menahan nafas.
Di ujung belakang jalan Gedongkuning,
sebuah kios rokok hangus terbakar dalam semalam.
Tak ada yang tahu penyebabnya. Tak ada yang mendengar suara ledakan.
Tapi yang aneh:
mesin ketik tua dari dalam kios ditemukan utuh… dengan satu kalimat diketik rapi di atas kertas baru:
“Bayang bukan hanya milik siang yang malas melihat.”
Tak ada tanda tangan.
Tapi satu coretan putih menyilang pintu kios:
YAMA.
—
Lorong Mataram, 03.11
Seorang wanita muda berlari sambil menggendong anak.
Tangisnya bukan panik, tapi sunyi dan sangat tahu apa yang dikejarnya: selamat.
Tiga pria mengikuti di belakang. Salah satunya membawa tongkat kayu. Mereka berseru-tapi seperti hanya didengar oleh tembok dan genangan air.
Wanita itu belok ke gang sempit, tak tahu bahwa gang itu buntu.
Ia memeluk anaknya erat-erat, menutup kepala si kecil, dan memejam.
Tapi suara langkah pengejarnya berhenti.
Tidak karena kasihan.
Tapi karena sesuatu telah berdiri di ujung gang.
Lelaki itu seperti muncul dari tiada.
Tak memakai penutup wajah, tapi tak ada satu pun yang bisa mengingat wajahnya.
Yang terlihat hanya sorot mata yang terlalu tenang untuk malam sekeras ini.
Dan bayangannya… terlalu panjang.
Terlalu bebas.
Terlalu hidup.
—
Pria pertama berusaha mendekat.
“Pergi. Urusan bukan sama kamu.”
Lelaki itu tak menjawab.
Ia hanya melangkah setengah langkah ke depan.
Bayangannya seperti menyusup ke dinding, lalu keluar dari sisi tembok lain, seolah tembok itu hanya tirai.
Suara besi retak terdengar.
Bukan dari senjata.
Tapi dari dalam bayangan yang mengeras dan memukul seperti palu ke dada pria pertama.
Yang dua lainnya mundur.
Tapi terlambat.
Bayangan dari langit-langit turun cepat seperti tali tambang, menyambar kaki dan tengkuk mereka, lalu menghentakkan tubuh mereka bersamaan ke tanah.
Tak ada darah.
Tapi suara leher yang patah pelan mengalahkan keheningan.
Wanita itu masih memeluk anaknya.
Matanya terbuka-tapi tubuhnya gemetar. Ia tak tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Ia ingin berterima kasih, tapi suara tak keluar.
Lelaki itu menatapnya sebentar.
Lalu mengangkat tangan. Bukan untuk memberi aba-aba.
Tapi untuk menyentuh dinding di belakangnya-dan masuk ke dalam bayangannya sendiri.
Ia menghilang.
Seolah memang tak pernah ada.
—
Pagi Harinya
Di koran harian, muncul satu kolom pendek di pojok bawah halaman tiga:
Tiga Penyerang Ditemukan Tak Sadar di Lorong Mataram.
Salah Satu Korban Mengaku Diselamatkan Oleh “Bayang”.
Tak ada saksi lain. Tak ada bukti yang bisa dipegang.
Hanya tanda gores di tanah yang anehnya tidak bisa dihapus air.
Warga sekitar mulai takut keluar malam.
Tapi mereka tak menyebut rasa takut itu seperti biasanya.
Karena entah kenapa…
rasa takut yang satu ini menenangkan.
Jogja, Mei 1983 – Malam Seperti Biasa
Tak semua tempat di kota ini diam saat malam turun.
Di luar jam kantor, ada kehidupan lain-yang justru bernapas ketika dering telepon dimatikan, mesin tik ditutup, dan gorden rumah-rumah besar mulai ditarik rapat.
Di Pasar Beringharjo, beberapa kios masih terbuka diam-diam meski papan bertuliskan “Tutup” sudah digantung.
Di balik barisan kain batik dan sandal kulit, tersembunyi sebuah ruangan kecil tempat kartu dimainkan, minuman keras rumahan dituang dalam botol bekas kecap, dan suara tawa para penjudi mengalahkan dengungan nyamuk.
Tapi malam itu, salah satu dari mereka mendengar suara pelan dari langit-langit.
Bukan suara langkah kaki.
Bukan pula suara benda jatuh.
Melainkan seperti kain panjang yang ditarik perlahan di atas genteng kayu tua.
Beberapa detik kemudian, lampu di ruangan itu padam dengan sendirinya.
Dan ketika menyala kembali-
satu orang sudah tergeletak tak sadarkan diri.
Yang lain diam, mulutnya terbuka namun tak bisa bersuara.
Dan meja kartu itu…
sudah retak, seperti dipukul keras dari atas,
padahal genteng tak tampak rusak.
—
Stasiun Tugu
Petugas malam sedang menyapu pelataran ketika ia melihat bayangan yang tak sesuai arah cahaya lampu.
Bayangan itu menjulur ke arah berlawanan.
Berjalan sendiri.
Tak mengikuti langkah siapa pun.
Petugas itu tak berkata apa-apa.
Ia berhenti menyapu.
Lalu melirik ke arah tempat parkir-di sana, seorang pemuda sedang mencoba membuka paksa sepeda motor milik seorang wartawan lokal.
Sebelum sempat memutar kunci palsu, tubuh pemuda itu terlempar seperti dihantam angin keras.
Dadanya menghantam kaca pos jaga.
Ia langsung tak sadarkan diri.
Tiga tukang becak yang menyaksikan dari kejauhan tak ada yang berani mendekat.
Mereka hanya saling berbisik:
“Bayangan itu muncul lagi…”
“Dia mengawasi semua lorong di kota ini…”
“Jogja sekarang tak lagi sunyi seperti dulu.”
—
Bioskop Senopati – Belakang Gedung
Di sisi lain kota, sebuah bioskop tua masih memutar film silat dari Hong Kong.
Anak-anak muda menonton sambil tertawa-tawa kecil, tapi di belakang gedung,
seorang penjaga malam menemukan sesuatu di dinding.
Bukan cat semprot. Bukan kapur. Tapi seperti bekas terbakar dari dalam bata.
Empat huruf hitam muncul, seolah tertulis oleh bara:
Y A M A
Dan tepat di bawahnya-
seorang pria mabuk ditemukan terikat di tiang listrik, dengan kabel yang dicabut dari instalasi dalam gedung.
Di dalam sakunya: daftar nama dan alamat gadis-gadis yang pernah ia ancam.
Tak ada laporan resmi.
Tak ada yang berani bicara.
Warga hanya menyimpan kesimpulan mereka sendiri:
“Ada seseorang… atau sesuatu… yang mengawasi kota ini.
Dan ia tidak tidur.
Bahkan cahaya pun tak bisa bersembunyi darinya.”
—
Tengah Kota – Jalan Malioboro
Seorang pemuda berjalan sendirian pukul dua dini hari, baru selesai bekerja di warung gudeg.
Ia mendengar suara samar di atap gedung toko, tapi menahan diri untuk tidak menoleh.
Ia tahu suara itu bukan ditujukan kepadanya.
Ia bukan target malam itu.
Namun dari ujung matanya, ia menangkap sosok-
seseorang berjalan perlahan di antara tiang-tiang toko.
Tanpa suara.
Bayangannya terlalu panjang, terlalu hidup, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak tampak.
Dan ketika ia akhirnya memberanikan diri untuk menoleh,
sosok itu sudah tidak ada.
Hanya angin yang lewat,
dan bau terbakar samar seperti sesuatu yang telah lama dikubur…
kini mulai belajar bernapas kembali.
—
Yang Tak Pernah Dilaporkan
Tidak semua aksi Yama tercatat.
Tidak semua malam berujung dengan kekerasan.
Kadang hanya sebuah tatapan.
Kadang hanya sensasi dingin di punggung, ketika seseorang hendak mencuri dompet seorang nenek di halte.
Kadang hanya coretan kecil di dekat pintu toko, cukup untuk membuat pemiliknya mengembalikan barang yang ia curi bertahun-tahun lalu.
Kadang… hanya bisikan tipis dari lorong sempit:
“Tak ada yang bisa lepas dari bayangan…
karena bayangan itu menyatu dengan dirimu sendiri.”
—
Yama belum punya wajah.
Tak punya nama.
Tapi seluruh kota mulai memahami satu hal:
Malam di Jogja tidak lagi diam.
Ia mendengar, melihat, dan membalas.
Dan wujudnya… bersembunyi di balik bayangan yang selama ini kau abaikan.
—
Panggilan yang Membelah Hari
Setelah menyelesaikan angkutan karung terakhir dari Toko Sido Dadi, ia melangkah pelan menuju warung kopi di ujung gang. Duduk di kursi kayu reyot yang dicat ulang berkali-kali, ia menanti segelas teh manis diseduh dalam poci aluminium tua, sambil memperhatikan keramaian pasar yang tak pernah benar-benar lengang.
Keringat belum sepenuhnya kering di punggungnya. Debu belum turun dari lengan bajunya. Tapi pikirannya telah melayang ke malam sebelumnya-malam yang membawanya pada batas sunyi antara dirinya dan… sesuatu yang belum berani ia beri nama.
Dan di antara hiruk-pikuk siang itu, suara itu datang, pelan tapi tegas.
“Maaf… Mas… Arno?”
Langit seperti berhenti bergerak.
Ia menoleh. Perlahan. Tanpa tergesa.
Matahari di belakang perempuan itu membuat sosoknya tampak seperti siluet yang menyala oleh kenangan.
Rambut hitamnya dikuncir rapi. Ia mengenakan blus lengan pendek berwarna biru muda, dipadukan dengan rok span cokelat tua yang jatuh tepat di bawah lutut. Di kakinya, sandal kulit bertali yang telah lusuh oleh langkah, tapi tetap bersih. Gaya yang sederhana, tapi terasa lekat dengan masa.
Wajahnya? Ceria, lembut, dengan sorot mata yang memantulkan cahaya sore seperti permukaan sungai yang tenang.
Hidungnya mancung, bibirnya tipis, dan senyumnya… ah, senyumnya seolah belum pernah belajar menyakiti siapa pun.
Ia berdiri di tepi warung, memegang buku tulis tebal yang dililit karet. Tak tinggi, tapi anggun dan proporsional-seperti lukisan yang dilukis dengan perasaan, bukan sekadar teknik.
Dan ia memanggil… Arno.
Bukan Mas Ar. Bukan Bayangan. Bukan nama samar yang ia ciptakan untuk bertahan hidup. Tapi Arno-nama yang telah lama ia kubur di balik selimut gatal dan malam-malam tanpa cahaya.
“Kamu… Arno, kan?”
Suara itu seperti tangan yang mengusap punggung di tengah hujan.
Ia tidak langsung menjawab. Hanya memandang.
Ada keterkejutan. Tapi tidak ada penolakan.
—
Perempuan yang Tidak Terhapus Waktu
“Eh… aku Aini. Masih ingat?” katanya, sambil tertawa kecil. Sederhana, namun hangat seperti senja di kampung halaman.
Aini.
Nama yang selama ini hanya hidup dalam mimpi pendek, potongan lagu dari radio tua, dan bayang senyum di bawah pohon jambu.
Teman satu bangku saat kelas tiga SD. Yang dulu selalu membawa bekal dua bungkus roti sobek dari toko Pak Rawi-satu untuk dirinya, satu untuk Arno yang sering pura-pura kenyang.
“Kamu beda banget sekarang. Lebih kurus… lebih diem juga.”
Ia tertawa kecil, dan suaranya jernih seperti aliran air dari kran sekolah yang bocor.
Tapi Arno tahu-yang membuat dadanya sesak bukan karena kenangan, tapi karena rasa bersalah.
Sebab ketika Aini tumbuh menjadi perempuan yang utuh, ia tumbuh menjadi bayangan.
“Aku tadi lihat kamu dari seberang. Aku hampir nggak percaya. Tapi langkahmu masih sama. Kayak orang yang bingung, tapi yakin ke mana.”
Ia ingin tertawa. Tapi hanya senyum yang muncul.
Senyum yang tak tahu harus menjawab dengan kata atau diam.
“Kamu masih tinggal di sekitar sini?” tanya Aini, menata rambutnya yang tersibak angin.
Ia mengangguk pelan.
“Kos. Di belakang rumah Bu Lastri.”
“Bu Lastri?! Ya ampun… dia masih hidup? Dulu aku sering beli jenang sumsum sama dia! Katanya kalau sering beli nanti pinter matematika.”
Obrolan itu mengalir seperti air sumur yang ditimba hati-hati.
Tak ada pertanyaan tentang hidup kerasnya, tentang bajunya yang bau solar, atau kapalan di tangannya.
Aini hanya bicara… dan mendengar.
Dan di sela tawa itu, Arno merasa dirinya kembali menjadi manusia.
Bukan alat. Bukan makhluk malam. Tapi seseorang yang dilihat… tanpa kecurigaan.
—
Satu Langkah Kembali ke Dunia
Matahari makin turun, dan suara becak mulai bersahutan dengan suara lonceng sepeda. Tapi dunia Arno terasa lebih tenang dari biasanya.
“Aku sering duduk di alun-alun kecil belakang masjid Agung, jam empat atau lima. Bawa buku, kadang cuma lihat langit.”
Ia bicara santai, sambil menggoyang-goyang buku di tangannya. Lalu mengedipkan mata, seperti masa kecil dulu saat menantangnya main petak umpet pakai batu.
“Kalau kamu lewat… ya sapa ya. Jangan hilang kayak dulu.”
Ia mulai melangkah pergi. Tapi sebelum benar-benar menjauh, ia menoleh.
“Arno… seneng lihat kamu masih hidup.”
Kalimat itu, mungkin terdengar biasa. Tapi bagi seseorang yang setiap malam berdansa dengan kegelapan…
Itu cukup. Untuk bertahan satu kehidupan lagi.
—
Dan Ia Masih Duduk di Kursi Tua Itu
Tehnya sudah dingin.
Tapi ia belum menyentuhnya.
Angin sore membawa suara bedug dari masjid, teriakan anak-anak main bola, dan suara hatinya sendiri-yang lama tak ia dengarkan.
Ia masih tak tahu bagaimana menjelaskan siapa dirinya sekarang.
Masih belum tahu cara menjawab:
Tapi hari ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama…
Arno ingin jadi seseorang.
Bukan hanya “yang bertahan.”
Tapi yang pulang.
Ingatan yang Tak Selesai Dicuci Waktu
Angin sore mulai beringsut membawa bau gorengan dari gerobak seberang. Tapi bagi Arno, yang kini duduk diam di warung itu, yang datang justru bau lain-bau dari masa yang tak ingin ia kenang, tapi tak juga bisa ia kubur.
Masa saat ia bukan hanya kehilangan arah, tapi juga kehilangan dirinya sendiri.
—
Dulu, di Sudut yang Tidak Pernah Diceritakan
Sebelum dikenal sebagai Mas Ar, bahkan sebelum tubuhnya dihinggapi bayangan, Arno hanyalah anak muda tanpa tempat berpulang.
Lulus SMP tanpa pesta. Ibunya meninggal ketika ia masih remaja, dan ayahnya hanyut dalam sepi yang menyaru jadi amarah. Rumah itu perlahan menjadi sarang sunyi. Satu-satunya suara yang bertahan hanyalah siaran sandiwara dari radio tetangga, dan sesekali bentakan lelaki tua yang merasa hidupnya dikhianati oleh hari-hari.
Maka Arno pergi.
Bukan karena punya mimpi. Tapi karena tak sanggup lagi bertahan di ruang yang tak menyisakan ruang untuk bernafas.
Ia tidur di emperan toko, hidup dari upah memanggul barang dan memalak anak-anak yang lebih kecil. Preman kecil-kecilan-yang tumbuh bukan karena keberanian, tapi karena tak ada siapa pun yang akan bertanya kalau ia hilang.
“Pilihannya cuma dua,” katanya suatu hari pada diri sendiri,
“jadi binatang… atau dilindas binatang.”
Dan ia memilih jadi binatang.
—
Pertemuan di Bangunan Tua
Satu malam, setelah melempar botol ke arah pemilik toko karena upahnya dipotong, Arno berlari ke sebuah bangunan tua di pinggir pasar. Gedung itu dulunya ruang serbaguna, kini tinggal dinding kusam dan lantai berdebu. Tapi malam itu, ada cahaya dari pelita kecil di dalamnya.
Ia masuk, bukan untuk berteduh dari hujan. Tapi untuk bersembunyi dari suara yang mulai ramai memburunya.
Bajunya basah, tangannya masih gemetar, dan dadanya dingin seperti besi tua.
Di dalam, duduk seorang lelaki tua bertopi caping lusuh, tengah mengaduk minuman panas dalam termos denting.
Lelaki itu menoleh, menatapnya tanpa gentar, lalu berkata:
“Kalau kau lari dari orang lain, kau mungkin selamat. Tapi kalau kau lari dari diri sendiri… lama-lama kau lupa siapa yang kau tinggalkan.”
Arno tak menjawab. Ia hanya duduk di lantai yang dingin dan lembab. Matanya mulai basah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis bukan karena ditinju. Tapi karena kalimat itu tepat-dan tajam.
“Saya… bukan orang baik.”
“Saya… nggak tahu caranya kembali.”
Lelaki itu menyodorkan secangkir minuman. Hangat. Pelan. Seperti jawaban dari dunia yang terlalu lama dingin.
“Orang tak harus baik untuk berubah. Kadang cukup tahu kapan waktunya berhenti melukai.”
Malam itu, di antara suara tikus dan embun di dinding, Arno tidak mengubah hidupnya.
Tapi ia berhenti bersembunyi.
Dan itu sudah cukup untuk memulai sesuatu.
—
Pertobatan Tidak Pernah Datang Sekali
Hari-hari setelah itu bukan cerita mukjizat.
Ia masih harus memikul karung. Masih harus menahan amarah. Tapi ia mulai belajar menahan tangan sebelum mengayun. Belajar menghitung sampai sepuluh sebelum bicara. Belajar diam saat dihina. Belajar berkata “tidak” pada tawaran mudah yang berbau gelap.
Beberapa orang menolak mempekerjakannya. Beberapa tertawa saat melihat bajunya yang compang-camping minta kerja. Tapi Pak Sidik, pemilik Toko Sido Dadi, memberinya kesempatan.
“Kalau kamu pukul orang, kamu keluar. Tapi kalau kamu tahan… kamu boleh tinggal.”
Dan Arno bertahan. Berkali-kali. Bahkan saat upahnya dipotong. Bahkan saat rekan kerja mencibir.
Ia tahu: pertobatan bukan soal menjadi bersih seketika. Tapi tentang memegang tali agar tak jatuh ke lubang yang sama lagi.
—
Dan Malam Itu… Bayangan Mulai Muncul
Seminggu setelah ia berhenti menjadi preman, sesuatu muncul di dalam dirinya.
Sesuatu yang bukan suara. Bukan penglihatan. Tapi rasa. Seperti ada makhluk yang berdiri di belakang bahunya, mengawasi… bukan menghakimi, tapi juga bukan melindungi.
Malam itu, lelaki tua di bangunan reot itu datang lagi. Kali ini tak membawa minuman. Hanya selembar daun kering, yang ia tiup pelan dan jatuh di pangkuan Arno.
“Ada bagian dunia ini yang hanya bisa dijaga oleh mereka yang pernah jatuh ke titik tergelap.”
“Apa maksudnya?” tanya Arno.
“Ada bayangan yang memilihmu. Bukan untuk kuasa. Tapi untuk menebus sesuatu yang tak bisa ditebus dengan lari.”
Dan sejak malam itu, Arno tidak benar-benar sendiri.
Bayangan itu ada. Tidak menyatu, tapi melekat. Tidak bicara, tapi mendengar. Diam di siang hari. Bergerak saat gelap.
Namun meskipun kekuatan itu nyata, musuh terbesarnya tetap dirinya sendiri.
—
Teh Dingin, Tapi Doa Masih Hangat
Ia menatap gelas tehnya. Uapnya sudah hilang. Tapi ada sesuatu di dasar hati yang masih hangat-seperti percik api kecil yang tak pernah benar-benar padam.
Bayangan masih menempel di dirinya. Tapi malam ini, setelah bertemu Aini…
Arno merasa ada sesuatu yang lebih kuat dari kekuatan.
Lebih tajam dari amarah.
Lebih berat dari penebusan.
Pengakuan.
Bahwa ia pernah gagal. Pernah tersesat. Tapi masih bisa pulang.
Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama…
Ia percaya.
—
Nama yang Tak Hilang dari Kertas
Sore berganti petang. Warung mulai sepi. Arno baru saja menghabiskan teh manis yang kini hanya menyisakan ampas gula. Ia berdiri, merapikan ransel lusuhnya, lalu melangkah perlahan. Tapi kali ini bukan ke kos-kosan lembap itu. Langkahnya tidak punya arah-tapi hatinya tahu: ia ingin tahu lebih banyak tentang Aini.
Dan seolah dunia ikut bersekongkol dengan pikirannya, ia melihat sosok itu lagi. Duduk tenang di bangku taman dekat pos ronda, menulis cepat di buku tulis yang sudah lecek di sisi-sisinya. Sesekali menatap ke arah jalan raya.
Tak banyak yang berubah. Masih mengenakan blus lengan pendek dan rok span cokelat. Kini dengan jaket jeans tipis diikat di pinggang.
Arno sempat ragu memanggil. Tapi sebelum ia sempat bicara, Aini sudah menoleh.
“Tahu nggak… kamu masih jalan seperti dulu.” “Kayak orang yang belum tahu tujuannya, tapi tetap jalan karena nggak mau diam.”
Ia duduk di ujung bangku. Tak terlalu dekat. Tapi cukup untuk mendengar nada bicara.
“Kamu masih nulis tangan?” tanyanya, menatap halaman penuh coretan.
“Masih. Mesin ketik terlalu rapi.”
Aini lalu mengeluarkan koran. “Dwi Warna”, edisi pekan lalu. Di sudut kanan bawah halaman utama, tercetak kecil:
Oleh: Aini Prameswari
—
Tulisan yang Mencium Asap
“Ini kamu yang tulis?”
Arno menunjuk judul tajam di halaman depan:
“Riuh dalam Sunyi: Bayangan yang Berkeliaran di Balik Kota”
“Kisah nyata,” ujar Aini ringan. “Atau mungkin… setengah nyata. Sisanya insting.”
Tulisan itu menggambarkan kejadian-kejadian ganjil:
Preman pasar yang mendadak berhenti memalak.
Pencuri yang ditemukan tak sadarkan diri di teras rumahnya sendiri.
Anak-anak kecil yang mengaku melihat sosok hitam di antara pohon, hanya saat lampu mati.
Tak ada nama disebut. Tapi Aini menatap Arno sejenak, lalu kembali ke catatannya.
“Kamu percaya ada orang yang memilih diam… tapi sebenarnya menata ulang keadaan di belakang layar?”
Arno tak langsung menjawab.
“Kadang bukan soal percaya,” katanya akhirnya. “Tapi soal… jangan sampai kita menulis tentang sesuatu yang belum siap dibaca.”
“Justru karena itu aku tulis,” kata Aini, lembut tapi tegas. “Biar nanti… saat waktunya datang, orang-orang tidak kaget bahwa yang menjaga mereka bukan selalu yang berseragam.”
—
Pertanyaan yang Tidak Butuh Jawaban
Aini menutup bukunya, lalu berdiri.
“Aku di kantor jam delapan besok. Tapi jam lima pagi aku di alun-alun. Kalau kamu lewat… ya duduk aja. Aku nggak suka ngobrol sendirian, tapi juga nggak perlu selalu ditemani.”
Ia melangkah pergi. Tak menoleh. Tapi suaranya tetap tertinggal:
“Kota ini penuh dengan orang yang kita pikir biasa. Tapi siapa tahu… salah satu dari mereka sedang melindungi kita dari hal yang nggak kita lihat.”
Arno tidak menyahut. Tapi di dadanya, sesuatu terasa longgar. Seperti beban yang tak diangkat, tapi sedikit digeser dari tempatnya.
—
Catatan yang Tak Pernah Dikirim
Di meja redaksi “Dwi Warna”, Aini menatap satu paragraf yang belum ia serahkan untuk naik cetak.
Kalimat itu:
“Kadang, yang tak dikenal justru paling banyak berjasa.”
“Bukan karena ia ingin disembunyikan, tapi karena ada luka yang lebih penting dari pujian.”
Ia simpan paragraf itu. Tak ia kirim ke editor.
Belum. Belum waktunya.
—
Bab: Hari-Hari yang Sunyi
Beberapa hari berlalu sejak malam yang membakar lembah itu.
Kota Jogja kembali pada iramanya sendiri: suara becak yang pelan di pagi hari, hiruk-pikuk pasar Beringharjo, dan deretan angkringan yang mulai ramai saat senja turun.
Tak ada yang tahu tentang pertempuran di tempat jauh itu-di mana cahaya dan bayangan saling mengiris dalam diam.
Bagi orang-orang kota, hidup tetap bergulir dari pagi ke malam, dari warung ke rumah, dari tawa ke letih.
Dan di sela hiruk-pikuk itu, Arno berjalan perlahan melewati Jalan Malioboro yang berdebu sore. Langkahnya ringan, tidak tergesa.
Hari ini, tak ada suara Svarnavarna di kepalanya. Hening, untuk pertama kalinya. Seperti badai yang memilih tidur sejenak.
Ia mampir di kios buku bekas, membuka halaman demi halaman tanpa sungguh-sungguh membaca. Hanya membiarkan waktu lewat, seperti daun yang hanyut di selokan pinggir jalan.
—
Di Taman Sore Itu Lagi
Dan sore itu, seperti beberapa hari lalu, ia kembali ke taman kecil di sudut kota.
Tempat yang tenang, dengan suara burung gereja bertengger di kabel listrik, dan angin yang membawa bau tanah basah setelah gerimis pagi.
Aini sudah di sana, duduk di bangku yang sama, membuka buku tulisnya yang sudah penuh coretan-coretan kecil. Rambutnya dikuncir seadanya, wajahnya santai tanpa riasan berlebih.
Ia menoleh sambil tersenyum.
“Ternyata kamu beneran lewat.”
“Kukira kamu bakal kabur lagi kayak kemarin-kemarin.”
Arno tersenyum tipis. Kali ini tak ada getir. Hanya… damai.
“Hari ini nggak ada alasan buat kabur.”
“Dunia lagi anteng.”
Aini mengangguk pelan, memandang langit yang mulai berubah jingga.
“Kadang dunia tuh cuma anteng di permukaan. Dalemnya siapa yang tahu.”
“Tapi ya… nikmatin aja dulu, sebelum ribut lagi.”
Mereka duduk diam beberapa saat. Tak perlu bicara, karena kadang diam adalah bahasa paling ramah di antara dua orang yang sama-sama letih.
—
Percakapan yang Bukan Tentang Bahaya
Aini kemudian tertawa kecil, lalu berkata:
“Eh, kamu masih inget nggak… waktu kita SD, main layangan di kuburan Cokrodiningratan? Layanganmu nyangkut, terus kamu suruh aku yang panjat pohonnya. Aku pulang-pulang dicariin ibu gara-gara bajuku sobek.”
Arno mengerutkan dahi, lalu tertawa pelan.
“Itu karena kamu lebih ringan badannya. Logika sederhana.”
“Alasan pengecut,” balas Aini sambil melempar pandangan malas.
“Tapi ya… itu pertama kalinya aku sadar, hidup tuh nggak selalu adil. Yang suruh manjat, yang duduk santai, yang dapet layangan juga dia lagi.”
Arno menatapnya, senyumnya lebih hangat dari hari-hari sebelumnya.
“Ya… kadang yang cuma duduk santai juga paling sering jatuh duluan.”
Aini diam sebentar, menatapnya dengan tatapan yang lebih lembut. Seperti ingin berkata sesuatu, tapi urung.
—
Sore Itu Milik Mereka
Angin sore berhembus pelan.
Tak ada bayang-bayang Banaspati. Tak ada suara Svarnavarna.
Hanya dua orang tua yang lewat sambil berjalan pelan, dan suara lonceng sepeda anak-anak yang baru pulang ngaji.
Di hari itu, Arno merasa…
Mungkin, untuk sementara, tidak apa-apa jadi orang biasa.
Mungkin, untuk sementara, dunia tak perlu diselamatkan.
Cukup didengarkan, cukup dilihat, cukup ditemani.
Dan dalam diamnya, ia tahu:
Pertempuran belum selesai. Bahaya belum benar-benar hilang.
Tapi hari ini…
Hari ini ia beristirahat.
—




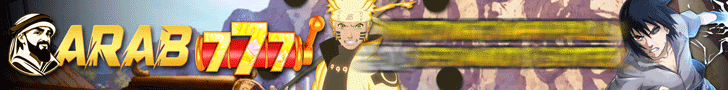
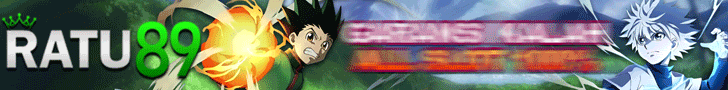



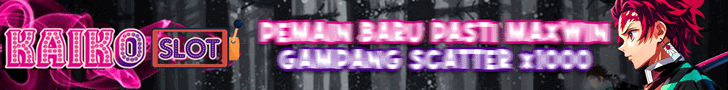

Comment
Wow disini tersedia novel juga kah
Kalo ada yang pengen nitip Up novel boleh
Ambil ambil dari WN min. Atau gak enak yg dah ada manhwa nya biar bisa langsung lanjut reader.